PENGANTAR: ini tulisan keempat dan terakhir saya tentang Klara Akustia, semoga. Sampai suatu saat sebuah "puzzle" tentangnya seutuhnya saya terakan dalam sebuah buku. Tulisan ini semata dorongan hati untuk menanggapi sebuah tulisan dari seorang sastrawan besar yang sangat subjektif, dengan penutup yang membikin miris. Tulisan itu dimuat di sebuah suratkabar Pikiran Rakyat, yang sayang tak memuat tanggapan ini. (Catatan susulan: Tulisan ini akhirnya dimuat Pikiran Rakyat, 10 Maret 2007, seminggu setelah pemuatan tanggapan Martin Aleida)
BELUM 40 hari. Timbunan tanah di pemakaman masih belum kering; menyisakan bunga-bunga bertaburan, juga karangan bunga dari “seorang lawan” Goenawan Mohamad. Belum ada “rumah” permanen bagi yang pergi, juga papan nama. Masih ada sisa duka dan kesedihan, serta kenangan yang mungkin tak sepenuhnya utuh. Sastrawan itu, A.S. Dharta atau Klara Akustia (dua dari sekian nama penanya) sudah berpulang 7 Februari 2007, sekitar pukul 05.30 di rumahnya di Cianjur, karena sakit paru-paru dan komplikasi jantung. Dia dimakamkan di pemakaman keluarga, tak jauh dari rumahnya.
Sekali ini saya menengok kamarnya. Gelap. Pengap. Lemari penuh buku. Koran-koran bertumpukan. Di dalam sebuah kardus, saya menemukan kertas usang seribuan halaman: Kamus Bahasa Sunda-Indonesia, yang dia bikin untuk menyambut permintaan Atje Bastaman dan Moh. Kurdi alias Syarief Amin –keduanya tokoh Sunda dan pernah bekerja di Percetakan Sumur Bandung. Inilah kerja terakhir Dharta yang belum usai. Kelak, keluarga berharap, ada yang berkenan meneruskan enam abjad terakhir dan menerbitkannya.
Dalam kamarnya, masih ada surat dari Ajip Rosidi, tentang penerbitan Ensiklopedia Sunda. Sebuah buku tebal-fotokopian, Kantjungkundang, tergeletak di meja. Dalam buku ini, ada sejumlah karya Dharta –di luar buku itu, saya juga menemukan sajak-sajaknya dalam bahasa Sunda. Semestinya pembicaraan tentang karya dan sosok sastrawan Sunda inilah yang kita harapkan dari Ajip Rosidi, dalam pembicaraan soal “Akhir Hidup Pengarang Lekra” di Pikiran Rakyat, 17 Februari 2007. Mari bicara karya, ketimbang pengalaman personal yang tak bisa dibantah si empunya nama. Dari situlah perjalanan kreatif penulis, pengalaman hidup yang menempanya, serta pemikirannya akan lebih memperkaya bahasa dan kesusastraan Sunda.
Ada juga surat pribadi wartawan-cum-sastrawan Sunda Rachamatullah Ading Affandie (biasa disingkat R.A.F.) tertanggal 8 Januari 2001. Isi suratnya dalam bahasa Sunda yang indah, agak bersajak. Isinya hangat, penuh persahabatan, dan mencerminkan kerinduan untuk bertemu. Menurut R.A.F., Dharta-lah yang kali pertama mendeklamasikan sajak (bebas) Sunda. Sajak-sajak Kis. Ws, Afiatin, dan Kusnadi pernah dideklamasikannya dengan gaya modern.
R.A.F. juga menulis, dalam perkembangan bahasa dan sastra Sunda setelah perang, Dharta tergolong orang yang mencintai bahasa dan sastra Sunda. Ia sejajar dengan Achdiat Kartamihardja, Utuy Tatang Sontani, Rusman Sutiasumarga, Rustandi, hingga Ajip Rosidi, yang sekarang menjadi “dewa” dan memegang kiblat sastra Sunda. “Tah ‘mimitina mah’ ka rengrengan sastra Indonesia eta (dina basa & sastra Sunda) dumukna A.S. Dharta teh. Ngan henteu nerus Dharta mah, ‘titik berat” aktivitasna leuwih museur dina pulitik,” demikian bunyi surat R.A.F.
A.S. DHARTA memang akhirnya “berpolitik” tapi setelah melewati proses perjalanan panjang. Ketika remaja, dia turun ke medan pertempuran. Usai kemerdekaan, tak ada hari tanpa kerja. Menjadi wartawan Harian Boeroeh di Yogya, memimpin sejumlah serikat buruh, ikut dalam organisasi pemuda dan buruh internasional, PEN Club-Indonesia, serta sejumlah lembaga kebudayaan. “Dalam kerja itu kita melakukan genesis, melahirkan kita kembali, lieber create man,” ujarnya.
Semuanya memperkaya pengalaman batinnya sebagai sastrawan dan anak zamannya –hal ini juga semestinya dibicarakan Ajip Rosidi. Karya-karyanya bejibun. Bentuknya sajak, cerita pendek, catatan perjalanan, esai, kritik sastra. Bukunya memang satu: Rangsang Detik. Selebihnya masuk dalam antologi puisi bersama sastrawan lainnya. Ada juga naskah drama Saidjah dan Adinda, adaptasi dari novel Multatuli Max Havelaar terjemahan Bakrie Siregar, yang pernah dipentaskan pada 1950-an. Novelnya, Keringat, keburu dimusnahkah pemerintah militer Jepang. Cerita bersambungnya antara lain Tirtonadi Mengaku. Inilah sejumlah karyanya yang bisa dibedah, dikritik, tanpa harus mendengar pembelaan si penulis –ketika sebuah karya terbit, ia menjadi milik pembaca atau masyarakat.
Dharta sudah menulis sajak semasa Jepang. Tapi namanya makin dikenal sejak esainya pada 1949, “Angkatan 45 Sudah Mampus”, menggemparkan kesusastraan Indonesia. Sejumlah sastrawan ikut menanggapinya, antara lain Sugiarti, Sitor Situmorang, Mochtar Lubis, Anas Maruf, Achdiat Karta Mihardja, M.S. Azhar, Asrul Sani, dan HB Jassin.
“Seorang sastrawan tidak mungkin dan tidak bisa berdiri ‘netral’, terlepas dari pengaruh lingkungannya,” tulisnya dalam “Kepada Seniman Universal”, menanggapi tulisan kritikus sastra HB Jassin yang memajukan konsep humanisme universal. “Antara Bumi dan Langit” adalah sajak Dharta yang ditujukan untuk HB Jassin: Kita berdua sama-sama tidak bebas / kau terikat pada dirimu / aku pada Manusia dan zaman kini.
Realisme sosialis atau realisme aktif menjadi pegangan Dharta. Ia juga dipegang, tapi tidak dipaksakan, oleh sastrawan dan seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang secara salah kaprah dianggap sebagai organ Partai Komunis Indonesia (PKI). Dharta pendiri Lekra, bersama M.S. Azhar dan Njoto, pada 17 Agustus 1950. Dharta pula yang ditunjuk sebagai sekretaris jenderal (Sekjen) dan redaktur Zaman Baru, penerbitan resmi milik Lekra. Pada 1958, jabatannya sebagai Sekjen dicabut karena “kemesuman borjuis” –istilah Dharta yang ingin menyadarkan perlunya otokritik, bukan hanya kritik. Juga keanggotaannya di Konstituante –masuk sebagai calon-tak-berpartai lewat PKI.
Tapi, oleh teman-temannya, A.S. Dharta dinilai sebagai orang yang sulit dicari gantinya. Dia jenis manusia yang tak bisa diperintah. Pendiriannya teguh. Dia membangunkan dan mempengaruhi sastrawan era 1950-an. Pergaulannya luas tapi dia tak henti-hentinya mencari generasi muda terbaik. Pramoedya Ananta Toer, novelis tetralogi Bumi Manusia, satu di antaranya.
A.S. DHARTA bukan orang yang berhenti di satu jalan. Dia selalu bergerak. Tapi Bandung selalu menarik hatinya. Pada 1951, dia menjadi pembicara dalam Kongres Kebudayaan Indonesia II, bersanding dengan Hamka. Sebagai Sekjen Lekra, dia mendorong pembentukan Lingkaran Sastra Bandung. Sementara sebagai anggota Konstituante, dia mendorong otonomi daerah dalam konstitusi yang sedang digodok. Untuk Bandung pula, dia menjadi anggota Komite Perdamaian, semacam “kabinet pribadi” Soekarno, untuk menyukseskan Konferensi Asia Afrika. Pada 1960-an, dia mendirikan Universitas Kesenian Rakyat, yang menurut Presiden Soekarno, dalam peresmiannya, adalah universitas pertama di Indonesia dalam bidang humaniora.
Tapi peristiwa G30S mengakhiri semua aktivitasnya. Dia masuk penjara Kebonwaru, Bandung, dan keluar pada 1978. Sejak itu, kesehatan terganggu. Orde Baru memasungnya, juga jutaan orang Indonesia. Orde Baru pula yang menanamkan stigma dalam benak masyarakat. Sejak reformasi, stigma itu perlahan dikikis, meski tak sepenuhnya berhasil. Di sana-sini masih ada spanduk “Awas bahaya laten komunis”, masih ada yang menganggap seorang komunis tak ber-Tuhan. Kita prihatin, stigma itu seolah dihidupkan lagi oleh Ajip Rosidi, seorang budayawan. Rasanya tepat apa yang ditorehkannya, di pintu kamarnya, pada secarik kertas: “Awas! Bahaya kedangkalan logika berpikir”.
A.S. Dharta sudah berpulang, dan saya percaya sudah tersenyum manis di sisi Sang Kekasih, meski tanpa iringan ucapan selamat jalan dari “seorang kawan”.*
------------------------------------------------
Pikiran Rakyat, 3 Maret 2007.
Ah… Ajip Rosidi
Oleh Martin Aleida
SAYA mengenal Ajip Rosidi sebagai sastrawan yang baik hati. Atau kalau ingin menggambarkannya dengan kata-kata yang mewah, maka dia adalah seorang budayawan yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Ketika sastrawan I. S. Poeradisastra (nama lain dari Boejoeng Saleh) dibebaskan, setelah menjalani penahanan sewenang-wenang tanpa alasan selama belasan tahun, termasuk dibuang ke Buru, Ajip memberikan rumah ekstranya di daerah Pasar Minggu untuk dihuni lawan politik namun teman sedaerahnya itu.
Saya kira kebaikan hati seperti itu merupakan keberanian yang tidak dimiliki oleh banyak orang, kecuali siap menanggung risiko berurusan dengan penguasa yang fasistis pada waktu itu.
Namun, Ajip yang saya kagumi mendadak sontak menjadi sosok yang tidak peka, menistakan adat kebiasaan, begitu saya membaca obituari yang ditulisnya mengenai A.S. Dharta, "Akhir Hidup Pengarang Lekra," (Khazanah, Pikiran Rakyat, 17 Februari 2007). Saya tak habis pikir, kesalahan apa yang telah diperbuat Dharta selama hidupnya, sehingga Ajip Rosidi merasa layak mengiringi jenazah penyair dan pendiri Lekra itu ke alam baka dengan cuci maki yang begitu bersemangat.
Saya tergugah dengan keindonesiaan Ajip yang dengan ulet, dan daya tahan yang susah dicari duanya, dalam menjunjung tinggi kebudayaan Sunda, antara lain dengan memprakarsai hadiah sastra Rancage, yang belakangan tidak hanya diberikan kepada mereka yang menghasilkan karya penting dalam bahasa Sunda, tetapi juga dalam bahasa Jawa dan Bali. Wah, tiba-tiba saya terperanjat begitu membaca obituari yang ditulisnya mengenai sastrawan berdarah Cianjur tersebut. "… ternyata Dharta sendiri yang mendahului meninggalkan jasadnya di Cibeber --tapi mungkin sebagai komunis dia tak percaya akan adanya alam di balik kematian-- sehingga dapatkah saya mengucapkan selamat jalan kepadanya?" Sarkasme untuk sebuah kematian. Layakkah? Tetapi, demikianlah Ajip menyudahi tulisannya.
Ajip adalah anggota Akademi Jakarta. Secara berseloroh saya ingin bertanya, apakah menjadi anggota "Akademi" tidak cukup bagi Ajip untuk memahami perbedaan antara "komunis" dan ateis? Filsuf Inggris termasyhur, Bertrand Russell, yang menulis "Why I Am Not A Christian," secara terbuka menyatakan dirinya ateis. Tetapi, dia adalah seorang yang antikomunis sampai ke tulang sumsum. Sesungguhnya akan merendahkan derajat Ajip kalau masih perlu dijelaskan bahwa seorang komunis belum tentu ateis, karena keduanya jelas berbeda. Lagi pula, ruangan yang terhormat ini tidak pantas dijadikan arena untuk menjelaskan apa itu komunis, kecuali mau mengambil risiko karena ada legislasi yang melarangnya. Zaman sudah berubah, namun ternyata taktik kaum fasis untuk menaklukkan musuh-musuhnya masih bergema.
Saya jadi bertanya-tanya, kebudayaan Sunda yang "adiluhung" seperti apa yang ingin dijunjung-dimuliakan oleh Ajip, sehingga dia ragu dan tak sampai hati untuk mengucapkan selamat jalan kepada sesama umat yang sedang diusung menuju pembuktian tentang kebesaran-Nya. Pantaskah mengatakan itu dengan memakzulkan kenyataan bahwa rumah Dharta, yang dikelilingi pematang sawah, adalah gelanggang pertemuan warga dan pusat pengajian yang ramah bagi warga sekitar? Juga kancah diskusi yang hangat buat para pemuda yang memutuskan untuk menyelesaikan hubungan mereka de-ngan Tuhan secara sendiri-sendiri dan memilih berdebat dengan orang yang sudah uzur tersebut tentang politik, tentang kesusastraan. Lagi pula, di mana Tuhan di dalam hati Dharta, siapa yang tahu…?
Ajip jumpalitan, kutip sana-sini, bongkar sana bongkar sini, hanya untuk membikin lukisan gelap tentang seseorang yang sedang menghadap Khaliknya. Seperti orang pusing tujuh keliling mencari tahu siapa gerangan nama sebenarnya A.S. Dharta. Dan sayang, tak sedikit pun ada usahanya untuk menyaksikan lingkungan hidup Dharta. Ketika diundang untuk menjenguk Dharta, dengan mudah dia cuma bilang: ".. di Cibeber (yang) letaknya di luar jalur perjalanan saya sehingga kecil kemungkinan saya dapat menemuinya." Begitu teganya! Ya, Dusun Cibeber, di Cianjur, memang bukan lintasan hidup Ajip yang menikmati hari tuanya di Magelang, Jawa Tengah. Tetapi, Cibeber toh bukan Christmas Island, jauh dari Pantai Palabuhanratu, harus mengarungi samudra kalau mau ke sana.
Tanpa periksa dengan saksama, sehina macam apakah Dharta sehingga dalam kematiannya ini sang istri, anak, dan cucu-cucunya yang belum kering airmata dukanya harus menanggung malu lewat kata-kata yang diumbar oleh budayawan kaliber internasional asal Jawa Barat itu? Mereka selayaknya mengenang Dharta, sang suami, ayah, dan kakek sebagai seorang yang ikut membesarkan dan menjaga mereka, dan bukan sebagai seorang Don Juan Tukang Selingkuh. Maaf, keadiluhungan budaya macam apa ini, Kang …, eh, Bung!
Begitu bersemangatnya Ajip memojokkan Dharta sehingga (dengan tak sengaja) dia membuat kesalahan ketika menyebutkan kumpulan sajak Klara Akustia Rangsang Detik diterbitkan oleh penerbit Lekra. Padahal buku itu terletak menunggu jamahan tangannya, karena dia tersimpan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pusat dokumentasi sastra yang ikut didirikan Ajip. Buku tersebut bukan Lekra yang menerbitkannya tetapi Yayasan Pembaruan, tahun 1957.
Sebenarnya, dari orang sebesar Ajip saya mengharapkan tinjauan yang serius mengenai karya Dharta. Sekritis apa pun tinjauan itu asal dilandasi ulasan-ulasan yang meyakinkan, layaknya sebagaimana yang dilakukan Soebagyo Sastrowardoyo dalam Bakat Alam dan Intelektualisme yang diterbitkan Pustaka Jawa, pimpinan Ajip Rosidi sendiri, tahun 1971.
"Sajak-sajak perlawanan Taufiq Ismail dan penyair-penyair segenerasi tidak lebih tinggi nilai sastranya daripada yang dihasilkan oleh Klara Akustia dan kawan-kawan separtainya," ujar Soebagyo. Dalam kesempatan lain, kritikus dan penyair itu juga menyimpulkan bahwa dalam sajak-sajak Taufiq Ismail dan kawan-kawan pada tahun 1966 ditemukan "paralelisme" dengan puisi para penyair Lekra, seperti A.S. Dharta (Klara Akustia), Hadi, Rumambi, Sudisman, F.L. Risakotta maupun Sobron Aidit. Paralelisme! Cap untuk teman, begitulah. Untuk tidak menyatakan epigonisme, karena paralelisme hanya mungkin kalau kedua pihak berada dalam tempat dan waktu yang setara dan sebangun.
Agaknya obituari tentang A.S. Dharta itu ditulis dalam suasana terkenang masa lalu dan dalam keadaan terburu-buru, asal jadi. Karena Ajip sedang sibuk-sibuknya menyusun memoir untuk ulang tahunnya yang ke-70 tahun depan. Semoga beliau terhindar dari kesalahan dan kesilapan, dan kita menunggu memoir itu sebagai sesuatu yang akan memperkaya khazanah sastra kita. Di mana kaliber dan posisi Ajip Rosidi sebagai seorang budayawan tak perlu disangsikan lagi adanya.*
Penulis, Sastrawan, tinggal di Jakarta.
------------------------------------------------
Pikiran Rakyat, Khazanah, Sabtu 17 Februari 2007
A.S. Dharta (1923-2007)
Akhir Hidup Pengarang Lekra
Oleh Ajip Rosidi
PADA dasarnya A. S. Dharta itu seorang romantis. Hal itu tampak di antaranya dari nama-nama pena yang digunakannya. Pada masa revolusi, ketika dia mulai menulis sajak dalam majalah Gelombang Zaman yang terbit di Garut dipimpin oleh Achdiat K. Mihardja dengan Tatang Sastrawiria, dia menggunakan nama Kelana Asmara. Kita tahulah kira-kira orangnya bagaimana kalau mempergunakan nama seperti itu. Entah Kelana yang mencari Asmara, entah Asmara yang berkelana. Kemudian dia gunakan juga nama samaran Yogaswara. Seperti diketahui Yogaswara adalah tokoh utama dalam roman R. Memed Satrahadiprawira yang berjudul Mantri Jero. Agaknya dia kagum sekali kepada tokoh satria muda yang jujur berpegang kepada kebenaran sehingga berani menyelam di Leuwi Panereban untuk membuktikan bahwa dirinya bersih, tidak seperti yang difitnahkan orang kepadanya.
Saya kira dia menggunakan nama samaran A.S. Dharta menjelang akhir tahun 1940-an, ketika dia banyak menulis dalam majalah Spektra yang terbit di Jakarta dan juga dipimpin oleh Achdiat K. Mihardja. Pada waktu itu dia di antaranya menyerang para pengarang ‘45 dengan mengatakan bahwa Angkatan ‘45 sudah mampus, sehingga timbul polemik yang ramai. Selanjutnya nama A.S. Dharta itulah yang dia gunakan sebagai nama sehari-hari, walaupun dia juga kalau menulis mempergunakan nama samaran baru antaranya Klara Akustia. Asrul Sani pernah mengatakan bahwa nama Klara Akustia itu diambil Dharta dari nama Hongaria. Keterangan Asrul itu keliru. Nama Klara Akustia digunakan setelah Dharta ditinggalkan lari oleh istrinya yang sehari-hari dia sebut “Klara”, walaupun namanya sebenarnya bukan demikian. Istrinya itu melarikan diri dengan seorang serdadu KNIL kabur ke negerinya.
Untuk membuktikan bahwa walaupun ditinggalkan lari dan dikhianati oleh istrinya, dia tetap setia, maka digunakannya nama Klara Akus(e)tia.
Menurut Ramadhan K.H. yang pernah bersama-sama dengan dia di HIS Cianjur, nama panggilannya sehari-hari adalah Rodji. Mungkin lengkapnya Fachrurodji. Kalau benar, artinya dia berasal dari lingkungan keluarga Islam yang cukup kental karena nama itu jelas nama Islam. Tetapi ketika Boejoeng Saleh menulis “Perkembangan Kesusasteraan Indonesia” yang dimuat dalam Almanak Seni 1957 bahwa namanya yang sebenarnya adalah Rodji, Dharta naik pitam dan mengancam akan menyeret Boejoeng ke pengadilan. Sayang, Boejoeng tidak sampai benar-benar diseret ke pengadilan sehingga sampai sekarang kita belum tahu siapa nama A.S. Dharta sebenarnya. Mungkin harus ditanyakan kepada keluarga atau sahabatnya sebaya di Cibeber yang kemungkinan besar sudah punah semua, karena ketika meninggal tanggal 7 Februari 2007, usia Dharta hampir 84 tahun, karena dia lahir di Cibeber, Cianjur tanggal 7 Maret 1923. Tampaknya akan sulit mencari kerabat atau sahabatnya yang usianya lebih tua daripadanya atau sebaya dengan dia, yang masih hidup dan ingat akan namanya yang sebenarnya.
Tapi what’s in a name, kata Shakespeare. Dia sendiri lebih dikenal sebagai A.S. Dharta. Nama-nama yang lain hanya dia gunakan sebagai nama pena belaka. Yang dia gunakan sebagai nama pengarang bukunya yang hanya satu yaitu kumpulan sajak Rangsang Detik adalah Klara Akustia. Buku itu diterbitkan oleh penerbit Lekra tahun 1957.
PADA tahun 1949 atau 1950, Dharta bersama dengan beberapa seniman dan pengarang lain (di antaranya Achdiat K. Mihardja dan H. B. Jassin) di rumah sahabatnya, M.S. Azhar di Jalan Siliwangi simpangan kecil dari Jalan Dr. Wahidin Jakarta, mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Lembaga Kebudayaan Rakyat yang kemudian lebih terkenal dengan singkatannya, Lekra. Salah seorang yang hadir pada waktu pembentukan organisasi tersebut adalah Njoto, tokoh yang bersama Aidit menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah pemberontakan Madiun. Tetapi pada waktu itu tampaknya Njoto belum banyak dikenal, sehingga orang-orang seperti Achdiat dan Jassin tidak memerhatikannya. Dan mereka berdua tidak turut menyusun Mukadimah Lekra yang disahkan pada bulan Agustus 1950.
Dharta dalam organisasi tersebut diangkat menjadi sekjennya. Seperti diketahui, kedudukan sekjen dalam organisasi kiri dianggap sebagai yang terpenting. Kedudukan itu dipegangnya terus sampai tahun 1959. Pada pemilu yang pertama diadakan di Indonesia (1955), Dharta dicalonkan sebagai anggota konstituante oleh PKI dan terpilih. Maka dia duduk sebagai anggota lembaga yang bertugas menyusun UUD baru itu. Tapi setahun sebelum lembaga itu dibubarkan oleh Presiden Sukarno yang didukung oleh Mayjen A.H. Nasution (Angkatan Darat), Dharta dipecat oleh partainya karena ketahuan bahwa dia berselingkuh dengan wanita yang bersuami. Pada waktu itu ada dua seniman anggota perwakilan PKI yang dipecat oleh partai karena tuduhan yang sama: berselingkuh. Selain Dharta yang dipecat dari keanggotaannya di konstituante, pelukis S. Sudjojono juga dipecat dari keanggotaannya di DPR. Sudjojono juga dituduh berselingkuh dengan wanita yang masih menjadi istri orang. Tapi berlainan dengan Sudjojono yang menerima pemecatan itu dan kemudian menikah dengan wanita itu setelah bercerai dari suaminya, Dharta menyatakan menyesal atas perbuatannya dan dia meminta ampun kepada partai, di antaranya dia menerima menjadi kader kembali. Niscaya kedudukan kader itu lebih rendah dari calon anggota. Sebagai tanda bahwa dia benar-benar menyesal, dia harus mengirimkan surat pernyataan menyesalnya entah kepada berapa puluh orang. Saya pernah ikut membaca surat penyesalannya itu yang dikirimkan kepada Achdiat K. Mihardja. Waktu kami membicarakan surat itu setelah membacanya, saya menyatakan kepada Achdiat bahwa saya tidak mengerti bagaimana orang seperti Dharta sampai mau menulis surat yang menghinakan dirinya seperti itu hanya karena mau diterima kembali di lingkungan PKI. Menurut Achdiat, buat orang komunis, diangkat menjadi anggota itu merupakan kehormatan. Oleh karena itu, ada seniman yang kami kenal juga (dia sebut namanya), ketika dinyatakan bahwa dia diterima (atau diangkat) sebagai anggota PKI setelah menjadi calon anggota beberapa lama, dia menangis karena hatinya gembira.
Saya sendiri sejak itu tidak bisa menaruh respek kepada Dharta. Saya bertemu dengan dia terakhir kira-kira bulan November 1965 setelah Gestapu. Ketika itu orang PKI dan Lekra belum ditangkapi, tetapi harus melapor di kantor polisi setiap minggu. Dharta baru selesai melapor di kantor polisi yang ketika itu bertempat di ujung utara Jalan Braga bertentangan dengan Gedung BI. Dia mau pulang ke arah Jalan Banceuy, sementara saya bersama dengan dua orang redaktur Madjalah Sunda yang lain baru pulang dari percetakan Ganaco di Jalan Gereja setelah melewati viaduck mau naik ke arah Jalan Braga. Ketika itu Madjalah Sunda yang saya pimpin dicetak di percetakan Ganaco. Isi Madjalah Sunda banyak mengkritik kaum komunis dan setelah terjadi Gestapu terang-terangan mendukung suara yang mendesak Presiden Sukarno agar membubarkan PKI.
Begitu melihat saya, Dharta berhenti dan mengajak berbicara.
“Sekarang Bung yang menang,” katanya. Dia selalu berbicara bahasa Indonesia walaupun dia juga menulis karya sastra dalam bahasa Sunda. Dia selalu memanggil Bung kepada saya. “Karena itu Bung harus menolong saya.”
“Menolong apa?” saya bertanya.
“Saya perlu uang. Bung kasihlah saya uang.” Dharta memang cenderung suka meminta uang kalau bertemu walaupun sebenarnya kami tidak begitu akrab.
“Kalau Saudara kalah bukan berarti saya yang menang,” jawab saya. “Dan kalaupun saya yang menang, belum berarti saya punya uang. Dan kalaupun saya punya uang, pasti saya tidak akan memberikannya kepada Saudara, apalagi di tengah jalan begini. Kalau ada yang menyaksikan saya memberikan uang kepada Saudara, saya akan dilaporkan bahwa saya membantu kaum pemberontak.”
Seingat saya, Dharta tidak memberi jawaban dan saya segera berjalan menjauhinya. Setelah berada dalam penjara Kebonwaru dia juga saya dengar pernah mengirim surat kepada Kang Atje Bastaman meminta uang sehingga Kang Atje ketakutan dan meminta nasihat kepada Kang Koerdie. Baik Kang Atje maupun Kang Koerdie adalah kenalannya yang cukup akrab.
Pada tahun 1976, dia dibebaskan dari tahanan dan tinggal di kampung kelahirannya di Cibeber, Cianjur. Ketika menyusun Ensiklopedi Sunda saya pernah menelefonnya meminta keterangan tentang Barmara untuk kepentingan penyusunan ensiklopedia, tapi dia menolak memberi keterangan karena dia ingin mendapat honorarium dari sajak-sajaknya yang dimuat dalam Kanjutkundang, padahal begitu Kanjutkundang terbit (1963) saya langsung mengirimkan honorarium kepada semua pengarang yang karangannya dimuat di dalamnya, termasuk kepada Dharta.
Kira-kira sebulan yang lalu saya ditelefon oleh anaknya yang perempuan yang memberitahukan bahwa ayahnya ingin saya jenguk di Cibeber, tapi dia sendiri sudah mulai pikun. Cibeber letaknya di luar jalur perjalanan saya sehingga kecil kemungkinan saya dapat memenuhinya. Saya tidak berani berjanji.
Tapi ternyata Dharta sendiri yang mendahului meninggalkan jasadnya di Cibeber --tapi mungkin sebagai komunis dia tidak percaya akan adanya alam di balik kematian-- sehingga dapatkah saya mengucapkan selamat jalan kepadanya?*
Penulis, Budayawan.
Monday, February 26, 2007
Selamat Jalan Sastrawan Sunda
at
7:40 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


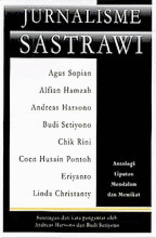


9 comments:
Mas buset, ni arif. mana tuh bagian akhir yang menghantam penulis subyektif itu! kok kepotong?? wah...
Arief, saya menghargai Ajip sebagai sastrawan. Saya pikir di bagian akhir saya sudah sedikit menghantam soal stigma. Dan kalau jeli, coba lihat bagian awal dan akhir, antara "lawan" dan "kawan".
Selebihnya, saya tak mau masuk ke soal filsafat, atau mengomentari apa yang ditulis Ajip. Ada data di kantong tapi minim konfirmasi, makanya disimpan aja deh. Thanks
lo, dimuat tulisan mas kan dimuat di khazanah, pikiran rakyat, sabtu, 10 maret?
Thanks, Udo. Tulisan ini memang akhirnya dimuat di PR, tiga minggu kemudian sejak pengiriman. Tapi ketimbang membingungkan, saya tambah catatan susulan di pengantar soal pemuatan naskah ini.
Sebagai bagian dari zaman yang berselisih jauh dengan para tetua itu, saya kadang merasa jengah menyaksikan luka lama yang sepertinya ingin dijejalkan para tetua itu. Negeri ini memang bukan sebuah meja makan yang rapi.karena itulah saya ikuti polemik para di Pikiran Rakyat dengan setengah ingin tahhu dan separuhnya lagi menahan jengkel. hehehe... salam!
salam kenal mas...bac2 sebentar
Liezmaya,
Salam kenal juga. Selamat membaca
Ajip Rosidi humanis? Dengan gaya pembantaiannya kepada kawan-kawannya yang sudah almarhum, kata tersebut sama sekali tidak tepat. Dalam buku 70 tahunnya dia dengan vulgar menguliti kawan sekaligus lawannya secara tidak beradab, dilengkapi dengan fitnah. Saya sekali memang....Farchad Poeradisastra
Farchad Poeradisastra,
Sayang memang, yang tua tak pernah mengajarkan kearifan bagi yang muda.
BTW, nama belakang Anda tidak begitu asing bagi sayang. Thanks menengok "rumah" ini.
Post a Comment