DAVID S. Broeder adalah wartawan-cum-kolomnis yang pernah bekerja buat The Washington Post dan peraih hadiah Pulitzer, hadiah prestisius bagi karya jurnalistik yang punya pengaruh luas. Pada 1992, bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Berita Di Balik Berita. Ini buku yang bagus tentang bagaimana wartawan menyikapi peliputan politik. Broeder memang seringkali meliput di Gedung Putih dan tahu bagaimana para politisi, dan juga presiden Amerika Serikat, menghadapi situasi sulit menjelang pemilihan.
Broeder dengan sangat jujur dan kritis menuliskan berita di balik berita mengenai kampanye pemilihan. Dia membedah kompleksitas strategi kampanye, sisi manusiawi seorang kandidat dalam menghadapi serangan-serangan kandidat lainnya, dan sebagainya. Di dalamnya diulas pula bagaimana sepak terjang tim kampanye, peranan (lembaga) polling, perilaku kandidat selama pemilihan, dan terutama sekali bagaimana korupsi dalam jurnalisme terjadi –dalam bahasa Broeder disebut sebagai jurnalisme klik, komplotan atau kelompok–, dan bagaimana wartawan sering mengalami kesulitan mencari jalan keluar.
Dia menghapus sebagian mitos penyampaian berita untuk melihat jurnalisme modern secara lebih realistis dan kritis. Menurutnya, wartawan sering salah menilai seorang tokoh, keliru melihat alur cerita, bahkan meski kadang fakta-fakta terlihat jelas tapi wartawan masih bisa tersesat karena salah memahami atau salah menilai konteks di mana fakta-fakta itu terdapat. Dengan kata lain, wartawan juga manusia, bisa salah.
Di Indonesia buku semacam itu atau liputan media kurang melihat segala aspek yang berperan dalam sebuah peristiwa politik. Tokoh politik cenderung digambarkan secara permukaan. Wartawan dianggap sebagai “orang suci”. Peristiwanya sering lepas dari konteks, tak bisa melihat jauh ke dalam kenapa peristiwa itu terjadi. Bahkan, di era persaingan media yang ketat ini, wartawan seolah jadi penyambung lidah politikus, gandrung dengan “talking news”.
Di belahan dunia manapun, televisi punya pengaruh besar bagi perubahan media, juga politik. Adanya televisi telah mengubah pola kampanye. Jika sebelumnya seorang kandidat mempersiapkan pidato kampanye yang panjang dan bisa enjoy dengan wartawan, maka kini dia harus siap dengan ucapan-ucapan singkat, dengan penampilan elegan di depan kamera. Tak mau kalah, wartawan media cetak kemudian terjebak pada perburuan berita model bergini. Sampai kemudian muncul istilah “jurnalisme pacuan kuda” yang hanya menekankan strategi dan taktik mendapatkan berita, tapi meremehkan masalah pokoknya, substansinya, dan tidak mempertimbangkan secara serius kualifikasi calon.
Dalam pemilihan umum, menyingkap kualifikasi calon bisa mudah bisa susah. Ini era komunikasi modern, yang segala sesuatunya dikemas mengikuti hukum budaya massa yang lebih menekankan aspek hiburan. Jangan kaget jika berita politik di media seolah jadi drama. Ada kemenangan, ada kepedihan. Kandidat politik main bola bisa jadi berita menarik. Kandidat “dianiaya” kandidat lain jadi berita. Padahal jiwa komunikasi di manapun adalah informasi. Seberapa media punya kesadaran itu, dengan melihat kampanye tidak hanya permukaannya? Menelisik lebih jauh kampanye di balik kampanye.
Kampanye di balik kampanye? Ya, karena apa yang disebut sebagai kampanye seringkali dimaknai secara sempit. Kita punya pengalaman pada Pemilu 2004. Definisi kampanye dalam undang-undang dan aturan Komisi Pemilihan Umum cenderung kabur dan seperti karet, sehingga seringkali menimbulkan perdebatan ketika ada pihak yang memaknainya lain. Kampanye sebenarnya tidak (hanya) terjadi pada waktu yang ditentukan penyelenggara Pemilu. Sejak mencalonkan diri sebagai kandidat, seseorang akan rajin melakukan kunjungan ke daerah dengan nama apapun: ulang tahun partai, kegiatan sosial, silaturahmi, peresmian, macam-macam. Dia juga jadi rajin nongol di media, tangkas menjawab suatu persoalan aktual.
Ketika masa kampanye dimulai, strateginya pun bukan hanya dalam bentuk yang terlihat di permukaan, seperti pawai, rapat akbar, dan iklan politik. Biarkan saja agar pemilih mendapat lebih banyak informasi tentang kandidat. Kalau pun ada politik uang atau dengan nama sumbangan untuk pembangunan jalan, misalnya –sarana kampanye yang dianggap lebih cocok untuk Pilkada ketimbang periklanan politik– terserah hati nurani pemilih, mau menerima atau menolak. Makin panjang kampanye makin banyak uang yang mesti dikeluarkan, tapi berapa dana yang mesti dikeluarkan seorang kandidat?
Tapi di sinilah peran media untuk mengimbangi informasi yang disebarkan masing-masing kandidat. Bukan hal mudah membedah kualifikasi kandidat, kompleksitas strategi kampanye, sisi manusiawi seorang kandidat dalam menghadapi serangan-serangan kandidat lainnya, dan sebagainya. Sejak itu pula muncul desakan untuk menghapus batasan masa kampanye, karena hanya menguntungkan kandidat yang punya nama dan punya jabatan.
Bagaimana dengan Pilkada di Kalimantan Barat, arena yang menjadi liang kubur bagi begitu banyak kandidat politik?
Media pasti akan diuntungkan dalam Pilkada. Di sini hampir semua kandidat akan kampanye periklanan untuk mempersuasi khalayak sasaran. Media mana yang akan dipilih tentu akan sangat tergantung dari efektivitas dan khalayak sasarannya. Media cetak dipilih karena keunggulan dan efektivitas pada kemampuannya memuat informasi dan iklan lebih terperinci. Kelemahannya, media cetak hanya bisa dinikmati dengan membeli, tidak seperti radio atau televisi. Radio memang hanya mengandalkan pesan yang hanya bisa didengar (audio) tapi pendengarnya terspesialisasi, tersegementasi, serta pesannya bisa menjangkau lapisan terbawah dalam masyarakat. Radio juga sangat mobile, mudah dibawa ke mana saja.
Lebih dari radio, televisi bukan hanya bisa didengar tapi juga dilihat (audio visual). Pesannya lebih mudah direkam pemirsanya, apalagi jika ditayangkan berkali-kali. Media televisi biasanya menjadi prioritas bagi kandidat. Bentuk iklan yang ditampilkan pun beragam, dari yang paling sederhana berupa orasi pemimpin partai, iklan testimonial, dokumentasi kegiatan, hingga berupa mini sinetron. Semuanya kemudian ditutup dengan ajakan mencoblos. Pengalaman selama kampanye pemilu legislatif 2004, televisi lokal sudah unjuk bicara dalam perolehan iklan. Jawa TV dan Bali TV bahkan mengungguli Global TV yang notabene stasiun televisi nasional, masing-masing dengan pemasukan Rp 3,8 milyar dan Rp 767 juta. Sementara Borobudur TV, stasiun televisi lokal di Jawa Tengah, meraup Rp 113 juta.
Tapi Pilkada bisa jadi lain dari Pemilu 2004, karena kekhasan dan lokalitasnya. Media cetak dan radio akan jadi sasaran utama karena relatif lebih duluan dikenal dan dinikmati masyarakat. Bisa jadi, jika televisi lokal sudah mengudara di Kalimantan Barat, dan mudah diakses, mata warga lebih akan mengarah ke sana, menonton berita seputar kampanye, kesibukan para kandidat, drama politik, dan deretan iklan-iklan politik.
Pertarungan menarik hati pemilih sesungguhnya memang terjadi di media massa. Dalam hal pemberitaan, para kandidat akan berusaha agar setiap kegiatan kampanyenya mendapat liputan luas dan menimbulkan citra positif. Kandidat akan punya kecenderungan yang sama seperti peserta Pemilu 2004. Ruang di media massa kurang dimanfaatkan secara maksimal untuk berkampanye. Tak ada jabaran program, visi, dan misi. Kampanye seolah jadi ajang hafalan nomor saja. Semestinya, iklan politik akan banyak menyinggung aspek-aspek politik, yakni berbagai isu berbangsa dan bernegara yang akan dijanjikan dalam jargon-jargon para politikus. Materi kampanye yang memuat visi dan misi akan menjadi tumpuan dan alasan bagi rakyat menentukan pilihan. Aspek pendidikan politik dengan menggunakan media modern tidak ditekankan para kandidat.
Di sisi lain, banyaknya kandidat, acara kampanye, dan pelbagai hal selama kampanye membuat media terjebak dalam arus informasi yang kurang dalam. Dalam Pemilu 2004, pemberitaan media televisi mengenai kegiatan kampanye hanya mengambil dari segi orasinya. Media televisi kurang menggali pesan-pesan politik yang disampaikan juru kampanye. Publik juga disuguhi berita yang kurang lengkap, sehingga keakuratan berita diragukan.
Media cenderung mengikuti dan terjebak pada agenda yang diusung masing-masing kandidat dan tim suksesnya. Dari kampanye tanpa isi, talking news, isu yang tak jelas informasinya, dan sebagainya. Pada Pemilu 2004, isu negatif seorang kandidat bertebaran, dari SBY yang kristen, Wiranto yang melanggar HAM, Mega yang tidak direstui kalangan Islam karena perempuan, Amien yang plin-plan, dan seterusnya. Isu itu memang berita. Ada sebagian yang mungkin benar. Tapi media tidak mengungkapkan semua itu ke dalam berita yang lebih dalam dan lengkap, yang bisa memberikan informasi memadai bagi pemilih. Isu itu bisa jadi memang dibikin pesaing untuk menjatuhkan saingannya. Bisa pula diciptakan sendiri untuk menarik simpati sebagai seorang “korban”. Ya komunikasi modern ketika bersinggungan dengan budaya massa menuntut semacam media hiburan: ada drama, ada selebritas.
Media semestinya tidak sekadar berlomba berebut kue iklan. Media juga punya peran dalam pendidikan pemilih. Bukan sekadar agar pemilih mau mendatangi kotak-kotak suara, tapi juga agar tidak datang dengan “mata buta” sehingga salah menentukan calon pemimpinnya.
Bukan hal mudah membedah kompleksitas kampanye. Aspek geografis dari sasaran konstituen di Kalimantan Barat sangat luas dan penuh keberagaman. Tapi menghadapi Pilkada, media seyogyanya punya agenda tersendiri dalam kampanye Pilkada. Media ikut memberikan pendidikan pemilih, bukan sekadar untuk mengajak pemilih datang ke kotak suara, tapi lebih dari itu, memberikan informasi yang memadai tentang kualifikasi calon, tentang persoalan yang menjadi tantangan pembangunan di Kalimantan Barat. Menghilangkan prasangka dengan berita yang benar. Menghilangkan sentimen atas nama apapun, agama maupun etnik. Memberikan kesempatan kepada semua kandidat untuk menjabarkan programnya tanpa alpa mengkritisi. Tidak memihak, sehingga tidak melukai suatu kandidat atau kepentingan yang lebih besar: akses informasi yang sama dan adil kepada kandidat.
Peran ini bisa jadi akan mengorbankan banyak hal dari media, atau wartawan: iklan malas mendekat, juga hubungan perkawanan.
Pada 1972, di sebuah restoran di New Hampshire, Broeder kebetulan bertemu dengan sahabat lamanya, seorang pengacara yang ternyata membantu kampanye kepresidenan dari Partai Demokrat. Mereka bercapak-cakap, sahabatnya berkata, “”Kamu tidak menulis tentang ini, bukan?”
Broder segera tahu masalahnya. Sahabatnya menjawab semua pertanyaan dengan jujur, tapi sebagai seorang sahabat.
“Kamu bukan orang yang tidak terkenal,” ujar Broeder.
“Kau tidak boleh melakukan itu. Ini akan merusak semuanya”
“Seharusnya kau pikirkan itu semua sebelum kau datang ke sini. Tidak mungkin kau dan kawan-kawanmu terlibat tanpa diketahui orang.”
Broder menuliskan cerita itu dan persahabatannya berakhir seperti yang diperkirakannya. Broeder tidak merasa yakin bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Dia merasionalisasikan “pengkhianatannya” dengan dalih bahwa kalau saya tidak menulis cerita ini, wartawan lain akan melakukannya. Tapi ini tidak menentramkan hatinya.
Tapi inilah tugas wartawan dan risiko yang harus ditanggung. Akan banyak pengalaman yang akan merisaukan seperti itu. Karena tugas wartawan adalah melayani kepentingan warga.
“Kebebasan pers pada akhirnya tergantung dari seberapa pentingnya pekerjaan kami bagi Anda (pembaca),” ujar Broeder.*
Saturday, September 23, 2006
Kampanye Media
at
7:53 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


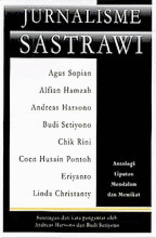


No comments:
Post a Comment