INI hari berat baginya. Di tengah malam, tanggal 31 Mei 1945, ia masih tak bisa memejamkan matanya. Ia bahkan menangis. Besok, ia mendapat giliran berpidato di hadapan anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) –lembaga bikinan pemerintah militer Jepang pada Maret 1945. Ia berpikir keras tapi tak juga ilham itu datang.
Ia keluar rumah. Langit terang. Kepalanya menengadah ke langit yang bertaburkan bintang. Ia berdoa, meminta petunjuk-Nya.
”Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepadaku ilham. Indonesia yang akan menjadi negara merdeka ini, harus berdasarkan atas dasar apa? Supaya Indonesia ini kompak, tetap bersatu, bangsa Indonesia ini tetap kompak bersatu, tidak terpecah belah.”
Lalu ia kembali ke dalam rumah, dan beranjak tidur. Keesokan harinya, 1 Juni, tiba-tiba ia mendapatkan ilham, dan ide itulah yang ia sampaikan di depan BPUPKI. Isinya tentang ”dasar-dasar yang nanti di atasnya negara Republik Indonesia akan diletakkan.” Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, diberinya nama Pancasila: lima sila, yang masing-masing tidak bisa dipisahkan. Lima menjadi satu, satu-kesatuan, panca-pancaning atunggal.
Pancasila tidak mendasarkan diri hanya pada satu agama atau kepercayaan, kepentingan golongan, maupun ideologi yang dianut. Mantra keberagaman tertera jelas dalam semboyan “bhinneka tunggal ika”. Pancasila mengakomodasi faham demokrasi, yang intisarinya diambil dari sistem yang sudah berurat-berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia (musyawarah). Dengan faham ini, sistem perwakilan (bukan sistem kerajaan yang absolut) mewujud dalam alam demokrasi di Indonesia. Terakhir, keadilan bagi seluruh rakyat.
“Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi,” ujar Soekarno dalan pidato Lahirnya Pancasila.
Nilai sosial terpenting dari Pancasila adalah toleransi. Dengan Pancasila, Soekarno berhasil meyakinkan kaum nasionalis sekuler, baik yang beragama Islam maupun tidak, bahwa negara baru ini tidak akan memprioritaskan Islam di atas lainnya. Meski, sejak itu, Pancasila menjadi bagian tak terpisahkan dari perdebatan politis dan ideologis.
Dalam perjalanannya, Pancasila belum teruji sebagai bagian dari jiwa dan semangat manusia Indonesia. Sejak Soekarno hingga sekarang, Pancasila hanyalah semboyan tanpa makna. Selalu disebut tapi tak ada perwujudan yang jelas. Terlebih di masa Orde Baru, Pancasila menjadi bagian dari upaya pemerintah memberangus ideologi lainnya. Pemerintah membuat penafsiran tunggal. Semua warga wajib mengikuti penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Dari dulu sampai sekarang, korupsi merejalela. Konflik daerah tak kunjung padam. Kemiskinan. Diskriminasi. Lalu orang menyatakan perlunya revitalisasi Pancasila.
Saya sendiri tak tahu kapan keberadaan Pancasila pernah dianggap tak vital. Ketika ia lahir, tentu ia sangat vital untuk, mengutip pidato Soekarno, ”dasar-dasar yang nanti di atasnya negara Republik Indonesia akan diletakkan.” Sebuah bayi akan lahir, dan ia butuh pijakan, bahkan tempat berpijak. Ketika Orde Baru berdiri, Pancasila menjadi vital, bahkan membuktikan ”kesaktiannya” terhadap masuknya ideologi lain yang berusaha merongrong keutuhan bangsa dan negara –begitulah jargon pemerintah. Sampai saat ini pun Pancasila masih dianggap penting, meski hanya sebagai penghias bibir para pejabat pemerintah. Tapi apakah Pancasila sudah menyatu dalam jiwa dan dalam setiap langkah, itu tampaknya menjadi persoalan.
Iseng-iseng, saya bertanya pada sejumlah orang tentang apa Pancasila itu masih penting di zaman ini. Umumnya terdiam sejenak dan berusaha menimbang. Ada juga yang hanya tersenyum, mungkin tersipu malu. Tapi ada pula yang langsung menjawab.
”Pancasila masih penting agar rakyat Indonesia bersatu.”
”Penting kalau dilaksanakan, bukan cuma omongan.”
”Jangan tanyakan ke saya. Tanyalah ke para pejabat, konglomerat-konglomerat ..., karena merekalah yang justru tidak memahami dan menjalankan Pancasila dengan benar.”
Yang agak ekstrem adalah jawaban ini: ”Pancasila tak bikin kenyang. Kalau sekarang yang lebih penting adalah bisa makan.”
Kesusahan hidup sudah menjadi gambaran Indonesia kini. Barang-barang kebutuhan hidup melambung. Lapangan pekerjaan susah didapat. Jawaban pragmatis akhirnya menjadi pilihan. Seandainya Soekarno masih hidup, mungkin ia akan sedih melihat kondisi ini. Sedih karena rakyat Indonesia ternyata belum beranjak dari kemiskinan, padahal kemerdekaan sudah lama teraih. Dulu di masanya, ia juga tak mampu menangani persoalan pangan ini. Bahkan seribu dewa dari khayangan tak mampu menyelesaikan masalah ini dalam satu malam. Lalu, ia juga sedih karena rakyatnya hanya memikirkan makan tok!
”Saya tidak mau membangun satu bangsa Indonesia yang memikirkan pangan saja. Saya tidak mau membangun satu bangsa Indonesia yang mau mikir isi perut saja. Tidak. Saya membangun bangsa Indonesia ... yang memperhatikan isi perut tetapi juga memperhatikan isi jiwa,” ujar Soekarno dalam pidato di depan anggota Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Paduan Suara Gelora Pancasila (Medan), 25 Juni 1966.
Isi perut dan isi jiwa adalah sama penting. Menyelesaikan persoalan kemiskinan menjadi agenda pemerintah yang harus diselesaikan dengan cepat. Di sisi lain, sebagai makanan jiwa, revitalisasi Pancasila juga sangat urgen dan mendesak. Persoalan yang dihadapai bangsa ini sudah begitu akut. Semua orang seolah kehilangan pegangan dan tak punya tujuan. Pancasila penting terutama untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia punya satu sejarah dan satu tujuan.
Itu bisa dimulai dengan menjadikan dasar negara ini kembali sebagai wacana publik. Masyarakat perlu diingatkan bahwa Pancasila masih ada dan masih dibutuhkan bagi negara-bangsa Indonesia. Sarananya bisa melalui pendidikan, tanpa harus mengikuti jejak indoktrinasi di masa lalu. Ada penataran P4, ada pelajaran Pendidikan Moral Pancasila yang mengharuskan kita hafal Pancasila, butir-butir nilai P4, UUD 1945, bahkan nama-nama menteri. Ada kewajiban menonton film-film sejarah. Masih banyak lagi. Ketika kuliah, ada mata kuliah kewiraan, filsafat Pancasila, dan seterusnya. Harus ada penjabaran dan langkah-langkah yang lebih kongret untuk mewujudkan upaya revitalisasi ini.
Apakah Pancasila sudah bersemayam di dalam hati kita? Tak mudah menjawabnya. Mungkin tidak, karena di dalam hati ini masih penuh gejolak, masih dipenuhi oleh tantangan dan persoalan hidup. Mungkin iya, karena ia sudah merasuk dan menggerakkan, sadar atau tidak, setiap gerak dan langkah kita. Selama dua tahun ini saya bikin dan ikut upacara bendera di lingkungan rumah, saya masih merasakan getaran lembut di dada kala mendengarkan pembacaan Pancasila.
Tapi sekarang saya sudah memutuskan menarik sebuah buku saku yang selama ini terselip dan terbengkalai di rak buku. Saya membelinya di pinggir jalan dari penjual buku loakan. Harganya sangat murah. Tebalnya 64 halaman. Isinya tentang UUD 1945 dengan penjelasannya, hasil amandemen, Piagam Jakarta, nama-nama menteri, dan –yang ini sungguh saya tak ingat lagi– 45 butir nilai P4. Berulang-ulang saya baca, karena untuk menghafal lagi seperti di masa sekolah menengah terasa berat.
Saya baca lagi, lalu merenungkan isinya dalam hati: apakah saya sudah menghayati dan mengamalkan Pancasila? Apakah Pancasila sudah menjadi kebutuhan dan makanan jiwa saya, ataukan selama ini saya masih hanya memikirkan isi perut saja?*
Wednesday, October 04, 2006
Isi Perut dan Jiwa
at
7:49 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


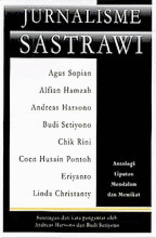


1 comment:
Hei! Banguun..! Sudah dapat hasil perenunganmu? Apa hasilnya? hehehe...
Post a Comment