TERBIT sudah. Memang telat dari ancangan semula, yang akan meluncurkannya berbarengan dengan peringatan 50 hari meninggalnya sang penulisnya. Tapi yang penting, ia kini sudah hadir kembali setelah setengah abad tenggelam dalam pusaran sejarah sastra Indonesia yang condong ke “kanan”.
Saya tak tahu kapan rencana penerbitan ulang ini muncul. Jauh sebelum saya mengenal penulisnya, Klara Akustia, dua pemuda sering datang ke rumahnya. Berdiskusi. Bercengkerama bak bagian dari keluarga. Mereka juga mencetak ulang kumpulan puisi ini dalam format sederhana. Hanya satu eksemplar, semacam proyek percontohan. Belakangan, ketika saya lebih sering ke sana, rencana penerbitan ulang ini sudah berjalan. Kabarnya, jauh sebelum sastrawan Pramoedya Ananta Toer meninggal dunia, dia sudah berpesan kepada anaknya agar menerbitkan karya-karya Klara Akustia. Saya melihat penulisnya melakukan koreksi di sana-sini. Baginya, penerbitan ulang suatu karya harus melihat konteks zaman. Saya pun didapuk membuat kata pengantarnya. Saya ingat pesannya agar membaca buku-buku George Lucaks, Ilja Ehrenburg, hingga Maxim Gorky.
Saya melihat penulisnya melakukan koreksi di sana-sini. Baginya, penerbitan ulang suatu karya harus melihat konteks zaman. Saya pun didapuk membuat kata pengantarnya. Saya ingat pesannya agar membaca buku-buku George Lucaks, Ilja Ehrenburg, hingga Maxim Gorky.
Saya membaca cetakan pertamanya. Kemasannya sederhana. Di kulit muka tergores buah tangan pelukis Basuki Resobowo: tulisan Rangsang Detik. Tapi di cetakan kedua, ada keinginan menampilkan wajah baru.
Pelukis Jeany Mahastuti membuatkan kulit muka. Pesan yang ingin disampaikan adalah perubahan (pantarei). Lalu jadilah gambar obor dalam lingkaran. Warnanya mencolok. Saya kurang tertarik. Untuk sebuah buku, terlalu kaku. Kurang menarik pembaca untuk membelinya. Saya usulkan agar sketsa penulisnya saja yang ditampilkan dalam sampul. Lebih elegan. Toh tak semua orang mengenal wajahnya.
Saya membuat kata pengantar yang mengaitkan pengalaman dan pemikiran penulisnya yang melahirkan puisi-puisi itu. Kata pengantar ini diletakkan di bagian awal (prolog). Eka Budianta belakangan juga menulis pengantar, yang kemudian dimasukkan sebagai epilog. Menurut Andreas Harsono, rekan saya di Pantau, pengantar saya mirip gaya tulisan orang-orang Lekra. Saya tak tahu di mana kemiripannya, karena saya belum menyelami gaya tulisan orang-orang Lekra –sekalipun saya sudah membaca buku-buku soal Lekra dan karya-karya penulis Lekra. Saya tak bermuluk-muluk untuk meletakkan posisi kepengarangannya dalam sejarah sastra Indonesia. Tapi saya berusaha dengan mencari bahan-bahan yang mungkin didapat. Saya masih mencari puisi-puisi lainnya di luar kumpulan puisi ini terbit. Saya mesti mencari puisinya dalam bahasa Sunda –menurut sastrawan Sunda R.A.F., Klara Akustia adalah pelopor dalam puisi Sunda. Juga dalam bahasa asing. Dalam sebuah surat yang dimuat di Harian Rakjat, Kas Widjaja dari SOBSI cabang Prabumulih, menceritakan perjalanannya ke Moskow dan Chekoslowakia pada 1951, dan orang-orang di sana mengenal dan menanyakan nama Klara Akustia.
Saya tak bermuluk-muluk untuk meletakkan posisi kepengarangannya dalam sejarah sastra Indonesia. Tapi saya berusaha dengan mencari bahan-bahan yang mungkin didapat. Saya masih mencari puisi-puisi lainnya di luar kumpulan puisi ini terbit. Saya mesti mencari puisinya dalam bahasa Sunda –menurut sastrawan Sunda R.A.F., Klara Akustia adalah pelopor dalam puisi Sunda. Juga dalam bahasa asing. Dalam sebuah surat yang dimuat di Harian Rakjat, Kas Widjaja dari SOBSI cabang Prabumulih, menceritakan perjalanannya ke Moskow dan Chekoslowakia pada 1951, dan orang-orang di sana mengenal dan menanyakan nama Klara Akustia.
Waktu masih berjalan. Dan detik demi detik terus merangsang untuk mewujudkannya.*
Friday, May 25, 2007
Rangsang Detik
at
2:13 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


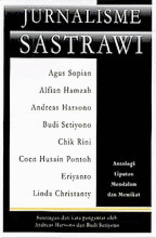


8 comments:
Halo, Mas Buset!
Saya sudah punya buku ini. Saya juga sudah membaca kata pengantar yang anda tulis. Tidak mendayu-dayu, memang, tapi masih terlalu liris untuk disebut bergaya tulisan orang-orang Lekra. Apalagi kalo Lekra di situ ukurannya adalah gaya esai-esainya Pram. Hehehe....
Saya suka covernya. Bening.
Zen, saya membaca banyak tulisan orang-orang Lekra, dari Aidit, Njoto, Dharta, Joebar Ajoeb, Soedjojono, hingga Pram. Umumnya memang lugas, kadang keras, tapi tidak liris. Saya membuat pengantar agak liris semata karena saya bicara dan mengupas soal puisi dan diri penyairnya. Thanks.
Orang-orang Lekra memang jarang sekali menulis liris. Itulah sebabnya saya bilang di komen sebelmnya kalau tulisanmu masih terlalu liris untuk disebut mirip tulisan orang-orang Lekra seperti yang dibilang Andreas.
Buset menulis: "Saya membuat pengantar agak liris semata karena saya bicara dan mengupas soal puisi dan diri penyairnya."
Saya bertanya: "Apakah puisi dan penyair hanya bisa didekati dengan gaya liris dan ditulis dengan gaya liris pula?"
Saya sempat berpikir: bukankah akan lebih mendekati "rasa puitika AS Dharta" jika pengantar ini ditulis dengan lugas dan sebisa mungkin menjauhi lirisisme, karena puisi AS Dharta pun bisa saya bilang tidak memilih gaya yang "liris"?
Itu menurut saya lho ya, yang lumayan sering membaca puisi Sobron dan Agam Wispi, tapi jarang membaca AS Dharta.
Akhirnya, kang... aku menemukanmu lagi...
Isih kelingan aku ta...
Iki moel, sastra inggris 95.
piye kabare...
Zen, sebaliknya, "Apakah puisi dan penyair tidak bisa didekati dengan gaya liris dan ditulis dengan gaya liris pula?"
Tentu juga bisa, kan. Itu soal pilihan.
Puisi Dharta ada yang liris, meski umumnya lugas. Sosoknya juga romantis. Suasana ketika saya menulis begitu redup, sentimentil (yang ada dalam benak adalah kenangan).
Tapi pada akhirnya, dalam menulis, gaya personal saya-lah yang masuk. Mungkin nanti, kalau saya menulis pengantar untuk esai-esainya, saya akan lebih lugas, tapi tetap dengan gaya bertutur.
Thanks
Moel, aku baik-baik saja. Senang bisa "bertemu" kembali.
Saya menunggu pengantar Sampeyan untuk esai-esai Dharta.
Di penyimpanan arsip digital kantor saya, saya pernah membaca serangan Dharta pada Ajip Rosidi. Barangkali dari sini "suasana personal" esai Ajip di PR bisa dilacak jejaknya.
Bos, aku link blogmu ya?
Post a Comment