DESA Cikondang, Cianjur, membentangkan hamparan sawah dan pegunungan yang menghijau dan segar. Sebuah rumah sederhana dan lumayan besar terlihat. Halamannya luas. Di sisi kanan gerbang terpampang papan nama sebuah yayasan. Rumah ini rasanya tak pernah sepi. Beragam kegiatan warga setempat meramaikannya. Sangat kontras dari kondisi rumah bercat biru yang terletak tak jauh dari rumah ini. Sepi.
Seorang lelaki tua berkacamata tebal duduk di beranda rumah, membaca berita hangat di koran pagi. Suara gemericik air sungai terdengar lirih dari kejauhan. Sesekali ditingkahi derit kereta melaju pelan. Saya mengenalnya setahun lalu, dan setidaknya sebulan sekali bertandang ke rumahnya.
Rumah menjadi bagian penting dalam pengalaman batin dan proses kreatif seorang penulis. Datang ke rumah ini seolah menggapai tempat yang melahirkan sajak-sajaknya. Atau lebih tepat lagi, mengkaji hubungan antara pengarang, karya sastra, dan lingkungannya. Dari sini pula saya memperoleh dan membaca Rangsang Detik, karya yang mencatatkan perjalanan kreatif, pengalaman hidup yang menempanya, serta pemikirannya dari 1949-1957.
Rumah ini akan selalu mengingatkannya ketulusan hati seorang ibu sekaligus pada sebuah kepedihan. Ini rumah masa kecilnya. Di sini pula ia dilahirkan, 7 Maret 1924. Namanya Endang Rodji –tapi kelak ia menggunakan banyak nama untuk karya-karyanya: Adi Sidharta, A.S. Dharta, Klara Akustia, Kelana Asmara, Rodji, Jogaswara, Barmara Putra, dan mungkin masih ada yang lain.
Tapi kasih sayang orangtuanya tidaklah genap. Hatinya luluh lantak dihantam kesedihan. Ibunya, Fatimah, meninggal dunia karena sakit pada 1930. Kepergian ibunya, orang yang biasa memanjakannya, benar-benar membuat dia sangat kehilangan. Disusul kemudian ayahnya, Moh. Usman. ”Saya seolah terlempar ke neraka,” ujarnya kepada saya. Setelah melewati pengalaman-pengalaman sedih, dia akhirnya pindah ke Bandung, lalu menetap di Jakarta.
 Tapi Priangan adalah tanah kelahirannya. Dari sinilah ilham dan segala nafas kehidupan membuncah dalam dirinya. Priangan mengasah rasa, emosi, gairah, dan segala gerak di lubuk hati manusia ini; bergerak merangkak pada sikapnya untuk memanusiakan manusia. Lihat saja betapa ia masih menyebut nama “ibu”, untuk menggambarkan betapa kejamnya perang –sehingga ia menyatakan: karena itu aku kini pahlawan anti perang. Kenangan dan kekaguman pada ayah angkatnya, Okayaman atau Barmara, seorang eks-Digulis, juga terpatri dan mempengaruhi sikapnya: panenmu di hari fajar berdarah / mekar menjadi panen pembebasan.
Tapi Priangan adalah tanah kelahirannya. Dari sinilah ilham dan segala nafas kehidupan membuncah dalam dirinya. Priangan mengasah rasa, emosi, gairah, dan segala gerak di lubuk hati manusia ini; bergerak merangkak pada sikapnya untuk memanusiakan manusia. Lihat saja betapa ia masih menyebut nama “ibu”, untuk menggambarkan betapa kejamnya perang –sehingga ia menyatakan: karena itu aku kini pahlawan anti perang. Kenangan dan kekaguman pada ayah angkatnya, Okayaman atau Barmara, seorang eks-Digulis, juga terpatri dan mempengaruhi sikapnya: panenmu di hari fajar berdarah / mekar menjadi panen pembebasan.Priangan pula yang memberikan energi kepada sajak-sajaknya yang mengabarkan kegandrungan kepada kebesaran manusia. Banyak sajaknya bernafaskan kegairahan bumi tempatnya dilahirkan, menyerap saripati dari semangat kepahlawanan para pejuangnya: “Rukmanda”, “Cadaspangeran”, “Bara di Priangan”. Sajak-sajak ini begitu bergumuruh, menantang segala yang menghadang perlawanan demi pembebasan manusia, tapi juga liris; sepi, merindu, melilitkan kenangan pada tanah kelahiran.
Ia juga tak terbersit pergi dari akar budayanya. Ia menulis sajak dalam bahasa Sunda. Karyanya antara lain termuat dalam buku Kantjutkundang, yang disusun oleh Ajip Rosidi dan Rusman Setiasumarga dan terbit pada 1963. Dalam buku ini, ada sejumlah sajaknya: “Poe Anyar” dan “Lagu”, “Kidung Sundayana”, serta “Talatahna Anepakeun”. Kedudukan dan pengaruhnya dalam bahasa dan kesusastraan Sunda juga tak bisa dibilang kecil. Klara Akustia-lah yang kali pertama mendeklamasikan sajak (bebas) Sunda dengan gaya modern, dan menyejajarkan namanya dengan sastrawan Sunda lainnya.
Bahkan sisa hidupnya dia kerahkan untuk tanah Priangan. Di kamarnya, di dalam sebuah kardus, teronggok tumpukan kertas usang seribuan halaman: Kamus Bahasa Sunda-Indonesia. Inilah kerja terakhirnya yang belum usai, menyisakan sentuhan tangan lain untuk meneruskan enam abjad terakhir yang tersisa.
TAPI pengertian rumah tak mesti sekaku itu. Jakarta bagaimana pun rumahnya juga, tempat dia menempa segala pengalaman hidup. Dalam istilah Pramoedya Ananta Toer, dalam tulisannya pada 1955, Jakarta hanyalah kelompokan besar dusun. Tak ada yang berubah dari sejak masuknya kompeni. Tak ada tumbuh kebudayaan kota yang spesifik, semua dari daerah atau didatangkan dan diimpor dari luar negeri: dansa, bioskop, pelesiran, minuman keras, dan agama. Dan bagi Klara Akustia, akhirnya, orang-orang datang dan berkumpul ke Jakarta, menjadi warga Jakarta, untuk mempercepatkan keruntuhan kelompokan besar dusun ini. Tambah banyak yang datang tambah cepat lagi.
Tapi itu sepuluh tahun kemudian. Pada saat Klara Akustia menginjakkan kakinya di Jakarta, kondisinya jauh lebih parah lagi. Jepang sudah menguasai Jakarta, menjadikannya hancur dalam puing-puing. Mayat bergeletakkan di mana-mana. Suasana ini mengoncangkan jiwanya. Ia tergerak, berjuang, menjalani pertempuran demi pertempuran, bertemu dengan kawan dan lawan. Di masa inilah ia mulai menulis sajak. Berdasarkan penuturannya, sajak pertamanya dimuat di suratkabar Tjahaja, Bandung. Isinya mengenai semangat para pemuda yang bergolak, membela tanah air. Sayang, saya belum mendapatkan sajak ini –juga, kalau ada, sajak-sajak lainnya.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia rupanya bukanlah akhir dari perjuangan. Pergolakan belum lagi mengendap. Tak ada perombakan dalam sistem sosial dan budaya masyarakat. Semangat Revolusi Agustus, yang tertanam di jiwanya, bergejolak ketika kemerdekaan sejati belumlah terwujud. Dan inilah masa-masa yang membutuhkan agitasi, daya dobrak, untuk memenuhi tuntutan zamannya. Satu zaman yang membutuhkan generasi baru, yang lebih lengkap, lebih sempurna, lebih kuat dari angkatan sebelumnya, seperti ia nyatakan dalam esai “Angkatan 45 Sudah Mampus”. Hal ini pula tampak dalam sajak-sajak awalnya, yang kental membicarakan soal kasih dan cinta, ketetapan hatinya sebagai pelaksana hari esok, meski mewarisi generasi lama, reruntuk lapuk yang kurombak (“Aku Pelaksana”). Tapi sejak awal dia tak hendak berjalan sendirian. Dalam sajak “Hati dan Otak Kita”, secara tegas dan pasti, dia mengajak: kawan-kawan yang masih tidur / tinggalkan mimpi 40 bidadari.
Ini juga masa-masa keremajaan cintanya bersemi dan berlabuh di hati seorang perempuan: Aini atau ia biasa sebut Klara. Tapi pergolakan revolusi pula yang memisahkan keduanya. Klara dikawin-paksa seorang serdadu Belanda dan dibawa ke negerinya –sejak itulah ia memakai nama Klara Akustia: setia kepada Klara, juga setia kepada cita-cita perjuangan. Kesedihan dan kekecewaan, yang berbalut dengan kemauan untuk tak menyerah, menyelimuti hatinya. Perasaan in ia terakan dalam sajak “Triompator Esok”: Tapi kutahu tuhan kekerasan ini / esok menyerah kepada tuhan rasio.
Usai kemerdekaan sepenuhnya, tak ada hari dilewatkannya kecuali untuk kerja. Menjadi wartawan Harian Boeroeh di Yogya, memimpin sejumlah serikat buruh, ikut dalam organisasi pemuda dan buruh internasional, PEN Club-Indonesia, serta sejumlah lembaga kebudayaan. Inilah aktivitas dan lingkungan yang memperkaya pengalaman batinnya sebagai sastrawan dan anak zamannya. Menurutnya, kerja itu nikmat, dan kenikmatan bukanlah monopoli satu orang. Itulah yang dia sampaikan kepada Rukiah Kertapati dalam “Kata Biasa”.
Kata orang, kita satu bahasa
mari adik, nikmat itu bukan monopoli
kita resapkan kepada mereka yang belum merasa.
Tahun 1950 ibarat kelahirannya kembali. Langkahnya lebih pasti, lebih kongkret. Di lapangan kebudayaan, setelah esainya menimbulkan polemik di jagat kesusastraan Indonesia, ia menggerakkan konsep yang lebih luas: di mana posisi sastrawan atau seniman di dalam perubahan masyarakat. Dalam esainya “Sekitar Angkatan 45”, ia menulis: “Ya, dan kita akan terus / dari agitasi ke organisasi / dari elan keinginan / ke energi pelaksanaan!”
Dan yang menghidupkan kata adalah perbuatan. Pada 17 Agustus 1950, Klara Akustia mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) –yang secara salah kaprah sering dicap organ Partai Komunis Indonesia (PKI)– bersama M.S. Azhar dan Njoto. Dia ditunjuk sebagai sekretaris jenderal (Sekjen) sekaligus redaktur Zaman Baru, penerbitan resmi Lekra. Sebagai Sekjen, dia aktif menjelaskan realisme sosialis, juga berpolemik dengan sastrawan lain.
“Seorang sastrawan tidak mungkin dan tidak bisa berdiri ‘netral’, terlepas dari pengaruh lingkungannya,” tulisnya dalam “Kepada Seniman Universal”, menanggapi tulisan kritikus HB Jassin yang memajukan konsep humanisme universal, sementara ia sendiri menawarkan konsep realisme sosialis atau realisme aktif. “Antara Bumi dan Langit” adalah sebuah sajaknya yang ditujukan untuk HB Jassin. Kita berdua sama-sama tidak bebas / kau terikat pada dirimu / aku pada Manusia dan zaman kini.
Rangsang Detik hanyalah karya satu-satunya yang sempat terbit. Kata dan kalimat dalam sajak-sajaknya, segera dapat bergetar kepada hati dan pikiran manusia, juga menjadi barikade ke jantung perasaan dan pemikiran. Dalam menulis sajak, seperti ditunjukkan dalam esainya ”Surat Kertas Hijau Sitor Situmorang”, ia mengajukan sebuah resep –meski untuk menimbang sesuatu sajak tidak ada resep tunggal. Pertama, adanya pribadi penyairnya dalam sajak-sajaknya. Kedua, mengharukan dan ini sangat subjektif, tergantung kepada sejarah pertumbuhan, suasana dan posisi masing-masing pembaca. Ketiga, setiap kata dan kalimat membawa ide dan formulasi yang padat. Dan saripatinya adalah kesadaran dan keyakinan akan perlunya harmoni antara keindahan dan realitas atau kehidupan.
“Keindahan adalah kehidupan” dan karenanya “Keindahan yang benar-benar tertinggi adalah keindahan yang dijumpai manusia di dunia nyata dan bukanlah keindahan yang diciptakan oleh seni,” demikian N.G. Tjernisevski dalam Hubungan Estetik Seni dengan Realitet, yang diterbitkan Bagian Penerbitan Lekra pada 1961.
Karenanya, ia menyambangi Si Amat; seorang buruh tapi kadang juga jadi tukang becak, yang minta merdeka dari penjajahan sepiring nasi dan mau dunia kembali satu dan sama. Ia mengemukakan penari Senen bernama Nyi Marsih dan Otjim “anak revolusi” yang menanti kapan merdeka, merdeka untuk semua. Ia menuntut keadilan dan pembebasan atas penindasan dan penghisapan di Madiun, Ngalihan, Korea, Vietnam, di mana-mana, di negeri-negeri yang derita rakyatnya masih bergolak, sambil mengagungkan pejuang-pejuangnya. Ia juga tak lupa mengajak untuk merapatkan barisan. Buruh adalah golongan masyarakat yang menjadi titik perhatian dalam sajak-sajaknya, yang tak lepas dari labuhan hatinya. “Cerita pada 1 Mei” misalnya, yang ditujukannya kepada Vaksentraal SOBSI, menggambarkan kerelaannya untuk menyerahkan dirinya utuh, tidak lagi butatuli memperdewa ke-aku-anku.
Tapi ia juga tak berhenti pada satu jalan. Pada 1955, tahun-tahun menjelang pesta demokrasi, Partai Komunis Indonesia menawarinya untuk mencalonkan diri sebagai anggota Konstituante lewat calon-tak-berpartai. Tawaran itu membuatnya bersoaljawab di dalam diri sendiri, menimbulkan konflik dua keakuan. Tapi ia memilih jalan itu, karena pencalonan itu memberikan “kesempatan kepadaku untuk bisa lebih kongkret menguji pelaksanaan segala maksud baik dalam hatiku dan dalam diri orang lain,” demikian esainya di Harian Rakjat, 7 Desember 1955. Dalam sajaknya “Rakyat Memilih” dia mengikis kebimbangan yang semula bertahta di dalam hati: Dan kita maju / berani memilih dari detik ke detik.
Ujung dari perjalanannya ini pun sampai. Klara Akustia dikeluarkan dari Lekra karena telah melakukan “kemesuman borjuis” –istilahnya sendiri. Ia mengakui perbuatan itu untuk menyadarkan perlunya otokritik, bukan hanya kritik. Pada 1958, jabatannya sebagai Sekjen dicabut dan beralih ke tangan Djoebaar Ajoeb. Juga keanggotaannya di Konstituante. Sajak “Berita dari Partai” yang menutup kumpulan puisi ini, menyiratkan sikapnya: selamat tinggal kelampauan / selamat datang keakanan.
Berita Partai tegakkan panji
pertempuran terhadap diri sendiri
hadapkan diriku pada pilihan:
kegairahan dari kehidupan
lacuti nafsu perseorangan
atau layu dalam mati sebelum mati.
Itulah sajak penutup daripada kumpulan sajak ini, pembuka daripada penghidupannya yang lebih baru.
KLARA Akustia kembali menetap di bumi Priangan. Selepas pencabutannya sebagai Sekjen Lekra, ia pulang ke kampung halamannya. Di sana ia mengajar kursus bahasa Inggris untuk masyarakat sekitar, juga menulis sajak –dalam kesepian yang memisahkan segala. “Temui Aku”, sajak yang tak termuat dalam kumpulan puisi ini, menyiratkan kegalauan hatinya.
Temuilah aku
dalam keriuhan yang lahirkan perubahan
di mana kerja adalah cinta
di mana remaja adalah senantiasa.
Kerja, ya itulah yang selalu ia damba. Pada 1962, bersama Hendra Gunawan, ia mendirikan Universitas Kesenian Rakyat di Bandung. Dalam peresmiannya, Presiden Soekarno mengatakan bahwa ini universitas pertama di Indonesia dalam bidang humaniora. Inilah salah satu cita-citanya untuk mensarjanakan masyarakat Indonesia. Tapi keinginan itu belum terwujud sepenuhnya ketika iklim politik berhembus ke kanan. Terjadi peristiswa terkelam dalam sejarah Indonesia pada 1965. Ia masuk penjara di Kebonwaru, Bandung. Selepas dari penjara, tahun 1978, sekali lagi ia bersandar di rumah masa kecilnya. Tapi sakit pula yang menggerogoti tubuhnya. Klara Akustia meninggal dunia pada 7 Februari 2007.
Melalui sajak-sajaknya, ia telah memilih untuk tak mau bersibuk dengan dirinya sendiri, mengakui satu-satunya realitas adalah egonya sendiri, dan karenanya menolak terkurung di menara gading. Ia memilih bersoal-jawab atas masalah-masalah yang dihadapi manusia-manusia di sekitarnya, dengan hasrat memecahkan persoalan-persoalan itu. “Hasrat akan sesuatu yang baru adalah sumber kemajuan,” ujar G. Plekhanov dalam Seni dan Kehidupan Sosial, yang diterbitkan Bagian Penerbitan Lekra.
Ia tak jemu mengajak manusia bergerak dan ikut dalam arus perubahan. Tapi ia juga orang yang tak henti-hentinya mencari generasi-generasi muda terbaik. Pramoedya Ananta Toer, novelis tetralogi Bumi Manusia, satu di antaranya. Dan ia percaya keremajaannya akan terus hidup, seperti tersirat dalam sajaknya, “Rukmanda”:
Aku kini tiada lagi
bersatu dengan bumi tanahair tecinta
tapi lagu aku tamatkan
bersama bintang seminar kelam
dengan debar jantung terakhir
yang melihat fajar bersinar
kelahiran tunas penyambung keremajaanku.
Pada akhirnya rumah ini mewujudkan keinginannya untuk pulang, sebuah konsep yang memiliki magnetnya sendiri. Pulang berarti masuk kembali ke jagad lama yang sudah sangat dia kenal: rumah, sejumput kenangan masa kecil, lalu bau tanah-bumi di pemakaman keluarga, tempat dia kemudian dimakamkan.
Rangsang Detik ini hanyalah penanda, bahwa yang pergi tetaplah akan dikenang, yang tinggal akan meneruskan keremajaannya. Tapi juga seperti judul ini, semuanya bermuara pada gerak, kerja, perubahan –dan itulah kenapa buku ini diberi judul Rangsang Detik.*
Hanjawar, Februari 2007
Budi Setiyono


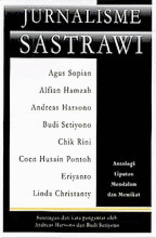


No comments:
Post a Comment