JALAN itu berkelok-kelok. Tebing tanah dan bebatuan berdiri rapuh di sisi jalan. Sesekali terlihat material tebing tersuruk. Sebuah batu besar tergeletak, menunggu tangan-tangan perkasa meluncurkannya ke jurang di sisi lainnya. Tapi mobil ini masih meluncur tenang menuju rumah para arwah di puncak gunung.
Ini perjalanan saya kali kedua di daratan Flores. Setahun lalu, saya hanya sempat menapakkan kaki di Gunung Meja. Puncaknya memang seperti meja. Datar. Luasnya sekira lapangan bola. Penuh dengan pepohonan menghijau. Ada kelapa, mangga, ubi, juga tumbuhan liar lainnya. Hm, saya menikmati ubi bakar dan kelapa muda di sebuah gubuk sambil menatap keindahan alam dari atas gunung: laut, pelabuhan, dan perumahan terhampar. Tapi memang tak lengkap ke Ende tanpa melihat Kelimutu.
Kelimutu adalah sebuah gunung yang meletus pada 1886. Ia lalu meninggalkan tiga kawah berbentuk danau yang airnya berwarna merah (tiwu ata polo), biru (tiwu ko’o fai nuwa muri) dan putih (tiwu ata bupu). Ketiga warna itu mulai berubah sejak tahun 1969 saat meletusnya Gunung Iya di Ende. Kawasan Kelimuti telah ditetapkan sebagai taman nasional sejak 26 Februari 1992.
Kelimutu, Kelimutu, kini saya datang.
Pagi ini langit cerah. Tak ada kabut. Persawahan masih terlihat jelas. Dua jam kemudian sampailah saya di halaman parkirnya. Tak ada seorang pun pengunjung. Tak ada juga penjual makanan. Kopi. Kain tenun. Hanya seorang petugas menanti di sisi motornya. Katanya, tiga turis bule baru saja pulang. Akhir-akhir ini memang sepi. Gempa dan tanah longsor, hujan yang mendera, dan angin kencang yang menerpa daratan Flores cukup menahan keinginan orang mengunjungi tempat ini. Kelimutu ramai saat-saat hari besar: Paskah, Natal, Lebaran.
Selain memiliki keanekaragaman hayati yang cukup bernilai tinggi, juga memiliki keunikan dan nilai astetika yang menarik yaitu dengan adanya tiga buah danau berwarna dan berada di puncak Gunung Kelimutu (1.690 meter dpl).
Saya menaiki jalur setapak, berbelok ke kiri, lalu terhamparlah tanah lapang penuh bebatuan. Dua tangga-naik di sisi kanan mengantarkan saya ke sisi sebuah lubang besar. Inilah danau yang pertama: Tiwu Ata Mbupu (danau arwah para orang). Dalam. Luas. Tebingnya curam. Warna airnya coklat. Angin hanya mampu membuat gelombang kecil.
Di sisinya, ada sebuah lubang besar lainnya. Posisinya agak tinggi. Warna airnya hijau muda. Ada buih kekuningan di sana-sini –mungkin belerang. Namanya Tiwu Nuwa Muri Koo Fai (danau arwah muda-mudi). Mungkin sesuai dengan namanya, danau kedua ini lebih sering berubah warna. Konon, ia sudah menjalani duabelas perubahan warna dalam jangka waktu 25 tahun.
Jarak keduanya berdekatan. Banyak orang takut, mungkin juga menunggu, apa yang terjadi jika kedua air danau itu menyatu. Tapi gempa tak mampu meruntuhkannya.
Menurut Om Hans, di dalam danau itu terdapat lubang atau goa yang mengalirkan airnya. Airnya mengalir sampai ke desa Jopu dan Nggela. Di sana ada sebuah kolam yang menampung air danau itu. Warnanya bening tapi bau belerangnya begitu kuat. Banyak penduduk mandi di kolam ini karena percaya bisa mengobati penyakit kulit. Tapi jika mencelupkan diri di kolam ini, bersiap-siaplah mencium bau belerang di tubuh yang susah menghilang. “Bisa sampai seminggu,” ujar Om Hans.
Saya tak sempat ke dua desa itu. Padahal di Nggela, ada kerajinan tenun tradisional. Masih asli, dikerjakan dengan tangan-tangan terampil. Juga alat pemintal benangnya. Sebagai pewarna, penduduk menggunakan dedaunan, bukan pewarna celup. Harga kain-kainnya sekitar Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu. Ah tapi saya sedang di Kelimutu, dan masih ada satu danau lagi di puncak lainnya.
Kelimutu, Kelimutu. Apa yang membuat warnamu begitu berbeda –sayangnya saya tak sempat menyaksikan perubahan warna itu. Mineral apa yang larut di dalamnya. Seolah seseorang telah mengecat warna airnya, lalu mengganti catnya jika bosan –sesuatu yang tak mungkin. Belum ada jawaban yang memuaskan. Hanya dugaan, perubahan warna ini akibat pembiasan cahaya matahari, adanya mikro biota air, terjadinya zat kimiawi terlarut, dan akibat pantulan warna dinding dan dasar dana.
Tapi di sinilah rumah para arwah. Di sinilah sebuah legenda menyebar dari mulut ke mulut dan menjadi abadi.
Masyarakat percaya, jiwa atau arwah seseorang akan datang ke Kelimutu setelah seseorang meninggal dunia. Jiwanya atau maE meninggalkan kampungnya dan tinggal di Kelimutu untuk selamanya. Sebelum masuk salah satu danau/kawah, arwah tersebut terlebih dulu menghadap Konde Ratu selaku penjaga pintu masuk di Parekonde. Ia masuk ke danau mana, tergantung pada usia dan perbuatannya. Tak jelas benar spesifikasinya. Tapi itulah legenda setempat yang tertera dalam sebuah papan di puncak Kelimutu.
Karena dianggap sakral, maka sejumlah aturan mesti Anda patuhi. Saya kutip bahasa Lio dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia:
Ma’e medi mairewo tamenga gambar/foto. Jangan mengambil sesuatu kecuali gambar.
Ma’e tau mata rewo ta menga nala/hibu. Jangan membunuh sesuatu kecuali waktu.
Ma’e welutau rewota menga la’e/ola. Jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak.
Saya pun mengambil gambar. Dua jam saya membunuh waktu di sini. Memandangi ketiga danau itu bergantian. Pemandangan sekitar. Awan. Kabut yang mulai mendaki. Pegunungan. Hamparan sawah di kejauhan. Lalu kami pun turun, meninggalkan jejak kami.
Penjaga tadi menunggu di pelataran parkir. Dia sudah siap menjajakan kain tenun warna-warni. Saya membeli dua helai selendang seharga Rp 25.000. Sarung tak terbeli. Harganya mahal, di atas Rp 100 ribu. Mungkin di Moni lebih murah, pusat tenun dan aktivitas warga sekitar.
Moni siang itu juga sepi. Tak ada penjual kain tenun. Hanya deretan bambu-bambu tanpa kain terlihat di sana-sini. Kata orang, hari biasa memang sepi. Harus datang pada hari pasar: Senen dan Selasa. Dan saya pun kembali ke Ende.*
Thursday, March 22, 2007
Kelimutu, Kelimutu
at
3:24 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


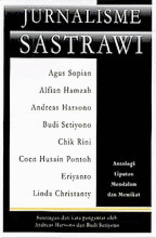


6 comments:
Ma’e medi mairewo tamenga gambar/foto. Jangan mengambil sesuatu kecuali gambar.
Ma’e tau mata rewo ta menga nala/hibu. Jangan membunuh sesuatu kecuali waktu.
Ma’e welutau rewota menga la’e/ola. Jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak.
Take nothing but picture.
Kill nothing but time.
Leave nothing but footprints.
Wah, keren! (Apakabar Mas Buset?)
di kalimantan pun banyak "danau": bekas galian macam-macam tambang. tadinya gunung, setelah dikeruk jadi "danau".
Idih hebat... ada buset di blogspot.
Bung, setidaknya lo punya kelebihan di banding si Boni... yaitu punya blog. Hahaha...
Salam dari Hoofddorp.
Ikram, aku baik-baik saja. Lagi belajar ngeblog. Mungkin ntar minta diajarin ganti banner. Salam
Sahrudin, hm, danau yang itu mesti "digali" jadi tulisan. Tapi memang butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit. Mau coba?
bangaiptop? Arief, bukan? Hei meneer, kok gak ada kabar berita?
ganti banner? siaaap.
eh, mas, kapan buku puisi clara akustia terbit nih?? kemarin malam aku ketemu mujib. Salam kenal kalau sudah lupa lagi (itu loh yang jangkung terus lihat2 buku mas di kebayoran lama :), hehehe)
Post a Comment