KABAR itu datang tiba-tiba: bapak sakit. Mama, putri satu-satunya bapak, memberitahuku sambil terisak. Sakit paru-paru bapak kambuh lagi. Nafasnya tersengal-sengal. Saya mendengarkannya dengan takzim sambil berusaha menghiburnya dengan kata-kata sederhana: “Bapak masih kuat, dan dia masih ingin mengobrol dengan nanda.”
Saya berada di Langsa, Aceh Timur, saat itu. Ada satu pekerjaan yang harus kuselesaikan. Sejauh itu, saya memang percaya bapak masih kuat. Sekalipun usianya sudah 82 tahun. Semangatnya masih tinggi. Ada cita-citanya yang juga belum tercapai: mensarjanakan masyarakat Indonesia. Itu bukan cita-cita di awang-awang semata. Hampir separuh hidupnya dibaktikannya untuk tujuan mulia itu.
Mama masih terus berkirim kabar soal kesehatan bapak, sementara mobil yang saya tumpangi terus melaju: transit di Medan, berjalan lagi ke Aceh Selatan, Meulaboh, hingga kembali ke Banda Aceh. Kata mama, bapak tak mau dibawa ke rumah sakit. Takut jika di jalan kesehatannya makin memburuk.
Butuh waktu tiga hari untuk meyakinkan bapak hingga akhirnya pada hari Minggu dia mau dibawa ke rumah sakit. Saya sudah berada di taksi menuju bandara ketika mobil ambulan rumah sakit yang membawa bapak meluncur ke Jakarta. Saya lega.
Lalu mama menelpon, lalu menelpon lagi karena bapak ingin bicara. Suaranya masih penuh energi. Kuat dan pasti. Pesan bapak masih sama seperti pesan yang selalu dia sampaikan setiap kali saya datang ke rumahnya di Hanjawar, Cianjur. Begitu pun ketika saya menengoknya di rumah sakit keesokan harinya.
Bapak sedang duduk di kursi, hal yang sebenarnya tak diperbolehkan dokter. Mungkin dia capek tergeletak terus di ranjang rumahsakit. Di sofa, ada keluarga Pramoedya Ananta Toer, penulis novel Tetralogi Bumi Manusia: Maimunah, istri Pram, dan Mbak Titi, anaknya. Komariyah, istri bapak, menemani mereka mengobrol.
Saya menjabat dan mencium tangannya sambil membisikkan nama saya di telinga kirinya. Lalu saya duduk di sofa yang bersebelahan dengan kursi bapak. Saya memijit tangannya, pelan.
”Ini siapa?”
Saya menjawab.
”Ini siapa?” Senyum mengembang di mulut bapak.
Saya tersenyum. Bapak masih suka bercanda. Ibu mendekat dan mengucapkan nama saya agak keras di telinga bapak. Lalu bapak diam sejenak.
”Kamu bisa tidak mengorganisasi wartawan, seniman, para mahasiswa. Bikin kelompok diskusi, membicarakan persoalan masyarakat.” Bapak mulai bicara.
”Kalau tidak bisa, berarti kamu sudah menjadi benalu!” Suaranya kencang. Posisi duduknya bergeser ke depan. Kedua kakinya yang semula bertumpu di kursi lain, diturunkan ke lantai. Tangannya menunjuk-nunjuk. ”Tapi ingat, kamu mau tahu atau tidak mau tahu, ikut atau tidak, hukum pantare itu akan terus berjalan. Sudah pasti terjadi.”
Ah bapak, selalu berapi-api ketika bercerita.
Lalu meluncurlah ceritanya tentang China, Venezuela, Bolivia, Argentina, dan sederet nama negara di Amerika Latin lainnya yang sedang bergerak menuju masyarakat sosialis. Dia kelihatan sangat bersemangat. Sebuah lagu dinyanyikannya dengan suara pasti, dengan tangan mengepal dan mengayunkannya seperti seorang dirigen. Saya tak tahu persis lagu-lagu itu. Terasa asing di telinga.
”Lihat aku nyanyi, aku nyanyi,” dia terkekeh. ”Apa gak edun. Bapak gak bisa nyanyi. Yang penyanyi itu Amir Pasaribu. Bapak mah bukan penyanyi.”
Mungkin karena lelah, bapak minta dipindahkan ke atas ranjang. Saya membantu mengangkatnya. Masih dengan posisi duduk, bapak menyanyi lagi. Dua buah lagu meluncur deras, penuh semangat. Hanya satu lagu yang bisa saya tahu: Internationale. Saya senang tapi juga miris, khawatir dengan semangat bapak yang meledak-ledak.
Akhirnya, bapak benar-benar lelah. Dia menyandarkan kepalanya ke bantal. Sejenak dia terdiam, seolah teringat kembali pada sakitnya. ”Bapak jadi ingat teman-teman bapak. Semuanya sudah gak ada lagi. Joebar Ajoeb, Henk Ngantung, Bakri Siregar, Basuki Resobowo, Njoto, Pram, ...... Bapak sendirian.” Bapak terdiam. Matanya menerawang ke langit-langit kamar.
Semua nama adalah seniman sezamannya, yang sama-sama menggerakkan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi kebudayaan yang pengaruhnya begitu luas di masa Orde Lama. Bapak adalah salah satu pendirinya, dan menjadi Sekjen pertama. Nama Amir Pasaribu tak disebutkan. Pasaribu masih hidup dan kini tinggal di Medan. Sama seperti bapak, dia juga sedang sakit dan pendengarannya terganggu. Dulu, bapak pernah berkolaborasi dengan Pasaribu; bapak membuat liriknya, Pasaribu komposisi musiknya. Beberapa bulan lalu Amir Pasaribu meraih penghargaan Akademi Jakarta untuk bidang musik.
Keluarga Pram hendak pamit pulang. Bapak kelihatan berusaha mencegahnya dengan mencandai mereka.
”Ini siapa?”
”Pacar bapak...,” ujar Ibu Komariyah. Rupanya sebelum saya datang bapak, sudah mencandai mereka.
”Mau ke mana? Di sini saja. Aku kan mertuamu. Aku yang menikahkan kau dengan Pram. Aku walinya.”
Maimunah hanya tersenyum.
Bapak yang mempengaruhi pemikiran Pram tentang dampak buruk kolonialisme dan banyak hal yang membuat Pram bergabung dengan Lekra. Bapak pula yang memberikan pekerjaan untuk Pram, menerjemahkan novel Maxim Gorky, Ibunda, yang uangnya cukup untuk hidup Pram setelah menikah.
Mereka tetap pulang dan berjanji akan datang lagi. Mereka bergantian memeluk bapak. Hangat.
Setelah itu saya memilih menyingkir ke beranda belakang. Ada mama di sana. Duduk di kasur lipat dengan wajah kuyu. Mama bercerita sambil menangis. Ratih Purwasih –penyanyi pop, yang sama seperti saya menjadi anak angkat mama– berusaha menenangkan mama. Saya hanya diam, terhanyut dalam suasana ini.
Menjelang tengah malam saya pulang sambil berjanji akan datang besok pagi untuk gantian menjaga bapak. Saya lihat bapak berusaha memejamkan matanya. Saya percaya bapak masih kuat. Seperti dulu, di tahun 1950-an, ketika dia menghadapi kondisi yang juga parah.
KALA itu bapak menjadi salah seorang ”kabinet pribadi” Bung Karno bersama BM Diah, MS Azhar, Sajuti Melik, Bung Tomo, dan Slamet Sumari (pemimpin redaksi Bintang Timur), untuk membantu persiapan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Nama resminya Komite Perdamaian. Karenanya, dia harus bolak-balik. Kadang-kadang di Istana Merdeka, kadang di Istana Bogor.
Suatu ketika, 8 Februari 1955, bapak mendapat panggilan dari Bung Karno agar segera ke Istana Bogor. Berangkatlah dia bersama teman-temannya dengan jeep Berita Indonesia. Dalam perjalanan, dia lebih banyak tidur ketimbang teman-temannya. Ketika memasuki daerah Cibarusa, Cibinong, tanpa terelakkan mobil yang mereka tumpangi menabrak sebuah truk di tikungan maut. Semua penumpangnya terlempar. Iren, MS Azhar, Ibrahim Isa, Joebaar Ajoeb, yang sempat melihat kejadian itu pun pingsan. Tak berapa lama mereka sadarkan diri. Tapi bapak, yang selama perjalanan memilih tidur, terlempar dengan posisi kepala dulu yang membentur jalanan yang beraspal. Dia pingsan agak lama, bahkan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat (dulu bernama CBZ, sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo).
Hampir semua rekannya kaget mendengar berita kecelakaan ini. Hendra Gunawan, pematung, yang sedang membikin patung Sudirman, terjatuh. Suhaimi Rakhman, dalam perjalanan dari Jakarta ke Bukit Tinggi, menulis sebuah surat, yang juga catatan perjalanan, dan kemudian diterbitkan di Harian Rakjat, 5 Maret 1955.
Bapak koma selama 2 bulan 1 hari. “Kata dokter rumah sakit, ini rekor,” ujar bapak. Dia juga tak bisa melihat kerja kerasnya. Konferensi Asia Afrika berjalan sukses dan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang memperkuat solidaritas di kawasan Asia Afrika.
Pada 14 April, kesehatan bapak membaik dan diizinkan meninggalkan rumah sakit. Dan dia tak perlu membayar biaya pengobatan. Menurut petugas administrasi, Bung Karno sudah membayar semuanya. Untuk memulihkan kondisinya, bapak beristirahat di pegunungan. Di sana bapak sempat menciptakan sebuah puisi berjudul “Harapan”:
Sunyi menyutera irama kenyenyakan
Kawan-kawan sekitar dalam rawatan
Masih jauh pagi bersemi
Malam makin memesra hati
Penuh harapan
Terpahat tegak dalam kandungan dada
Segala tanda kasih kawan-kawan diluar
Aku ini bukan sampah terbuang
Sebagian granit samudera massa
Intan fajar memerah.
Klara Akustia
(RSUP, hari akan istirahat)
Puisi ini dimuat di Harian Rakjat, 14 Mei 1955, dan kelak masuk dalam kumpulan puisi bapak: Rangsang Detik, yang diterbitkan Jajasan Pembaharuan pada 1957.
Ketika kesehatannya pulih, bapak kembali menjalani aktivitasnya, sebagai anggota Konstituante dan Sekretaris Jenderal Lekra. Tentu juga sebagai penyair, redaktur Zaman Baru, kritikus sastra.
Bapak sudah bercengkerama dengan maut. Tapi Tuhan masih memberikannya waktu. Masih banyak yang mesti dikerjakannya. Juga sekarang, ketika bapak tergeletak di Rumah Sakit UKI, Cawang.
”Bapak tak tahan di sini. Tak bisa kerja,” ujarnya lirih. Nafasnya masih tersengal-sengal, seolah oksigen di dunia ini sudah menipis.
Kerja, bagi bapak, adalah aktivitas yang membawa nikmat. Di masa remajanya dia ikut bersama teman-teman seusianya, keluar masuk hutan, bertempur melawan musuh. Di masa merdeka sepenuhnya, dengan sepeda kumbang, bapak tak bosan-bosannya menyambangi satu tempat ke tempat lainnya. Begitu banyak aktivitasnya: seorang penyair, kritikus sastra, wartawan, politikus, aktivis serikat buruh.... Mungkin itu pula yang membuat paru-parunya jadi bermasalah –meski mungkin juga menjadi bawaan lahir.
Sudah sejak lama bapak mengidap penyakit ini. Tak jelas sejak kapan bapak mulai merasakannya. Tapi menurut bapak, dia pernah berobat ke Medical Hall di Peking di zaman Mao Tse-Tung. Saya tak tahu istilah kedokterannya. Yang jelas, paru-paru bapak diberi benteng di sekelilingnya agar terlindungi dan masalahnya tak menjalar ke mana-mana. Tim dokter di Peking menyarankan agar sepuluh tahun kemudian bapak kembali untuk memeriksa ulang benteng tersebut.
Tapi kenyataan berbicara lain. Niat kembali ke Peking jadi tertunda. Peristiwa 30 September 1965, menutup rapat kesempatan tersebut. Mungkin faktor itu menjadi salah satu pemicu paru-parunya sering bermasalah.
Sekitar tahun 1992, penyakit ini pernah kambuh. Bapak segera mendapat perawatan di rumah sakit di Cianjur selama kurang lebih 10 hari. Dia ditangani oleh Dr Hudaya. Setelah sembuh, bahkan hingga sekarang, bapak lebih suka diperiksa oleh Dr Erwin Peetosutan, dokter yang berpraktik di RS MMC Jakarta. Alasannya jelas, dari sekian dokter yang ditemui bapak, hanya Dr Erwin yang memahami bagaimana cara menangani paru-paru bapak yang pernah ditangani dokter-dokter di Peking. Biasanya dua atau tiga bulan sekali bapak menemui Dr Erwin.
Selama saya berkunjung ke Cianjur, saya melihat tak ada masalah dengan paru-parunya. Bapak juga tak pernah mengeluhkannya. Tapi bapak masih rajin mengonsumsi obat. “Lihat ini aku sudah putus asa. Masak mesti minum obat ini sampai Agustus,” ujar bapak suatu ketika sambil menunjuk kapsul-kapsul dalam kotak plastik. Obat ini baru dikirim dari Hongkong, dan dibawa mama ke Cianjur.
Merasa lebih baik setelah ditangani Dr Erwin, lengahlah dia. Jadwal rutin memeriksakan kesehatan terabaikan. Sampai kejadian terburuk ini terjadi. Sakit paru-paru bapak kumat lagi. Jantung bapak juga terkena imbasnya: membengkak.
Nasi sudah jadi bubur. Paru-paru bapak sedang berusaha keras memasok oksigen. Selang infus tertancap di lengannya. Lengan lainnya sudah lebam kena tancapan jarum infus. Selang berwarna hijau mengalirkan oksigen lewat dua rongga hidungnya. Tabung oksigen cukup meringankan kerja paru-parunya, tapi juga tak bisa terus-menerus. Oksigen adalah racun, begitu kata Dr Joen, teman mama. Ia juga tak boleh terlalu banyak, tak baik jika melewati ambang batas 2.
Ya, nasih sudah menjadi bubur. Sekarang kesalahan ini harus ditebus, dengan menjaga dan merawat bapak sebaik-baiknya.
”Saya merasa prihatin dengan sakit yang dideritanya. Andaikata memungkinkan, ingin kuberikan saja paru-paruku kepadanya agar bapak bisa kembali sehat dan meneruskan segala pekerjaannya yang tertunda. Bagiku bapak lebih berarti daripada diriku sendiri,” ujar mama.
Saya percaya. Mama sudah mengatakannya berkali-kali. Mama pula yang menunjukkan perhatian selama bapak sakit.
”Ada rasa takut yang menghujam hatiku yang paling dalam; andaikata sesuatu yang lebih buruk terjadii, apa yang harus aku lakukan? Terus terang aku tak siap menghadapinya. Aku belum mampu membahagiakan bapak. Apalagi kalau aku teringat apa yang dikatakan Mang Atun (Ramadhan KH) agar aku menjaga bapak dengan baik.”
Dan malam itu mama harus ekstrakeras menjaga bapak. Bapak mengeluh. Dia tak bisa tidur. Mata begitu berat tapi nafasnya tersengal. Dia terus mengaduh.
SEHARIAN itu dia sudah terlalu banyak bicara. Setiap kali ada teman datang, tak bosan-bosannya dia bercerita. Saya baru tahu belakangan bahwa kondisi itu tak bagus bagi pemulihan kesehatannya. Tak boleh terlalu banyak bicara, tak boleh terlalu bersemangat. Tangis keluarga dan tawa kegembiraan sang bapak juga bisa membuat tensi darahnya melonjak.
Benar saja. Keesokan harinya bapak masuk ruang perawatan intensif (Intensive Care Unit atau ICU). Dalam istilah kedokteran, ini juga kata Dr June Luhulima, keluarga dinilai gagal menjaga dan merawat bapak. Tapi memang tak mudah menangani bapak. Kadang rewel, suka mencari perhatian. Tapi juga bandel. Bahkan kata-kata dokter tak harus diturutinya. Suster-suster di rumah sakit sudah tahu tabiat bapak. Dokter yang menangani bapak juga harus sabar mendengar omongan bapak tiap kali memeriksa.
Saya datang ke rumah sakit siang hari. Tapi bapak tak bisa dijenguk. Hanya ada waktu satu jam ketika magrib. Tak lama kemudian datang kawan-kawan bapak. Putu Oka, Amrus Natalsya, dan kawan-kawan lainnya. Keluarga memberi mereka kesempatan pertama memasuki ruang ICU begitu jam jenguk tiba. Dari pintu masuk ruangan, saya melihat bapak senang. Suaranya keras. Kadang tertawa.
Lalu kami berganti masuk. Saya melihat saja, berharap bapak tak mengajak saya bercerita. Takut bapak tak mau berhenti bicara. Pamela, anak pertama mama, sedang mengajaknya berbicara dalam bahasa Sunda. Bapak terkekeh-kekeh. Pengunjung lain melihat kami dengan tersenyum. Tapi waktu akan segera berakhir. Saya yakin bapak akan kembali tersiksa, dijauhkan dari keluarga.”Ruangan yang tak berperikemanusiaan,” begitulah istilah bapak.
Kami mengambil kapling di depan loket. Biasanya suster akan memanggil keluarga pasien dari loket ini, kemudian memberikan resep dokter. Ketika obat sudah di tangan, orang tersebut akan membunyikan bel agar si suster mengambil obat tersebut melalui loket. Tapi hari sudah malam. Aktivitas itu bisa dipastikan akan jauh berkurang. Di sinilah kami menggelar kasur dan meletakkan semua peralatan yang dibutuhkan.
Malam itu saya memutuskan menjaga bapak dari luar. Saya membawa laptop, sehingga bisa mengerjakan sesuatu. Yang lainnya tidur. Sesekali mama terbangun, menuju pintu ruang ICU, lalu merebahkan badan agar bisa mengintip bapak dari celah yang sempit.
Di sana bapak hanya sehari. Masa krisis berlalu dan dia bisa meninggalkan ruang ICU. Kami kembali menempati kamar VIP.
Tapi kondisi bapak sudah menurun, tidak sebaik ketika pertama masuk rumah sakit. Nada bicaranya terputus-putus. Setiap kali saya datang di malam hari, saya langsung menuju beranda belakang. Bersama mama dan Ratih. Ibu Komariyah, Pamela dan Alam (dua anak mama) tidur di dalam ruangan. Sesekali saya mengintip dari jendela ketika terdengar suara eluhan atau erangan.
”Anfal, anfal.... Aduh!.” Selalu begitu ketika bapak hendak buang air kecil. Mungkin bapak merasa kesakitan.
Sesekali bapak mengganti kata ”anfal” itu dengan ”ampun” atau ”attack”.
Meski belum sembuh, bapak ingin pulang. Sudah beberapa kali dia mengatakannya. Tak ada yang bisa menahannya terlalu lama. Dengan seizin dokter, bapak akhirnya diizinkan pulang. Semua keperluan bapak dipersiapkan. Tabung oksigen sudah dipesan. Juga mobil ambulan yang akan mengantarkan bapak pulang. Pulang memang konsep yang penuh magis, seperti pernah dikatakan Umar Kayam. Pulang berarti masuk kembali ke jagad lama yang sudah sangat bapak kenal: rumah, sejumput kenangan masa kecil, entah apa lagi.
Saya tak bisa mengantarnya pulang. Tapi saya berharap bapak akan segera sehat dan kembali berdiskusi dengan saya.
”Budi, kamu harus tegar. Tabah. Dalam perjuangan selalu dibutuhkan ketabahan.” Suara bapak lirih.
”Iya, Pak.” Saya mengatakannya sambil mendekatkan bibir saya di telinganya. ”Yang penting bapak sehat dulu, biar bisa ngobrol lagi sama Budi.”
Bapak mengangguk pelan. Matanya terpejam. Saya undur diri.
Malam itu, mama mengirim pesan pendek. Kami sudah sampai di rumah. Bapak akhirnya bisa tertidur pulas, bahkan sambil menyunggingkan senyuman. Mungkin bapak senang bisa pulang.*
Tuesday, January 30, 2007
Pulang
at
7:25 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


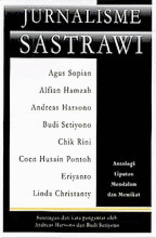


4 comments:
Semoga dirimu tabah. Semoga bapak diterima di sisi-NYA.
Btw, aku gak nyangka, tulisanmu penuh emosi seorang anak ketimbang penulis.
Bintang, ini memang hanya catatan personal. Tak banyak cerita tentang dirinya. Untuk yang itu, ya tunggu saja kalau biogafinya terbit. Tapi tentu saja sentuhan emosi ini perlu dalam tulisan narasi. Lebih hidup, lebih dekat, lebih menggugah.
Seorang penulis pada akhirnya adalah anak zaman kini, anak dari segala manusia dan persoalannya.
Aku menjabat dan mencium tangannya sambil membisikkan namaku di telinga kirinya. Lalu saya duduk di sofa yang bersebelahan dengan kursi bapak. Saya memijit tangannya, pelan.
(set, aku itu apane saya? hehe... kapan ke rumah lagi?)
Aulia, itu salah ketik. Awalnya aku menulis pake "aku" tapi akhirnya diganti pake "saya". Jadi, ada yang terlewat.
Nantilah kalau aku ke Semarang lagi, semoga bisa main. Aku masih di Cianjur sekarang. Minggu depan sudah mesti ke Flores.
Salam buat teman-teman dan binimu.
Post a Comment