KUDUS, 1918. Pada suatu malam, beberapa saudagar Tionghoa bertemu di Kudus Tua. Mereka membicarakan penyakit influenza yang tengah melanda Kudus dan menewaskan banyak orang di sana. Mereka berdiskusi mengenai bagaimana cara mencegah penyakit tersebut karena upaya yang dilakukan pemerintah tidak begitu berhasil. Penyakit influenza ini –kemudian dikenal dengan sebutan flu Spanyol— juga telah menewaskan puluhan juta orang di seluruh dunia, yang menunjukkan betapa ganasnya penyakit ini.
Setelah mengobrol kesana-kemari, akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan slamatan; sembayangan dan perarakan toapekkong dengan upacara.
Tepat pada waktu yang telah ditentukan, acara itu pun digelar. Perarakan pertama berjalan lancar. Begitu pula perarakan kedua dan ketiga yang diadakan beberapa hari kemudian. Penduduk pribumi sepertinya senang mendapatkan hiburan gratis yang meriah.
Tapi, perarakan terakhir pada tanggal 30 Oktober, berakhir rusuh. Terjadi keributan kecil akibat ulah beberapa orang pribumi yang menertawakan rombongan perarakan. Tindakan ini dibalas dengan tempelengan oleh orang Tionghoa yang tak bisa menahan amarahnya. Penghinaan balasan juga dilakukan. Suasana jadi memanas, tapi perselisihan itu kemudian bisa dilerai, bahkan dengan kesepakatan damai.
Tapi, api telah membakar sekam. Kesepakatan itu tinggallah janji kosong belaka. Perselisihan yang terjadi pada siang hari di dekat menara Kudus itu rupanya membangkitkan dendam lama yang sempat terpendam di hati sebagian penduduk pribumi, terutama pedagang kayanya. Sejak lama, kemajuan usaha rokok dan batik mereka tersendat akibat kalah bersaing dengan pengusaha Tionghoa. Bahkan banyak pekerja pribumi yang pindah ke pengusaha Tionghoa yang mau memberi gaji lebih besar. Dari perselisihan itulah mereka mendapat momentum yang pas untuk melampiaskan dendamnya. Dengan memanfaatkan pengaruh Sarekat Islam (SI), organisasi politik beraliran Islam yang berkembang pesat di masa itu, pemimpin SI cabang Kudus yang kebanyakan haji dan pedagang kaya merencanakan pembalasan dendam.
Keesokan harinya, pada suatu malam, mereka mengumpulkan orang-orang dari Demak, Mayong, juga Welahan, yang kemudian disebar dalam kelompok-kelompok di wilayah pecinan, terutama di Kudus Tua. Begitu suara batu berdentangan di atap-atap rumah orang Tionghoa sebagai tanda perintah penyerangan, dimulailah aksi mereka. Rumah-rumah dihujani dengan batu. Pintu dan jendela didobrak. Perabotan diporakporandakan, dan beberapa di antaranya dijarah. Bensin dan minyak tanah disiram, lalu dinyalakan dengan api. Dengan cepat deretan rumah itu terbakar dan menghanguskan isinya.
Kepanikan menyelimuti wajah penduduk Tionghoa yang rumahnya menjadi sasaran penyerangan maupun tidak. Mereka berhamburan dari rumah untuk menyelamatkan diri. Sebagian bersembunyi. Nyaris tanpa perlawanan. Bahkan beberapa opas pribumi yang berdatangan untuk meredam kerusuhan mengurungkan niatnya karena jumlahnya kalah banyak. Kerusuhan baru bisa dipadamkan setelah beberapa jam kemudian datang bantuan polisi dari Semarang yang dipimpin komisaris besar Reumpol. Mereka bertindak cepat. Seketika itu juga massa membubarkan diri, dan beberapa di antaranya ditangkap.
Tapi ketakutan masih bergelayut di benak orang-orang Tionghoa. Saat itu juga mereka bergerak ke arah Semarang dengan berjalan kaki. Beruntung kemudian datang mobil-mobil bantuan dari Ing Giap Hwe, perkumpulan orang muda Tionghoa di Semarang. Ing Giap Hwe juga menyediakan penginapan dan uang makan selama mereka di Semarang. Untuk keperluan itu, datang pula bantuan dari orang Tionghoa di beberapa tempat, yang kemudian dikumpulkan oleh komite Fonds Koedoes yang didirikan di Semarang, Surabaya, dan Jakarta.
Terhadap kerusuhan tersebut, perkumpulan Tionghoa menyesalkan sikap para pejabat setempat karena tidak adanya jaminan keamanan. Dalam sebuah konferensi untuk membicarakan masalah Kudus, yang dihadiri perkumpulan-perkumpulan Tionghoa dari beberapa daerah, diambil keputusan antara lain bahwa masalah tersebut tidak dihubungan dengan politik dalam negeri, mengangkat komisi untuk memprotes dan menekan pemerintah, meminta hukuman yang layak bagi para pelaku, serta melakukan upaya agar orang Tionghoa bisa hidup rukun dengan orang pribumi.
SI, terutama pemimpin SI Kudus dan beberapa anggotanya, dianggap terlibat dalam kerusuhan di Kudus ini. SI melalui organ resminya, Oetoesan Hindia yang terbit di Surabaya dan Sinar Hindia (Semarang) membela diri dan menuding orang Tionghoa sebagai pencetusnya. Sebaliknya, perhimpunan Tionghoa menuding SI. Pertikaian politik itu akhirnya bisa reda setelah pada 30 November 1919 terjadi pertemuan yang diprakarsai Tjokroaminoto, pemimpin SI Surabaya, di gedung Tiong Hoa Oen Tong Hwee di Molenvliet, Batavia.
KUDUS, 1919. Tan Boen Kim bersama Tjiong Koen Liong, pemilik percetakan Goan Hong & Co. di Betawi, mendatangi Kudus yang telah dilanda kerusuhan rasial anti-Tionghoa. Mereka hendak mencari keterangan lebih jauh tentang kerusuhan tersebut dengan mewawancarai banyak orang di sana. Mereka tak peduli besarnya biaya yang harus ditanggung, asal bisa mendapatkan keterangan dan bahan-bahan penting untuk membuat sebuah buku. Keduanya datang ketika perselisihan antara Sarekat Islam dan perhimpunan Tionghoa sudah rampung.
Proses pemeriksaan terhadap terdakwa kerusuhan tersebut masih berlanjut. Enampuluh sembilan orang telah ditangkap dan dipenjara, beberapa di antaranya pemuka agama di Kudus. Selang 15 bulan kemudian, mereka diperiksa di pengadilan. Mereka dijatuhi hukuman antara sembilan bulan sampai limabelas tahun kurungan potong tahanan. Tujuh orang dibebaskan.
Berdasarkan wawancara dengan banyak orang, ditambah dengan pemberitaan pers, keterangan polisi, dan proses verbal di pengadilan, Tan Boen Kim menuliskan peristiwa rasial di Kudus itu menjadi sebuh buku berjudul Peroesoehan di Koedoes, yang kemudian diterbitkan percetakan Goan Hong & Co pada 1920. Percetakan Goan Hong & Co. memang biasa menerbitkan ceita-cerita baru dari kejadian sesungguhnya, selain juga menerbitkan rupa-rupa cerita Tionghoa, buku pelajaran, syair, pantun, undang-undang, dan sebagainya.
Peroesoehan di Koedoes menjadi catatan sejarah yang penting, yang menggambarkan betapa sentimen rasial sudah hidup lama di negeri ini, bahkan menunjukkan bentuknya dalam beberapa kerusuhan rasial anti-Tionghoa. Kerusuhan rasial seperti api dalam sekam. Dipicu masalah sepele saja kerusuhan itu bisa meletus. Umumnya timbul terutama karena sentimen dagang; orang Tionghoa dipandang sebagai penghalang usaha ekonomi pribumi. Kerusuhan kali pertama terjadi di Solo, yang saat itu menjadi pusat kapital, produksi, dan perdagangan batik. Kemudian menjalar seperti api di beberapa tempat di tanah air; Bangil, Tuban, Rembang, Cirebon, dan Kudus.
Di Kudus kerusuhan terjadi pada 31 Oktober 1918. Kejadiannya jauh lebih besar karena meliputi hampir seluruh kota yang disertai pembakaran pecinan, perampokan, dan pembunuhan. Latar belakangnya karena sentimen dagang yang sudah berlangsung lama. Perkembangan perusahaan rokok dan batik milik Tionghoa mengkhawatirkan pengusaha pribumi, terutama yang dikelola para haji.
Tan Boen Kim menyadari bahwa sentimen rasial ini sulit untuk dipadamkan. Karena itu dalam pengantar bukunya, Peroesoehan di Koedoes, ia mengingatkan “bagimana bintjana ada deket sekali, djika boeat lakoekan satoe perboeatan orang tida maoe pikir lebih djaoe”. Ia tak ingin sejarah kelam seperti di Kudus tidak terulang lagi.
TAN BOEN KIM terbilang penulis produktif di zamannya. Menurut Claudine Salmon dalam Literature In Malay by The Chinese of Indonesia, tidak jelas apakah ia pernah menerima pendidikan formal. Dilahirkan pada 1887, lelaki ini menjadi penulis dan wartawan secara otodidak. Pernah bekerja sebagai jurutulis di sebuah bank, ia mulai menulis untuk Sin Po, tempat ia biasa menyumbangkan karangannya berupa “pidato mingguan” berjudul Zaterdagsch Causerie dengan nama pena Indo China.
Ia lalu malang-melintang di dunia jurnalistik. Sekitar tahun 1916 ia diminta untuk memegang jabatan direktur dari harian Thjioen Thjioe yang didirikan di Surabaya pada 1914. Tak lama kemudian ia kembali ke Batavia, dan pada 1917 menjadi editor mingguan Ien Po. Pada 1926, ia tinggal di Palembang selama beberapa bulan, dan bekerja untuk mingguan Kiao Po. Sebagai jurnalis, Tan Boen Kim kritis. Gaya tulisannya penuh sarkasme, sehingga membuat banyak musuhnya tak ragu untuk menggunakan kekerasan untuk melawannya. Ya, ia bahkan dipenjara beberapa kali karenanya. Dalam bahasa Wartawan P.W. dalam Pantja Warna, “Tan Boen Kim kenjang dibatjok dan keluar masuk pendjara”.
Novel pertama Tan Boen Kim tampaknya telah dipublikasikan pada 1912. Belakangan ia menulis banyak kisah besar yang didasarkan pada peristiwa aktual atau soeatoe tjerita jang betoel terdjadi pada waktoe jang belon sebrapa lama, seperti perampokan dan pembunuhan. Salah satunya yang terkenal adalah Nona Fientje de Feniks (1915) yang berkisah tentang pembunuhan pelacur terkenal Fientje de Feniks. Novel ini mendapat perhatian banyak orang, sehingga mengalami cetak ulang. Bahkan Tan Boen Kim akhirnya menulis sambungannya; Njai Aisah atawa djadi korban dari rasia (1915) dan G. Brinkman atawa djadi korban dari perboetannja (1915). Kisah Fientje de Feniks ini juga kemudian ia gubah menjadi syair berjudul Sair Nona Fientje de Feniks dan sekalian ia poenja korban jang benar terdjadi di Betawi antara taon 1912-1915. Artinya, Tan Boen Kim juga mulai mencoba menulis syair. Tapi, ia mengaku mengalami kesulitan ketika menulis syair. “Menulis sebuah syair dalam sajak enam baris sungguh urusan amat sulit. Sebuah syair tidak bisa berbicara sebaik sebuah kisah dalam prosa, karena sangat hemat kata. Jika Anda ingin memahaminya lebih jernih, saya menganjurkan –dengan semua respek—agar Anda membaca versi prosanya,” ujarnya.
Tan Boen Kim menulis kerusuhan anti-Tionghoa seperti Peroesoehan di Koedoes yang menggambarkan masalah di Kudus pada 1918 ketika perusahaan-perusahaan rokok dan batik milik Tionghoa mengkhawatirkan dan berkompetisi dengan pengusaha santri. Kebanyakan novelnya memang berkisah mengenai masyarakat Tionghoa Peranakan dengan mengambil setting Indonesia.
Ketertarikannya pada negara China mendorongnya untuk menerjemahkan beberapa novel, bahkan menulis biografi Sun Yat Sen. Perlu disebutkan pula koleksi pidatonya Tan Boen Kim’s Pridato yang memberikan bermacam keadaan yang muncul pada 1929. Buku ini dicetak ulang pada 1931 yang juga berisi pidato tokoh nasionalis Indonesia seperti Ki Hadjar Dewantara, Mohammad Hatta, dan sebagainya. Pada akhir hidupnya dia tertarik astrologi, dan menerbitkan beberapa buku tentang topik tersebut.
Tan Boen Kim menjalani tahun-tahun terakhir hidupnya dengan kemelaratan; tinggal di dalam sebuah ruangan Jinde yuan, satu dari kelenteng Tionghoa tertua di Kota, Jakarta, hingga meninggal pada 1959.
Saya terkenang Tan Boen Kim setelah menemukan karyanya di atas tumpukan buku dan makalah yang berceceran. Saya senang Tan Boen Kim telah mencatatkan peristiwa rasial anti-Tionghoa di Kudus agar bisa dijadikan pelajaran. Membaca Peroesoehan di Koedoes, bagi saya, seperti membaca sebuah novel yang penuh detil. Ini tak lepas dari kemauannya untuk datang ke lokasi kejadian untuk melihat langsung dampak kerusuhan, mencari data dan wawancara. Tan Boen lalu Kim menuliskannya dengan gaya bertutur sehingga enak dibaca. Ketegangan, kecemasan, kepedihan, dan konflik bergulir dalam jalinan cerita yang rapi dan terjaga.
Sayangnya, penulis hanya mengulas latar belakang peristiwa dari kacamata ekonomi. Aspek politis atau kekuasaan tidak disinggung sedikit pun kecuali faktor keamanan yang kurang memadai dan faktor ekonomi. Dan tentu saja ada bias penulisan di sana-sini karena latar belakang penulisnya sebagai orang Tionghoa, pihak yang menjadi korban dari peristiwa itu –meski ini juga bisa menjadi sebuah kelebihan.
Tapi, saya juga sedih ketika sadar bahwa apa yang diharapkan penulisnya tak terwujud. Peristiwa rasial kembali meletus di Indonesia, tepatnya Mei 1998. Saat itu di beberapa tempat, terutama Jakarta dan Solo, puluhan rumah dan toko milik orang Tionghoa dirusak, dibakar, dijarah isinya. Kabarnya beberapa gadis diperkosa. Sejarah pun kembali mencatat: untuk kali kesekian, kerusuhan rasial anti-Tionghoa terjadi di Indonesia.
Seandainya masih hidup, Tan Boen Kim mungkin merasakan kepedihan yang sama, dan mungkin pula mencatatkan kembali peristiwa kelam tersebut.*
Wednesday, November 22, 2006
Tan Boen Kim
at
12:16 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


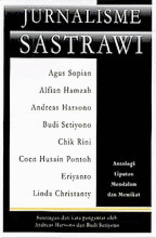


4 comments:
apa kabar, mas buset?
Sahrudin, kabarku baik-baik saja. Selama ini memang lebih banyak berurusan dengan buku. Di Pantau mengedit berita selain mengajar kursus. Kangen juga sih menulis lagi buat majalah.
Hm, tulisan-tulisanmu di webblog memikat. Ayo dong terus menulis dan mencoba masuk media.
mas boleh tau buku referensinya ? saya lagi nyari informasi tentang konflik cina vs pribumi tahun 1918 hubungannya sama SI
mas boleh tau buku referensinya ? saya sedang mencari informasi tersebut untuk penelitian. terimakasih
Post a Comment