BIASANYA saya akan tiba dini hari. Di dalam bus, saya akan bersiap turun ketika melintasi jembatan Sungai Pemali. Jembatan itu ibarat landmark kota ini bagi saya; bukan alun-alun tak jauh dari situ, yang terlihat sama seperti alun-alun di kota-kota lain di Jawa.
Saya turun sesampai di pasar. Sejumlah abang becak menyambut, berebut menawarkan jasa. Saya memilih yang duluan mendekat. Saya naik, meluruskan kaki, lalu menghirup udara kota ini dalam-dalam sembari sesekali menghembuskan asap rokok.
Apa arti sebuah kota kecil bagi saya? Kecuali keluarga, dan sejumput kenangan masa kecil, adakah yang bisa dan mampu menggerakkan saya untuk (ingin) kembali? Teman, entah ke mana pergi. Semuanya mungkin sama seperti saya, merantau ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan, seperti seekor itik yang suka mengelana. Kenangan saya pada kota ini amatlah tipis.
Saya terlahir ketika Indonesia tengah getol-getolnya membuka diri dari modal asing. Sebuah demontrasi besar pun muncul yang berujung rusuh: Peristiwa 15 Januari atau Malari. Peristiwa itu tak menyurutkan langkah pemerintahan Soeharto untuk meneruskan kebijakannya. Di sisi lain, Indonesia sedang berada di puncak kemakmuran akibat lonjakan harga minyak.
Tapi kemakmuran hanyalah milik segelintir orang kaya. Saya, yang lahir tak lama setelah Malari, tetap menjalani hidup layaknya anak-anak seusia saya di kota ini. Hidup sederhana. Kehadiran saya menambah sesak rumah milik orangtua saya. Kami tidur berhimpitan dalam sebuah kamar.
Modal belum juga singgah di kota ini. Baru pada 1980, modal berdatangan untuk mengembangkan usaha pertambakan. Pemilik uang memanfaatkan daerah rawa-rawa dan menjadikan kota ini sebagai penghasil utama udang windu dan bandeng terbesar di Jawa Tengah. Adakah pengaruhnya bagi kota saya? Hingga kini kota ini masih dianggap kota tertinggal di Jawa Tengah.
Modal belum juga singgah di kota ini. Baru pada 1980, modal berdatangan untuk mengembangkan usaha pertambakan. Pemilik uang memanfaatkan daerah rawa-rawa dan menjadikan kota ini sebagai penghasil utama udang windu dan bandeng terbesar di Jawa Tengah. Adakah pengaruhnya bagi kota saya? Hingga kini kota ini masih dianggap kota tertinggal di Jawa Tengah.
Dan sepanjang saya kenal, kota ini tak pernah berubah.
KOTA ini sudah tercatat dalam arsip-arsip VOC. Saat itu daerah ini menjadi pemasok kayu jati yang merupakan bagian dari kerjasama VOC-Mataram. Bahkan, pada awal abad ke-16 VOC membangun pengergajian yang digerakkan angin. Di masa VOC ini pula Brebes diakui sebagai sebuah kabupaten, dipisahkan dari wilayah kabupaten Tegal pada 1678. Pemisahan itu dilakukan atas desakan Sunan Amangkurat II dengan alasan ancaman pemberontakan.
Tak banyak catatan sejarah tentang kota ini selain urusan politik dan pemerintahan. Sejumlah peristiwa menunjukkan dinamika kehidupan kota: kerusuhan rasial di awal kemerdekaan, revolusi sosial yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Tiga Daerah, penumpasan DI/TII, hingga penghancuran gerakan komunis.
Kalaupun ada, kota ini hanya masuk dalam lintasan sejarah. Kota ini punya hubungan khusus dengan satu nama besar yang menjadi pelopor sandiwara modern dan mempengaruhi perkembangan musik keroncong di Indonesia: August Mahieu, dengan kelompok Komedie Stamboel-nya.
Komedie Stamboel kali pertama muncul di Surabaya pada 1891. Pelopornya adalah August Mahieu, seorang Indo-Prancis. Komedie Stamboel menarik minat penonton seantero Hindia Belanda, bahkan hingga Singapura. Biasanya mereka bermain di alun-alun kota atau kompleks perkebunan.
Dalam sebuah tour keliling Jawa, Sinar Stamboel –kelak berubah nama menjadi Komedie Sinar India– pernah mampir di Brebes. Bintang Soerabaia, sebagaimana dikutip Matthew Isaac Cohen dalam The Komedie Stamboel: popular theater in colonial Indonesia, 1891-1903, melaporkan kelompok itu tampil di sebuah tenda di barat-laut area pasar, mungkin wilayah pecinan. Mereka menghadirkan "enam perempuan Eropa, empat perempuan Muslim, empat lelaki Belanda, dan orang-orang dari ras lain". Di sini, mereka mengenakan kostum dan latar panggung yang benar-benar baru serta menampilkan drama pertunjukan seperti Ali Babi dan Perang Lombok. Untuk kursi kelas tiga, penonton cukup membayar 25 sen. Penonton berjubel. Namun keuntungan di Brebes menurun oleh hujan dan reputasi para pemain yang garang: penonton perempuan melaporkan bahwa mereka enggan menonton karena takut perkelahian pecah.
Pada 14 Januari 1903, Mahieu kembali mengunjungi Brebes untuk menggelar pertunjukan. Dia tiba di Bumiayu dengan rombongan sandiwaranya, Sinar India. Kedatangannya mengejutkan warga Bumiayu. Kondisi kesehatannya memburuk. Kehidupan yang dia habiskan di jalan menguras tenaganya, dan sejumlah penyakit terus-menerus mengintipnya. Penyakit sudah lama menghinggapi tubuh Mahieu dan anggota rombongannya yang lain. Di sini penyakitnya kian parah.
Menurut Matthew Isaac Cohen, malaria lagi mewabah di kota Brebes. Di dekat Tanjung, yang berpenduduk 300 jiwa pada akhir 1902, tercatat 50 orang meninggal dunia karena malaria antara 1-13 Januari 1903. Malaria pula yang kemudian menghinggapi tubuh Mahieu. Mahieu meninggal dunia pada atau sekitar 24 Januari 1903.
Kematian Mahieu kali pertama diberitakan suratkabar De Locomotief pada 31 Januari 1903. Beberapa bulan kemudian, Bondsblad, 11 Juli 1903, menurunkan laporan panjang tentang kematiannya: “Dia mengalami serangan malaria di sini, sakit selama tiga hari, dan meninggal dunia. Sebuah kematian yang menyedihkan! Dirundung kemiskinan dan menginap di sebuah rumah Jawa yang kotor bersama rombongannya, dia menghembuskan nafas terakhirnya di bale-bale pada suatu malam pada 24 Januari. Sepenuhnya ditinggalkan, jauh dari dari keluarga dan teman-temannya, dia menemukan kuburannya sendiri yang terpencil di Bumiayu, sebuah makam yang belum ditandai oleh batu.”
Saya tak tahu apakah jejak Mahieu masih tersisa di Bumiayu –seperti halnya makam Van De Jong yang mengelola perkebunan teh Kaligua di masa Belanda. Saya juga tak tahu pengaruhnya bagi kesenian di kota ini. Tapi seyogyanya, denyut kegiatan seni dan budaya menjadi warna sebuah kota.
Dalam sebuah laporan di majalah Tempo, 7 April 1973, Bumiayu –saya kira seperti juga daerah lainnya– sebelum 1965 ramai dengan kegiatan kesenian. Di sana ada 13 organisasi orkes Melayu, lebih dari 10 perkumpulan keroncong, beberapa buah band, perkumpulan akrobatik, angklung paduan suara, orkes terbang (rebana besar), perkumpulan sandiwara, perkumpulan tari, hingga kesenian rakyat seperti jaran ebeg (kuda lumping), wayang, ketoprak, dan tari-tarian. “Semua kegiatan itu timbul berbarengan karena adanya organisasi-organisasi pendukung yang satu sama lain saling berlomba. Yakni Lesbumi, LKI dan Lekra,” tulis Tempo.
Masa itu, ketika politik menjadi panglimanya, kesenian memiliki lahan yang subur dan menjadi salah satu alat penyadaran masyarakat. Kesenian tradisional dan modern tumbuh bersama. Beragam organisasi memberi warna bagi perkembangannya. Ada persaingan. Terkadang intrik dan adu kuasa. Tapi dinamika itulah yang menghidupkan sebuah kota, mendorong kreativitas orang-orang yang hidup di dalamnya.
Peristiwa 1965 menjadi titik kemunduran. Pemerintah Orde Baru bukan hanya menghancurkan organisasi komunis tapi juga pemikiran dan kreativitas berkesenian. Imbasnya, kesenian tradisional mengalami kemandegan, atau hanya menjadi pengisi acara seremonial. Banyak studi yang mengkaji masalah ini. Kondisi ini juga juga terasa di sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk para penentu kebijakan kesenian di Jakarta: Bumiayu.
“Bumiayu barangkali sebuah potret kecil untuk setiap pelosok negeri ini. Potensi kesenian untuk menghibur banyak. Bakat-bakat ada, kebutuhan ada. Tetapi tempat tak ada dan semangat kelihatannya seret, dengan berkurangnya kegiatan organisasi tempat bergantung,” tulis Tempo.
Kesenian semestinya mewarnai kehidupan sebuah kota.
SUNGGUH, menelusuri jejak kota ini seperti memungut remah-remah. Tak banyak yang saya ingat. Saya menghabiskan masa kecil dengan bermain. Di rumah, ketika hujan mengguyur, kami bermain congklak, bekel, cublak-cublak suweng, atau sluku-sluku bathok. Nyanyian anak-anak itu masih terngiang di benak –dan mengingatkan banyak orang tentang kehidupan dan kematian.
Sluku-sluku bathok
Bathoke ela-elo
Si Rama menyang solo
Oleh-olehe payung motha
Mak jenthir lo lo lo bah
Wong mati ora obah
Nek obah medeni bocah
Nek urip goleko duwit
Di halaman depan rumah, di sebuah tanah lapang, kami bermain benteng-bentengan, gobak sodor, pakpakdor, gasing, mobil-mobilan dari kulit jeruk, dan banyak lagi. Terkadang, kami bermain wayang kertas atau wayang suket (terbuat dari daun pohon ketela).
Jika ramadhan tiba, malam berubah menjadi lautan pelita. Hampir di beranda setiap rumah, berderet pelita dari bambu. Anak-anak juga punya obor sendiri, terbuat dari bunga kapuk. Meriam bambu lalu menyemarakkan malam. Juga terikan kaget pelintasan jalan ketika kakinya melanggar seutas tali yang tersambung dua kaleng berisi kerikil.
Dengan dolanan anak, saya tak hanya beroleh keceriaan tapi juga belajar kebersamaan, solidaritas, dan sportivitas. Dolanan anak juga tak bias gender; laki-laki dan perempuan bermain bersama. Adakah anak-anak zaman sekarang memainkannya?
KOTA ini sudah tercatat dalam arsip-arsip VOC. Saat itu daerah ini menjadi pemasok kayu jati yang merupakan bagian dari kerjasama VOC-Mataram. Bahkan, pada awal abad ke-16 VOC membangun pengergajian yang digerakkan angin. Di masa VOC ini pula Brebes diakui sebagai sebuah kabupaten, dipisahkan dari wilayah kabupaten Tegal pada 1678. Pemisahan itu dilakukan atas desakan Sunan Amangkurat II dengan alasan ancaman pemberontakan.
Tak banyak catatan sejarah tentang kota ini selain urusan politik dan pemerintahan. Sejumlah peristiwa menunjukkan dinamika kehidupan kota: kerusuhan rasial di awal kemerdekaan, revolusi sosial yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Tiga Daerah, penumpasan DI/TII, hingga penghancuran gerakan komunis.
Kalaupun ada, kota ini hanya masuk dalam lintasan sejarah. Kota ini punya hubungan khusus dengan satu nama besar yang menjadi pelopor sandiwara modern dan mempengaruhi perkembangan musik keroncong di Indonesia: August Mahieu, dengan kelompok Komedie Stamboel-nya.
Komedie Stamboel kali pertama muncul di Surabaya pada 1891. Pelopornya adalah August Mahieu, seorang Indo-Prancis. Komedie Stamboel menarik minat penonton seantero Hindia Belanda, bahkan hingga Singapura. Biasanya mereka bermain di alun-alun kota atau kompleks perkebunan.
Dalam sebuah tour keliling Jawa, Sinar Stamboel –kelak berubah nama menjadi Komedie Sinar India– pernah mampir di Brebes. Bintang Soerabaia, sebagaimana dikutip Matthew Isaac Cohen dalam The Komedie Stamboel: popular theater in colonial Indonesia, 1891-1903, melaporkan kelompok itu tampil di sebuah tenda di barat-laut area pasar, mungkin wilayah pecinan. Mereka menghadirkan "enam perempuan Eropa, empat perempuan Muslim, empat lelaki Belanda, dan orang-orang dari ras lain". Di sini, mereka mengenakan kostum dan latar panggung yang benar-benar baru serta menampilkan drama pertunjukan seperti Ali Babi dan Perang Lombok. Untuk kursi kelas tiga, penonton cukup membayar 25 sen. Penonton berjubel. Namun keuntungan di Brebes menurun oleh hujan dan reputasi para pemain yang garang: penonton perempuan melaporkan bahwa mereka enggan menonton karena takut perkelahian pecah.
Pada 14 Januari 1903, Mahieu kembali mengunjungi Brebes untuk menggelar pertunjukan. Dia tiba di Bumiayu dengan rombongan sandiwaranya, Sinar India. Kedatangannya mengejutkan warga Bumiayu. Kondisi kesehatannya memburuk. Kehidupan yang dia habiskan di jalan menguras tenaganya, dan sejumlah penyakit terus-menerus mengintipnya. Penyakit sudah lama menghinggapi tubuh Mahieu dan anggota rombongannya yang lain. Di sini penyakitnya kian parah.
Menurut Matthew Isaac Cohen, malaria lagi mewabah di kota Brebes. Di dekat Tanjung, yang berpenduduk 300 jiwa pada akhir 1902, tercatat 50 orang meninggal dunia karena malaria antara 1-13 Januari 1903. Malaria pula yang kemudian menghinggapi tubuh Mahieu. Mahieu meninggal dunia pada atau sekitar 24 Januari 1903.
Kematian Mahieu kali pertama diberitakan suratkabar De Locomotief pada 31 Januari 1903. Beberapa bulan kemudian, Bondsblad, 11 Juli 1903, menurunkan laporan panjang tentang kematiannya: “Dia mengalami serangan malaria di sini, sakit selama tiga hari, dan meninggal dunia. Sebuah kematian yang menyedihkan! Dirundung kemiskinan dan menginap di sebuah rumah Jawa yang kotor bersama rombongannya, dia menghembuskan nafas terakhirnya di bale-bale pada suatu malam pada 24 Januari. Sepenuhnya ditinggalkan, jauh dari dari keluarga dan teman-temannya, dia menemukan kuburannya sendiri yang terpencil di Bumiayu, sebuah makam yang belum ditandai oleh batu.”
Saya tak tahu apakah jejak Mahieu masih tersisa di Bumiayu –seperti halnya makam Van De Jong yang mengelola perkebunan teh Kaligua di masa Belanda. Saya juga tak tahu pengaruhnya bagi kesenian di kota ini. Tapi seyogyanya, denyut kegiatan seni dan budaya menjadi warna sebuah kota.
Dalam sebuah laporan di majalah Tempo, 7 April 1973, Bumiayu –saya kira seperti juga daerah lainnya– sebelum 1965 ramai dengan kegiatan kesenian. Di sana ada 13 organisasi orkes Melayu, lebih dari 10 perkumpulan keroncong, beberapa buah band, perkumpulan akrobatik, angklung paduan suara, orkes terbang (rebana besar), perkumpulan sandiwara, perkumpulan tari, hingga kesenian rakyat seperti jaran ebeg (kuda lumping), wayang, ketoprak, dan tari-tarian. “Semua kegiatan itu timbul berbarengan karena adanya organisasi-organisasi pendukung yang satu sama lain saling berlomba. Yakni Lesbumi, LKI dan Lekra,” tulis Tempo.
Masa itu, ketika politik menjadi panglimanya, kesenian memiliki lahan yang subur dan menjadi salah satu alat penyadaran masyarakat. Kesenian tradisional dan modern tumbuh bersama. Beragam organisasi memberi warna bagi perkembangannya. Ada persaingan. Terkadang intrik dan adu kuasa. Tapi dinamika itulah yang menghidupkan sebuah kota, mendorong kreativitas orang-orang yang hidup di dalamnya.
Peristiwa 1965 menjadi titik kemunduran. Pemerintah Orde Baru bukan hanya menghancurkan organisasi komunis tapi juga pemikiran dan kreativitas berkesenian. Imbasnya, kesenian tradisional mengalami kemandegan, atau hanya menjadi pengisi acara seremonial. Banyak studi yang mengkaji masalah ini. Kondisi ini juga juga terasa di sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk para penentu kebijakan kesenian di Jakarta: Bumiayu.
“Bumiayu barangkali sebuah potret kecil untuk setiap pelosok negeri ini. Potensi kesenian untuk menghibur banyak. Bakat-bakat ada, kebutuhan ada. Tetapi tempat tak ada dan semangat kelihatannya seret, dengan berkurangnya kegiatan organisasi tempat bergantung,” tulis Tempo.
Kesenian semestinya mewarnai kehidupan sebuah kota.
SUNGGUH, menelusuri jejak kota ini seperti memungut remah-remah. Tak banyak yang saya ingat. Saya menghabiskan masa kecil dengan bermain. Di rumah, ketika hujan mengguyur, kami bermain congklak, bekel, cublak-cublak suweng, atau sluku-sluku bathok. Nyanyian anak-anak itu masih terngiang di benak –dan mengingatkan banyak orang tentang kehidupan dan kematian.
Sluku-sluku bathok
Bathoke ela-elo
Si Rama menyang solo
Oleh-olehe payung motha
Mak jenthir lo lo lo bah
Wong mati ora obah
Nek obah medeni bocah
Nek urip goleko duwit
Di halaman depan rumah, di sebuah tanah lapang, kami bermain benteng-bentengan, gobak sodor, pakpakdor, gasing, mobil-mobilan dari kulit jeruk, dan banyak lagi. Terkadang, kami bermain wayang kertas atau wayang suket (terbuat dari daun pohon ketela).
Jika ramadhan tiba, malam berubah menjadi lautan pelita. Hampir di beranda setiap rumah, berderet pelita dari bambu. Anak-anak juga punya obor sendiri, terbuat dari bunga kapuk. Meriam bambu lalu menyemarakkan malam. Juga terikan kaget pelintasan jalan ketika kakinya melanggar seutas tali yang tersambung dua kaleng berisi kerikil.
Dengan dolanan anak, saya tak hanya beroleh keceriaan tapi juga belajar kebersamaan, solidaritas, dan sportivitas. Dolanan anak juga tak bias gender; laki-laki dan perempuan bermain bersama. Adakah anak-anak zaman sekarang memainkannya?
Pengaruh budaya asing perlahan merembes ke kota ini. Yang sangat terasa adalah tari kejang atau tari patah-patah (breakdance), yang jadi tren di Amerika pada 1980-an. Setiap sore, atau malam minggu, segerombolan remaja berkumpul di lapangan sepakbola. Mereka melingkar. Pemutar kaset dinyalakan. Dan mulailah mereka menari. Saat itu belum ada MTV, tapi entah bagaimana tarian ini bisa menyebar ke desa-desa. Ketika beberapa kelompok menari, tak jarang terjadi adu ketangkasan dan ujung-ujungnya... berkelahi.
Lalu perlahan muncul beragam acara televisi, video game, dan internet.
Saya mungkin beruntung karena masa kecil saya tak terengut oleh video game, Facebook, atau televisi. Saya juga lebih memilih jaipongan ketimbang tari kejang. Alih-alih bermain bersama teman-teman, anak-anak sekarang memilih berada di depan layar televisi atau komputer; menonton kartun atau sinetron, bermain game atau Facebook. Kalau butuh hiburan, mereka menuju kota tetangga untuk jalan-jalan di mall –karena kota ini miskin mall dan mall bagi mereka adalah lambang kemajuan sebuah kota.
Saya kira kita tak butuh mall. Mall bukan lambang kemakmuran, tapi konsumersime dan kemiskinan kreativitas. Mall mengajarkan kita menjadi konsumen tapi tak mendidik kita menjadi produsen. Kita hanyalah subjek, pasar bagi beragam barang. Kini kita menyaksikan betapa hampir semua barang yang dulu bisa kita hasilkan berasal dari negara lain. Impor, impor, impor. Beras impor, gula, kedelai… apa lagi. Beruntung Brebes masih menjadi penghasil terbesar bawang merah, yang bertahan dari gempuran bawang impor.
Saya bayangkan kota ini memiliki ciri pada landmark kota, museum, dan perpustakaan. Adakah museum di kota ini? Ada banyak bangunan bersejarah tapi kita seringkali memilih Borobudur untuk liburan sekolah atau belajar sejarah. Perpustakaan entah bagaimana kabarnya. Tak ada gedung kesenian yang menampung kreativitas anak-anak muda. Tak ada taman kota, ruang publik bagi beragam aktivitas warga kota. Infrastruktur, terutama jalan, masih belum memadai. Tapi kota ini juga punya banyak potensi dan keunggulan yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan kota. Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Wisata alam, kuliner, dan kerajinan. Keberagaman seni dan budaya.
Apa yang membuat daerah ini terlihat statis dari tahun ke tahun? Saya belum tahu. Mungkin benar jika kita, juga saya, layaknya seekor itik dengan sifat acuh tak acuhnya (cuek bebek) dan berjalan lamban (bagai itik pulang petang). Kita belum mengambil sifat terbaik itik: kebersamaan, kemandirian, dan kerja keras pantang menyerah. Kita juga selayaknya jadi Itik Buruk dalam cerita dongeng, yang cuek dengan cemoohan orang tapi punya hasrat untuk mewujudkan mimpi.
Dirgahayu.*
Lalu perlahan muncul beragam acara televisi, video game, dan internet.
Saya mungkin beruntung karena masa kecil saya tak terengut oleh video game, Facebook, atau televisi. Saya juga lebih memilih jaipongan ketimbang tari kejang. Alih-alih bermain bersama teman-teman, anak-anak sekarang memilih berada di depan layar televisi atau komputer; menonton kartun atau sinetron, bermain game atau Facebook. Kalau butuh hiburan, mereka menuju kota tetangga untuk jalan-jalan di mall –karena kota ini miskin mall dan mall bagi mereka adalah lambang kemajuan sebuah kota.
Saya kira kita tak butuh mall. Mall bukan lambang kemakmuran, tapi konsumersime dan kemiskinan kreativitas. Mall mengajarkan kita menjadi konsumen tapi tak mendidik kita menjadi produsen. Kita hanyalah subjek, pasar bagi beragam barang. Kini kita menyaksikan betapa hampir semua barang yang dulu bisa kita hasilkan berasal dari negara lain. Impor, impor, impor. Beras impor, gula, kedelai… apa lagi. Beruntung Brebes masih menjadi penghasil terbesar bawang merah, yang bertahan dari gempuran bawang impor.
Saya bayangkan kota ini memiliki ciri pada landmark kota, museum, dan perpustakaan. Adakah museum di kota ini? Ada banyak bangunan bersejarah tapi kita seringkali memilih Borobudur untuk liburan sekolah atau belajar sejarah. Perpustakaan entah bagaimana kabarnya. Tak ada gedung kesenian yang menampung kreativitas anak-anak muda. Tak ada taman kota, ruang publik bagi beragam aktivitas warga kota. Infrastruktur, terutama jalan, masih belum memadai. Tapi kota ini juga punya banyak potensi dan keunggulan yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan kota. Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Wisata alam, kuliner, dan kerajinan. Keberagaman seni dan budaya.
Apa yang membuat daerah ini terlihat statis dari tahun ke tahun? Saya belum tahu. Mungkin benar jika kita, juga saya, layaknya seekor itik dengan sifat acuh tak acuhnya (cuek bebek) dan berjalan lamban (bagai itik pulang petang). Kita belum mengambil sifat terbaik itik: kebersamaan, kemandirian, dan kerja keras pantang menyerah. Kita juga selayaknya jadi Itik Buruk dalam cerita dongeng, yang cuek dengan cemoohan orang tapi punya hasrat untuk mewujudkan mimpi.
Dirgahayu.*


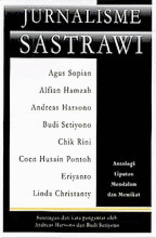


7 comments:
Ide soundtrack!
Iwan Fals punya Berkacalah Jakarta. Kalo mau diadopsi, judulnya jadi Berenanglah Brebesku. Hehehe..
Atau, adopsi Sluku-sluku Bathok aja:
Mak jenthir lo lo lo bah
Brebes mati ora obah
Ayo obah ngalapi berkah
Ayo urip goleko duwit
mbrebes mili.. Hehehe
Bagus sekali tulisanmu, Mas. :)
Ronny,
Sekadar memenuhi janji menulis ulang tahun kota kelahiran di majalah Pemda. Sempat pusing dan akhirnya memutuskan mengorek kenangan masa lalu. Hehehe.
Dirimu tak berhenti menulis kah? Semoga
Mungkin inilah gambaran masyarakat sekarang, banyak yang melupakan budaya sendiri akibat adanya globalisasi. ttp smgt dan cintai budaya kita.ok
mas budi boleh minta kontak yang bisa di hubungi? kami pengen ngundang mas budi ni
Muhammad Burhan,
Silakan kontak email saya: inibuset@yahoo.com. Thanks
Post a Comment