ROSIHAN Anwar tak berubah gayanya. Ia eksentrik, nyleneh, dan terkesan suka menyelepelakan orang lain. Suaranya meledak-ledak, seraya mengangkat kaki di atas kursi, atau bahkan nangkring di atas meja. Yang penting lagi, ia tetap menulis. Karena itu, Rosihan menolak disebut “mantan wartawan”.
“Saya bukan mantan, tetap wartawan. Walaupun tak punya koran, saya merasa diri wartawan. Saya masih menulis di mana-mana.”
Setidaknya Rosihan mendapat jatah menulis kolom di tabloid hiburan Cek & Ricek. Bila tokoh nasional meninggal, pasti ada media yang menurunkan obituari sang tokoh dan penulisnya Rosihan Anwar. Ketika ada “ulang tahun” peristiwa bersejarah, tulisannya pun tak pernah absen.
Ya, Rosihan adalah saksi hidup sekaligus sejarah itu sendiri. Sejarah yang terbuka. Lembar buku sejarah itu terus saja membuka, seperti tertiup angin.
“Wartawan Indonesia sekarang lebih bagus ketimbang dulu,” katanya baru-baru ini, seraya membandingkan tingkat pendidikan wartawan maupun kemapanan media dimana mereka bekerja, yang tak sebanding dengan apa yang dialaminya pada 1940-an hingga 1960-an.
Sesekali suara batuk berat mengusiknya, dan ia segera menutupinya dengan selembar sapu tangan. Buku itu memang sudah lapuk. Ia sedang sakit.
ROSIHAN bersahabatan dengan bulan purnama, karena dibawah sinarnya lah ia dilahirkan. 10 Mei 1922, di Kubang Nan Dua, Sumatera Barat. Oleh Anwar gelar Maharadja Soetan, ayahnya, pegawai pamongpraja Hindia Belanda berpangkat Asisten Demang, ia diberi nama Rozehan Anwar. Kelak, nama itu lebih dikenal dengan Rosihan Anwar.
Selepas sekolah menengah, Meer Uitgebreid Lager Ondrewijs di Padang, Rosihan Anwar melanjutkan ke Algemene Middelbare School Westers Klassieke Afdeling (AMS A-II), jurusan Sastra Klasik Barat di Yogyakarta. Selama tiga tahun menimba ilmu di sana, ada dua nama yang selalu ia ingat; Dr Tjan Tjoe Siem, pemilik indekostnya, dan H.J. van de Berg, guru sejarahnya. Kedua orang itu lah yang mengusik alam pikiran Rosihan, memperkenalkannya pada ajaran sosialisme.
Van de Berg, menurut Rosihan dalam otobiografinya Menulis Dalam Air, adalah guru sejarah yang pandai bercerita secara menawan. Berg suka menyetensil uraiannya, yang kemudian membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Salah satu uraiannya ialah tentang penulis sosialis Jerman, Karl Marx. Rosihan juga acap membaca buku-buku sosialisme milik Meneer Tjan, begitu Dr Tjan Tjoe Siem dipanggil.
Selama menuntut ilmu, Rosihan membaca dan berkenalan dengan sosialisme, tapi belum memahaminya. Hingga suatu ketika, di zaman revolusi, Rosihan mendapatkan sebuah pamflet politik. Sebuah buku kecil, seperti buku saku, tergeletak di meja redaksi Merdeka, dimana Rosihan bekerja sebagai wartawan. Ia ambil, dan membacanya. Pamflet itu berjudul "Perjuangan Kita", ditulis oleh Sutan Sjahrir. Isinya begitu dahsyat. Memancing kemarahan orang-orang politik, terutama yang pernah bekerja sama dengan pemerintahan balatentara Dai Nippon. "Inilah orang yang akan memperjuangkan tegaknya de menselijke waardigheid, martabat kemanusiaan di bumi persada Indonesia," pikirnya.
Setelah melahap habis, ditaruhnya kembali pamflet itu. Ia begitu terpesona. Merasa lebih terbuka melihat peta politik internasional. Kemudian ia membaca buku Sjahrir yang terbit di negeri Belanda, Indonesische Overpeinzingen (Renungan Indonesia).
Rosihan mulai mengenal Sjahrir ketika Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri. Rosihan juga mulai bergaul dengan Soedjatmoko yang bertugas di Kementerian Penerangan. Juga Sudarpo Sastrosatomo yang mengurusi hubungan dengan koresponden-koresponden asing. Dan Subadio Sastrosatomo, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Ketiganya dikenal sebagai Sjahririest atau orang-orang Sjahrir.
Pertengahan 1946, bersama Koko --begitu Soedjatmoko disapa-- yang mewakili majalah Kementerian Penerangan Het Inzicht dan Rinto Alwi dari Ra'jat, Rosihan berangkat ke Makassar untuk meliput Konferensi Malino yang diadakan Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. Van Mook. Mereka diinapkan di Oranje Hotel, dengan lampunya yang redup-redup. Rosihan dan Soedjatmoko ditempatkan dalam satu bungalow. Penyesuaian dan pertukaran gagasan, meski berada di kakus sekalipun. Di atas kali kecil yang airnya mengalir deras, pagi-pagi Rosihan dan Koko nongkrong sebelah-menyebelah. Mengobrol dari soal remeh-temeh, politik, sastra hingga filsafat.
"Saya lihat kamu seperti seorang yang tegak di atas jari-jari kakinya agar tampak besar. Kamu tampak arogan," kata Koko.
"Sama. Saya juga melihat kamu sebagai orang yang angkuh," balas Rosihan.
“Eksistensialisme itu apa, Ko?” tanya Rosihan.
"Eksistensialisme ialah suatu filsafat yang menyatakan kebebasan manusia perorangan," jelas Koko.
"Kalau itu saya akur, Ko," ujar Rosihan sambil membebaskan tubuhnya dari kotoran agar jatuh ke selokan.
Dari toilet sessions ini pula muncul gagasan perlunya menerbitkan sebuah majalah politik dan budaya dalam bahasa Indonesia.
“"Ko, sudah saatnya kita membuat majalah yang bisa digunakan sebagai sarana pendidikan politik masyarakat," ujar Rosihan.
"Iya, kita sudah bosan dengan propanda Belanda melalui sarana-sarana kementerian penerangan," timpal Koko.
Hubungan dengan Koko, Soebadio, Soedarpo, dan Sjahrir membuat Rosihan makin dekat dengan kubu sosialis ini. Sesekali ia datang ke rumah Sjahrir di Jakarta untuk berdikusi mengenai sosialisme. Tapi Rosihan enggan menjadi anggota Partai Sosialisme Indonesia, partai politik yang pada tanggal 12 Pebruari 1948 didirikan oleh Sutan Sjahrir bersama Sjahririest. Rosihan memilih bersikap independen, sebagai wartawan.
DESEMBER 1946, Rosihan disibukkan persiapan pendirian majalah politik dan budaya. Segala kebutuhan dipersiapkan. Bantuan datang dari Kementerian Penerangan berupa sejumlah kertas lembaran dan uang tunai sebesar Rp 3.000. Lumayanlah, cukup untuk menerbitkan empat nomor pertama dengan tiras 3.000 eksemplar, format tabloid, 12 halaman. Diputuskan, nama majalah mingguan tersebut adalah Siasat. Rosihan Anwar ditunjuk sebagai pemimpin redaksi, sedangkan jajaran dewan redaksi diisi oleh Soedjatmoko, Sutomo, Gadis Rasid dan A.B. Lubis, dengan dibantu tenaga tata usaha sebanyak empat orang. Siasat terbit pada 4 Januari 1947.
Dalam waktu tiga bulan tiras majalah ini meningkat 12.000 eksemplar. Meski tergolong peningkatan luar biasa, Siasat lebih menonjolkan sisi idealisme. Rosihan butuh perahu lain untuk ia nahkodai, secara lebih bebas. Kesempatan terbuka ketika pada 1948 ia diberi tahu Soemanang Soerjowinoto bahwa R.H.O Dhuanedi memiliki dana dan ingin menerbitkan koran yang membawa suara "kaum kiblik", pendukung perjuangan RI di Jakarta yang telah diduduki Belanda sejak clash militer ke-1. Syaratnya sederhana. Nama depan koran harus dengan huruf P, sama dengan nama depan Pemandangan.
Rosihan mengusulkan nama Pedoman. Djunaedi tak keberatan. Begitu juga ketika Rosihan memboyong orang-orang Siasat ke Pedoman.
Persiapan untuk Pedoman pun dilakukan. Di sebelah kanan masthead dibuat lingkaran yang ditutupi oleh lima azas, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Indonesia, Kedaulatan Rakyat, Keadilan Sosial dan Kemanusiaan. Pada halam pertama sebelah kanan atas dipasang gambar tiga kolom dari bintang film Sofia Waldy dalam adegan film Di Pinggir Kali Citarum.
Sebuah “koran kiblik” memasang gambar wnita cantik! Nyleneh. Seperti disebutkan dalam tajuk memeringati ulang tahun Pedoman ke-4, alasan pemasangan itu karena, "Sofia waktu itu manis. Pembaca surat kabar di negeri mana juga biasanya suka pada gambar wanita-wanita cantik. ... dan gambar pemimpin-pemimpin republik sudah terlalu keseringan dipasang di surat kabar-surat kabar republik." Djunaedi tak puas dengan gambar itu. Apa lacur, koran sudah mulai dicetak. Nomor perdana harian Pedoman pun terbit pada 29 November 1948.
Pendirian Pedoman menurut editorialnya, “Laki-laki dan perempuan yang mengasuh surat kabar ini akan berdaya-guna terus untuk berpegang pada sifat-sifat sebagai surat kabar umum, memisah-misahkan mana yang facts, mana yang opinion, tidak mewarnai berita, tapi tidak pula berarti tanpa pendapat dan pendirian yang tegas, sebagaimana terbukti dan terbayang dalam kolaman tajuk rencana serta pojoknya.”
“Berpuluh-puluh tahun yang lampau telah dikatakan bahwa tugas dan fungsi surat kabar adalah to comfort the afflicted and to afflict the comfortable atau dalam bahasa kita "menghibur mereka yang sengsara dan mencambuk mereka yang keenakan".
Begitulah. Sebuah koran telah lahir di Indonesia, menambah jumlah koran kaum kiblik yang ikut berjuang untuk kemerdekaan. Sekali ia dibredel oleh Regerings Voorlichtings Dienst atau Jawatan Penerangan Belanda Januari 1949. Pasalnya, Pedoman karena memuat berita pidato radio Menteri Luar Negeri (darurat) Indonesia Mr Maramis dari New Delhi, yang berisi anjuran agar kaum republiken meneruskan perjuangan kemerdekaan dengan tekad yang bulat. Setelah enam bulan lumpuh, Pedoman terbit kembali. Tanpa Djunaedi yang tak begitu antusias meneruskan peranannya sebagai penerbit.
Rosihan pun mengembangkan Pedoman. Tahun 1950 Pedoman menjadi pusat Indonesian Press Service, yang menurut Rosihan dalam Ihwal Jurnalistik, merupakan sindikat pertama dalam persuratkabaran Indonesia di zaman kemerdekaan yang boleh dibilang berhasil. Sindikat itu menyebarkan tulisan-tulisan bertema politik, ekonomi, militer dan sebagainya, secara serentak di lima harian; Pedoman (Jakarta), Pikiran Rakyat (Bandung), Suara Rakyat (Surabaya), Suara Merdeka (Semarang) dan Mimbar Umum (Medan). Suatu cara yang lazim dipakai pers luar negeri untuk mempermudah dan membantu kesulitan mendapatkan tulisan bermutu. Untuk karangan-karangan tertentu Haluan (Padang) dan Pedoman Rakyat (Makassar) memuatnya. Kolomnis-kolomnisnya antara lain Dr Sumitro Sjojohadikusmo, Dr Saroso, Dr Moh Sadeli, Kol A.H. Nasution, Letkol Rakhmat Kartakusumah dan Usmar Ismail.
Pelan tapi pasti, oplah Pedoman melesat. Mulai dari 3.000 eksemplar pada 1949, 5.000 (1950), 13.500 (1951), 15.600 (1952), 22.000 (1953), 27.000 (1954), 38.000 (1955), 48.000 (1956) hingga menjadi 53.000 (1960 dan 1961), dan menjadikan Pedoman sebagai koran beroplah terbesar.
Dari sukses itu, Pedoman melebarkan sayap. Dibuatlah "adik-adik penerbitan" Pedoman yang kemudian oplahnya juga tak kalah besar. Tahun 1961 misalnya, seperti dicatat Daniel Dhakidae dalam The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Economy of Indonesia News Industry, tiras bulanan Pedoman Anak mencapai 45.000, dwimingguan Pedoman Sport 40.000, bulanan Pedoman Wanita 15.000 dan Pedoman Minggu 42.000.
Keberhasilan itu menjadikan Pedoman sebagai raja media. Mengentalkan istilah personal journalism, yang Rosihan sendiri berusaha menghapus stempel itu. Tapi orang kadung menyebut Pedoman adalah Rosihan Anwar, Rosihan Anwar adalah Pedoman. Seperti BM Diah di Merdeka, seperti Mochtar Lubis di Indonesia Raya.
Ketika Pedoman diberi bentuk hukum berupa Perseroan Terbatas (PT), Rosihan mengusulkan agar hak milik atas surat kabar ini dibagi sama rata. Masing-masing wartawan dan karyawan mendapat jumlah saham yang sama. "Sikap demokratis ini mengikuti ajaran sosialis. Saya tidak mau diperlakukan lebih istimewa dari yang lain dalam hal kepemilikan saham perusahaan, sehingga terbentuk sikap kolektif dan koperasi," kilahnya.
Di kantor, Rosihan --yang acap dipanggil Bung Cian dan Haji Waang -- lebih mirip seniman. Ia jarang mengenakan kemeja, apalagi dasi. Sebuah sapu tangan melingkar di di leher. Di kakinya terinjak sepotong sandal jepit.
PADA awal 1955 suasana politik menghangat. Kabinet silih berganti. Pemilihan umum yang sudah dipersiapkan jauh-jauh tahun, akan digelar. Inilah pesta demokrasi kali pertama setelah Indonesia merdeka.
Partai sibuk, koran juga sibuk. Partai politik giat melakukan propaganda melalui media masing-masing. Yang tak punya koran, dekati pemimpin koran umum. Warna koran menjadi pelangi. Ada merah, hijau, putih. Semua koran terhanyut euforia, sehingga soal fairness nyaris terpinggirkan. Pers akhirnya cenderung berpikir dalam kotak-kotak kepartaian.
Dalam tajuk rencana Pedoman "Objektivitas dalam pers", 9 Pebruari 1955, Rosihan menuliskan kegelisahannya. Sekaligus meyakinkan pembaca Pedoman bahwa "Surat kabar ini adalah surat kabar umum yang menghargai terpilihnya ukuran-ukuran objektivitas dalam pers".
Namun siapa yang tak tergoda dengan iklim politik semacam itu?
Rosihan memutuskan masuk politik. Ia mengira bisa bisa menjadi wartawan sekaligus politisi. Bersama Koko, dia menandatangani secarik kertas yang berisi pernyataan "Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini adalah anggota Partai Sosialis Indonesia". Tanpa kop Partai Sosialis Indonesia, tanpa tanda tangan Sjahrir. Setelah menandatanganinya, Rosihan menyerahkannya kepada Soedjatmoko, yang kemudian membawanya. Rosihan menjadi anggota partai untuk memenuhi formalitas dan ketentuan sebagai calon anggota Konstituante. "Konstituante itu kan soal gelanggang menggadu gagasan, mengadu ide, pikiran. Konstitusi nih yang akan kita bicarakan. Saya tertarik. Tak ada obsesi kekuasaan."
Meski sudah menjadi anggota, Rosihan tak pernah mengikuti rapat partai. Kampanye, apa lagi. "Sesudah menandatangani secara formal itu saya nggak pernah ikut anggota partai. Karena saya beranggapan, Kamu toh yang mesti berterima kasih sama saya. Nggak bisa (saya) diinjak-injak oleh disiplin partai. Tanpa mengeluarkan uang satu sen pun dapat koran, koran nomor satu lagi di Indonesia. Tirasnya paling besar; 40.000," kata Rosihan, bangga.
Tak sedikit orang seperti Rosihan dalam PSI. “Orang-orang seperti Rosihan dibutuhkan, dan efektif untuk gerakan sosialis. Karena Rosihan mandiri, bebas, bisa menulis, mengambil sikap menurut kesadaran dia sebagai seorang wartawan yang berbobot. Dia tidak bisa dikendalikan. Paling diajak omong, ia ambil sarinya, jadi berita. Kalau didisiplinkan, efisiensinya jadi hilang,’ ujar salah seorang aktivis Partai Sosialis Indonesia, Murdianto.
Dengan masuknya Rosihan, jajaran redaksi Pedoman yang menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia bertambah. Lainnya adalah A.K. Lubis (pemimpin perusahaan) dan Sanjoto Sastromihardjo (wakil pemimpin redaksi). Sanjoto ikut kampanye di beberapa tempat di Jakarta. Begitu juga A.K. Lubis. Keduanya pengurus Partai Sosialis Indonesia cabang Kebayoran. Masuknya Rosihan menjadi anggota PSI makin memperkuat penyebaran dan perjuangan sosialisme lewat Pedoman. “Dia (Sjahrir –red.) ngerti sendiri, saya juga ngerti sendiri,” ujar Rosihan.
Saat pemilihan umum mendekati hari H, beberapa koran menyiarkan dukungan terhadap partai masing-masing. Pada 26 September 1955, secara mengejutkan keluar dukungan Pedoman terhadap Partai Sosialis Indonesia dalam tajuk rencana "Pilihan Kita: PSI". Disebutkan, dalam senantiasa membela kepentingan umum dan kemajuan rakyat kecil, Pedoman melihat bahwa "partai yang paling positif pendiriannya mengenai bermacam soal yang meliputi tanah air dewasa ini dan juga jelas memberikan gambaran mengenai perspektif masa depan dan cara-cara mewujudkannya adalah PSI".
Kebijakan pemberian dukungan terhadap Partai Sosialis Indonesia adalah inisiatif Rosihan, tanpa dibicarakan di kalangan redaksi. Menurutnya, dalam opini, mendekati hari pemilihan umum harus tegas dinyatakan.
Rosihan menjadi anggota partai begitu saja. Tak ada dilema. Dan toh ia beranggapan bahwa Pedoman tetap koran umum, bukan koran partai. Bagi wartawan Pedoman non-Partai Sosialis Indonesia seperti Amir Daud pun tak terkejut dengan pemunculan tajuk itu. “Tidak jadi problem. Karena semua tahu bahwa ini bukan koran partai, kalau simpatisan PSI memang benar. Dan lagi hampir semua (wartawan Pedoman) itu pecinta PSI, walaupun bukan orang partai,” kata Daud.
Ada 60 tanda gambar peserta pemilu yang mesti mereka pilih. Baik partai politik, organisasi profesi maupun perorangan. Tak seperti dikhawatirkan banyak orang, pemilihan berlangsung aman dan tertib. Tak ada kegaduhan atau huru hara di Jakarta Raya. Hasil pemungutan suara cukup mengejutkan; PSI kalah telak. Ia hanya memeroleh lima kursi di parlemen. Kursi terbanyak diperoleh Partai Nasional Indonesia dan Msayumi (57 kursi), Nadhlatul Ulama (45) dan Partai Komunis Indonesia (39).
Rosihan kecewa. Ia kemudian menganalisa sebab kekalahan itu. Antara lain dalam bentuk kritik untuk Partai Sosialis Indonesia seperti pemuatan tajuk rencana Nieuwsgier yang berjudul "Tekort ener elite" (kekurangan suatu elit), 6 Oktober dan komentar majalah Belanda Groene Amsterdammer yang menyatakan bahwa PSI memperlihatkan lakon yang sedih, een leger van bekwage officieren, zonder soldaten (suatu tentara dari perwira-perwira cakap, tanpa prajurit-prajurit).
Orang masih sibuk menanti pengesahan hasil pemilu. Koran masih memuat kecurangan-kecurangan pemilu, perbedaan suara, dan sebagainya. Tak terasa usia Pedoman bertambah. Direktur Lembaga Pers dan Pendapat Umum Marbangun yang diminta untuk memberi sambutan "Pedoman sedang menjadi journal d'information?" menulis ambivalensi Pedoman sebagai alat pendukung sosialisme (Partai Sosialisme Indonesia) dengan sebagai sebuah perusahaan dagang. Marbangun menganggap Pedoman sudah menjadi alat propaganda partai sebagai “party bound” atau surat kabar partai pada hari-hari menjelang pemilu. “ Hal tersebut sudah tentu sama artinya dengan "kleur bekennen". Kami agak sangsi, apakah pada pemilu yad ini Pedoman kembali akan mengorbankan kemerdekaan jurnalistiknya... Ini menurut pendapat kami bagi Pedoman merupakan suatu dilema.”
Sambutan Marbangun berbalas. Dalam tajuk rencana "Pedoman 7 Tahun" pada edisi itu juga Rosihan membantah dan menjawab keraguan Marbangun. Bagi dia, untuk menjadi “koran partai”, koran itu harus tunduk sepenuhnya kepada politik partainya, mendapat keuangan dari partai, dan sebagainya. Pedoman tidak demikian. “Pedoman dapat mengatakan kepada Saudara Marbangun: Tiga hari sebelum hari pemungutan suara untuk DPR kita menulis tajuk rencana yang berkepala: "Pilihan Kita: PSI". Maka untuk pemungutan suara guna Konstituante nanti pendirian itu masih tetap berlaku, dan kita tegaskan lagi: "Pilihan Kita: PSI".
Penegasan sikap itu disertai pemasangan tanda gambar Partai Sosialis Indonesia di sudut atas halaman muka, terkadang diimbuhi tulisan "Dalam pemilihan Konstituante, Saudara tusuklah tanda gambar ini (bintang, lambang Partai Sosialis Indonesia)” seperti dimuat 29 Nopember. Kemudian Pedoman menegaskan kembali sikapnya dalam tajuk "Konstituante: Pilihan Kita PSI", 12 Desember, yang disebutkan bahwa itu menuruti suatu kebiasaan jurnalistik yang baik. Mengapa Pedoman memilih partai yang kalah dalam pemilihan umum? "... di dalam konstelasi kepartaian sehabis pemilu nanti maka justru partai-partai kecil dapat memainkan pernan yang tidak kurang pentingnya. Partai-partai besar didalam merumuskan suatu program seringkali terlalu harus mengingat kepada "sayap" yang harus disatukan didalam barisannya. penyakit yang demikian tidak ada pada suatu partai kecil seperti PSI."
Pilihan sikap Pedoman itu menjadi bahan ejekan koran lain, suatu hal yang biasa di zaman pers partisan. Suluh Indonesia menganggap Pedoman “wis entek entute”. Alasannya Pedoman adalah bulat-bulat koran Partai Sosialis Indonesia. Karena Partai Sosialis Indonesia gagal besar dalam pemilihan umum, begitu juga Pedoman. Tajuk rencana Pedoman, 14 Desember, menjawabnya dengan tulisan, “menghadapi pemilihan Konstituante, kami tegaskan Pedoman durung entek entute dan begitu pula halnya PSI. (Yakin)”.
Keyakinan yang tak berbuah. Dalam pemilihan Konstituante Partai Sosialis Indonesia hanya memeroleh 10 wakil di Konstituante. Rosihan gagal menjadi anggota Konstituante, sedangkan Soedjatmoko lolos.
SESUDAH pemilihan umum, suasana politik tetap hangat. Pemimpin sipil dan militer di daerah melakukan “pembangkangan” terhadap pemerintah pusat. Beberapa daerah bergejolak, menuntut pembelakuan otonomi daerah. Kebijakan ekonomi pemerintah yang kurang menguntungkan pribumi, dipertanyakan. Pernyataan-pernyataan anti-Cina meluap. Korupsi merajalela.
Sebuah peristiwa yang menjadi makanan empuk pers adalah Peristiwa 13 Agustus 1956. Peristiwa yang terjadi di Percetakan Negara itu melibatkan beberapa pejabat tinggi pemerintah, seperti Piet de Queljre dan Lie Hok Thay, direktur jenderal dan wakil direktur jenderal, serta Sjamsudin St. Makmur, bekas menteri penerangan.
Menteri Penerangan Sudibyo yang sebelumnya sudah diberitahu secara resmi keadaan Percetakan Negara menyatakan tak bisa mengatasi dengan alasan politis. Para pemuda yang tak senang melihat keadaan itu, menculik Lie Hok Thay, dan kemudian menyerahkannya ke kejaksaan agung. Hasil pemeriksaannya cukup menggemparkan; Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani terlibat.
Panglima TT II dari divisi Siliwangi yang sedang melancarkan pemberantasan korupsi, mengeluarkan perintah penahanan Abdulgani. Abdulgani ditangkap CPM, tapi dilepaskan kembali setelah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Kepala Staf Angkatan Darat A.H. Nasution campur tangan. Dalam Memenuhi Panggilan Tugas Jilid IV, Nasution menulis, waktu akan ditangkap Abdulgani dan istrinya menelpon Perdana Menteri Ali, yang segera menghubungi Nasution. Ali mengatakan, “Bagaimanapun juga KSAD harus bertindak, tak bisa seorang menteri ditangkap begitu saja".
Kasus tersebut dilansir secara besar-besaran oleh pers, terutama oleh Pedoman dan Indonesia Raya. Terlebih pemerintah tampaknya tak punya kemauan politik untuk mengusut kasus tersebut. Untuk meredam pemberitaan pers tersebut Mayor Jenderal Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat pada 14 September 1956 tentang larangan untuk mengecam atau menghina pembesar-pembesar pemerintah. Tapi nyamuk pers makin berdengung.
Terhadap peraturan tersebut, Pedoman memuat karikatur "Heil Ali! Heil Nasution!" yang merupakan ucapan Bung Tomo atau Sutomo ketika mengajukan pertanyaan kepada pemerintah selaku anggota DPR dari fraksi Partai Rakyat Indonesia. Sutomo, seperti dimuat Pedoman 19 September, menanyakan kenapa Menteri Penerangan Sudibjo menjawab agar ditanyakan kepada Kepala Penerangan AD ketika ditanya apakah Kitab Undang-undang Hukum Pidana tak cukup lagi oleh pemerintah untuk menghadapi pers. “ Dengan mengerahkan kekuasaan militer dalam persoalan yang tidak bersifat militer pemerintah malahan menunjukkan bahwa zonder kekuatan militer pemimpin-pemimpin Indonesia (dalam hal ini menteri-menteri sebagai politikus) tidak dapat mengatasi keadaan yang sampai detik ini hanya bersifat politik saja.”
Peraturan pers itu juga dipertanyakan beberapa anggota parlemen. Anggota parlemen Siauw Giok Tjhan seperti dikutip Pedoman (19/1) menamakan peraturan itu sebagai “mau menyembelih ayam dengan meriam”.
Empat hari kemudian Rosihan Anwar diperiksa dan didengar keterangannya oleh Corps Polisi Militer di Jalan Guntur. Interogasi juga dilakukan terhadap Mochtar Lubis (Indonesia Raya) dan Naibaho (Harian Rakyat) oleh Corps Polisi Militer detaseme Jakarta Raya atas perintah Komandan Komando Militer Kota Besar Djakarta Raya Mayor Djuhro selaku pemegang kekuasaan Staat van Orloog (SO) atau keadaan bahaya perang.
Rosihan datang di markas Corps Polisi Militer. Pemeriksaan berlangsung dari pukul 09.00-13.00 dan 17.00-22.00 sekitar Peristiwa 13 Agustus, Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat dan karikatur-karikatur yang dimuat oleh Pedoman. Tentang berita sekitar Peristiwa 13 Agustus, Rosihan menyatakan ia yang bertanggung jawab atas segala pemberitaan yang dimuat dalam Pedoman. Rosihan juga menjelaskan berita-berita sekitar penangkapan yang hendak dijalankan kepada Roeslan Abdulgani, agar pihak Corps Polisi Militer memahami bagaimana jadinya berita itu sampai dimuat dalam Pedoman dengan tidak menyebut sumber berita atau informannya, sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Pertanyaan mengenai Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat oleh Rosihan Anwar dijawab bahwa itu membatasi kemerdekaan pers dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Sementara pasal 19. Sedangkan karikatur "Heil Ali! Heil Nasution!" merupakan persetujuan Rosihan terhadap anggota parlemen Sutomo yang mengajukan pertanyaan kepada pemerintah.
Usai pemeriksaan, Rosihan diperintahkan untuk menghadap Letnan Kolonel Chandra Hasan, Kepala Bagian Inteligence Staf Umum Angkatan Darat pada 20 September. Begitu juga Mochtar Lubis. Namun keduanya sudah kadung punya rencana, menghadiri seminar International Press Institute di Zurich. Karena perintah lisan, sehingga tak punya dasar hukum, dan perintah tertulis tak juga datang, mereka memutuskan berangkat ke Zurich. Apalagi tiket dan sebagainya sudah siap. 20 September 1956, Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis berangkat ke Zurich bersama pemimpin redaksi yang lain: BM. Diah (Merdeka), Supardi (Suluh Indonesia), S. Tasrif (Abadi), Wonohito (Kedaulatan Rakyat), dan Adam Malik (Antara). Di lapangan terbang Kemayoran mereka tak menemui halangan dari pihak militer sekalipun.
Dalam penerbangan di atas pesawat terbang KLM, berjam-jam di atas laut, menyeberangi Samudera Hindia, terbersit gagasan untuk membuat suatu kesepakatan. “Kami 7 wartawan Indonesia, dalam melewati garis khatulistiwa bersama ini dengan tekad yang bulat menentang bersama-sama setiap percobaan dari pihak manapun untuk mengekang kemerdekaan pers Indonesia, karena kemerdekaan pers itu adalah satu hak asasi manusia merdeka yang telah ditebus dengan darah dan jiwa patriot Indonesia.”
Dari Zurich, Rosihan dan Lubis tak langsung pulang. Ditemani Adam Malik dan Tasrif, mereka melakukan beberapa kunjungan santai ke beberapa negera, antara lain Belanda dan Italia, sambil menunggu keadaan politik mereda.
Keempat wartawan itu kembali ke tanah air dan tiba di Kemayoran pada 19 Oktober 1956, dengan kesiapan mental akan disambut oleh petugas-petugas militer untuk langsung dibawa ke penjara. Tak terjadi. Hanya seorang petugas kejaksaan agung yang datang memberitahu bahwa mereka boleh pulang ke rumah. Selebihnya wartawan dalam negeri dan koresponden asing yang mengerubuti mereka. Rosihan Dan Mochtar Lubis kepada pers di lapangan terbang Kemayoran mengatakan, “Kami akan berjuang mempertahankan kemerdekaan pers dan selama Peraturan KSAD No. 001/9/PKM/1956 itu masih berlaku di Indonesia, maka kami sebagai wartawan akan tetap menentangnya.”
Selanjutnya, dalam statemen, ditegaskan sikap mereka yang akan memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan pers apapun akibatnya, serta penolakan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat. Statemen itu juga berisi klarifikasi kepergian mereka ke luar negeri. Bahwa kepergian mereka telah diketahui sepenuhnya oleh kejaksaan agung.
Keesokan harinya, Rosihan mendapat panggilan agar datang di kantor Corps Polisi Militer di Jalan Merdeka Timur untuk melanjutkan pemeriksaan yang belum selesai. Rosihan datang, dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Selesai. Namun genderang perang sudah ditabuh. Surat kabar Rosihan dan ketiga wartawan lainnya memuat laporan "pedas" tentang tindak-tanduk rombongan Presiden Soekarno sewaktu berada di luar negeri. "Laporan 4 wartawan kepada seluruh rakyat (tentang kelakuan anggota rombongan Presiden Soekarno)", yang berfoya-foya dan bermewah-mewahan bersama perempuan-perempuan cantik dan kendaraan-kendaraan mewah, dimuat Pedoman pada 22 dan 23 Oktober 1956.
Kecuali untuk Mochtar Lubis, kasus sekitar Peristiwa 13 Agustus yang menimpa Rosihan Anwar tak dilanjutkan. Mochtar Lubis harus menghadapi kenyataan pahit; sekitar sembilan tahun mengalami tahanan kota dan tahanan rumah.
Peristiwa 13 Agustus membuat Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengajukan permohonan berhenti pada bulan Maret 1957, bertepatan dengan diumumkannya keadaan perang dan darurat perang. Kebebasan pers resmi ada dalam bahaya paling serius sejak kemerdekaan Indonesia.
DI Sumatera dan Sulawesi gejolak ketidakpuasan terhadap Jakarta belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Bahkan makin memanas. Dinas rahasia Amerika Serikat, Central Intelligence Agency, dikerahkan oleh Washington untuk membantu pasukan di Sumatera dan Sulawesi. Mereka membantu persedian senjata, uang, latihan militer bahkan pilot bayaran untuk menerbangkan pesawat terbang menyerbu kedudukan strategis tentara Indonesia di Sulawesi dan Maluku.
Bantuan Amerika membesarkan hati para perwira pemberontak maupun rekan politisi sipil mereka, antara lain ekonom Soemitro Djojohadikusumo, untuk mengumumkan pengambilalihan kekuasaan di daerah.
Pemerintah Jakarta memberlakukan keadaan perang dan darurat perang di seluruh negeri. Ini menempatkan posisi militer pada posisi yang vital. Tapi darurat perang ini menempatkan pers dalam posisi tak menguntungkan. Tiap komando militer bisa seenaknya memberlakukan peraturan pers di daerah masing-masing.
Bulan Maret 1957, Penguasa Militer Djakarta Raya Letkol. Dachja mengeluarkan peraturan tentang larangan penyiaran berita-berita militer yang tak bersumber resmi dari penerangan angkatan darat atau komando militer Jakarta. Wartawan bekerja dalam suasana yang sangat sulit.
Peraturan itu mulai memangsa korban. Pukul 14.00, 20 April, atas perintah Penguasa Militer Djakarta Raya, surat kabar Pedoman dan Bintang Timur dibredel selama 3 hari dari 23 April sampai 25 April 1957. Tapi menurut keterangan resmi Komando Militer Kota Besar diketahui bahwa pembredelan Pedoman disebabkan karena pemuatan berita: “Dua utusan Dewan Banteng ditahan di Jakarta” tanggal 16 April 1957.
Isi berita tersebut, yang dimuat di halaman dua, adalah: “Lts. Nasution dan Lts. Sinaga keduanya utusan dari Padang untuk menyampaikan surat Ketua Dewan Banteng Letkol. Achmad Hussein kepada KSAD Nasution, telah ditahan oleh CPM pada hari Minggu. Menurut keterangan yang diperoleh setibanya di Jakarta kedua orang utusan itu telah lebih dulu melaporkan diri kepada KMKBDR. Alasan penahanan masih belum diketahui.”
Pedoman belum diperbolehkan terbit ketika pada tanggal 25 April 1957 Rosihan Anwar diundang Corps Polisi Militer untuk diperiksa karena pemuatan berita bertajuk "Informan2 KMKB yang Partikelir Menipu, Memeras, dan Pura2 Menolong" pada tanggal 18 Pebruari. Berita tersebut sebenarnya diambil dari berita bulletin Antara tanggal 16 Pebruari berkepala "Pembantu2 KMKB yang terdiri dari Orang2 Partikelir dihapus". Karena itu, redaksi Antara juga diperiksa.
Rosihan menjelaskan, pengolahan berita dari setiap kantor berita menggunakan dasar bahwa setiap surat kabar mempunyai pribadinya sendiri. Ia berhak memilih berita atau bagian berita mana yang ia perlukan. Kepala berita Pedoman juga tidak dimaksudkan untuk menghina korps informan Komando Militer Kota yang sah.
Pembredelan besar-besaran dilakukan Penguasa Militer Djakarta Raya untuk meredam pemberitaan pers saat berlangsung Musyawarah Nasional yang mempertemukan wakil-wakil tertinggi di kalangan militer dan sipil dari semua daerah, termasuk daerah-daerah yang memberontak. Dua hari sebelumnya, Penguasa Militer Djakarta Raya mengeluarkan seruan agar pers mau membatasi diri berdasarkan pengumuman penguasa militer Djakarta Raya tertanggal 3 September mengenai pemberitaan di sekitar Munas.
Pembredelan pertama menimpa Bintang Timur, Harian Rakyat dan Kantor Berita Antara. Redaksi Pedoman menerima press release dari Komado Militer Kota Besar Djakarta Raya mengenai pembredelan tersebut, dan bisa memahami karena ketiga media itu telah menyiarkan pembicaraan Presiden Soekarno dengan Wakil Presiden Hatta yang dihadiri Perdana Menteri Djuanda beserta 3 wakilnya dan Kepala Staf Angkatan Darat. Peringatan staf kehakiman Komando Militer Kota Besar Djakarta Raya agar jangan mengeruhkan suasana juga diikuti secara sungguh-sungguh.
Anehnya, tetap saja Pedoman kemudian kena bredel. Tentu saja itu menimbulkan tanda tanya besar: "Apa yang terjadi di Jumat malam", saat pengumuman pembredelan kedua dikenakan terhadap 10 organ pers lainnya, “kita tidak tahu”. (”Pembreidelan pers di ibukota”, tajuk rencana Pedoman, 16/9). Redaksi Indonesia Raya saja, seperti ditulis Mochtar Lubis dalam Catatan Subversif-nya menerima larangan melalui telepon, hingga percetakan koran hari Sabtu terpaksa dihentikan.
Penguasa militer di Jakarta tak mau menanggung risiko menghadapi surat kabar-surat kabar yang biasanya bersuara blak-blakan. Praktis, 10 harian dan 3 kantor berita kena bredel selama Munas. Keesokan harinya, pukul 20.00, juru bicara Penerangan Angkatan Darat Pusat Pringgadi mengumumkan pada para wartawan yang hadir mengikuti Musyawarah Nasional, pembredelan 10 harian dan 3 kantor berita telah dicabut. “Ini sesuatu lelucon yang sama sekali tidak lucu,” tulis Mochtar Lubis.
SELASA, 24 September 1957, Pengadilan Negeri Istimewa tampak lengang. Padahal hari itu ada tiga orang wartawan yang akan disidang. Mungkin bukan hal menarik. Di pengadilan ini menumpuk ratusan perkara pers. Tiga wartawan itu adalah Tahsin, penanggung jawab Harian Bintang Timur, Junus Lubis, penanggung jawab harian Pemuda, serta penangung jawab Harian Pedoman, Rosihan Anwar.
Tahsin dituduh melanggar peraturan militer no 6, yakni menyiarkan berita yang tak berasal dari instansi yang berhak. Antara lain ”Apa itu Batalion Sumatera?”, “Negara Sumatera diproklamirkan 17/4” dan “Tentara partikelir ke arah pemberontakan?”. Rosihan juga terkena pelanggaran yang sama, karena memuat tulisan “Dua utusan Dewan Banteng ditahan di Jakarta”. Serdangkan Junus Lubis dituduh melanggar peraturan mengenai batas waktu pemilu untuk DPRD, yakni dengan mengutip berita dari Harian Rakyat.
Tepat pukul 09.00 sidang digelar. Di dalam ruangan hanya terdapat lebih kurang selusin orang, terdiri dari jaksa dan panitera, dua orang Corps Polisi Militer, tiga orang terdakwa dan satu-dua wartawan. Rosihan duduk di kursi pesakitan. Sidang dimulai dengan tanya jawab antara hakim dan terdakwa. Hakim menanyakan bagaimana cara kerja di redaksi, kemudian ditutup dengan sebuah pertanyaan:
‘’Menurut saudara, apakah berita mengenai ‘Dua Utusan Dewan Banteng ditahan di Jakarta’ itu termasuk bidang militer,’’ tanya hakim.
‘’Menurut interpretasi saya, tidak,’’ tegas Rosihan.
Tanya jawab usai. Hakim mempersilahkan Jaksa untuk membacakan tuntutannya. Jaksa Mr. Anas Jakoeb mengajukan tuntutan agar terdakwa dihukum satu bulan penjara atau denda Rp 300. Hal yang meringankan terdakwa adalah surat kabar terdakwa pernah dibredel oleh penguasa militer Jakarta Raya lantaran berita tersebut.
Tiba giliran Rosihan Anwar membacakan pledoi. Kertas dibuka, kemudian ia mulai membacanya. ‘’Apa yang dimaksud dengan bidang militer (dalam soal pemberitaan) tidaklah selalu jelas bagi para wartawan, justru karena tidak diberikan batas-batas yang tegas dalam interpretasinya.”
“Sebagai ilustrasi, misalnya Kantor Berita PIA dibredel tanggal 16 sampai dengan 23 April 1957, dituduh melanggar Pengumuman No. 6, menyiarkan berita: “Keterangan Kolonel Simbolon tentang Ikrar Bersama 48 Perwira TT-I”. Begitu pula tanggal 23 sampai dengan 26 April 1957, surat kabar Pedoman dan Indonesia Raya dibredel, masing-masing karena menyiarkan berita: “Dua Utusan Dewan Banteng ditahan di Jakarta” dan interview dengan Ketua Dewan Banteng Letkol. Achmad Hussein.”
“Aneh bin ajaib, mengherankan sekali pada waktu itu, bahwa oleh penguasa militer Jakarta Raya tidak pula diambil tindakan pembreidelan terhadap Kantor Berita Antara dan Harian Rakyat. Antara menyiarkan berita dengan dateline 16 April dari Denpasar mengenai latar belakang peristiwa militer di Kupang. Sedangkan Harian Rakyat: "Memorandum KSAD kepada Panglima TT-II".
“Kesimpulan yang dapat kita tarik dari ilustrasi di atas ini ialah bahwa dalam beleidnya menghanteer pengumuman No. 6 itu, KMKBDR bersikap diskriminatif, bersikap pilih kasih, membeda-bedakan antara "surat kabar pihak sini" dengan "surat kabar pihak sana". “
Ketika Rosihan Anwar akan melanjutkan pledoinya tentang soal tersebut, hakim mengetok dan menyatakan bahwa soal beleid KMKBDR itu tidak perlu disinggung lagi. Rosihan Anwar lalu melanjutkan saja. “Bahwa para wartawan tidak dapat mendapat sesuatu pegangan dan patokan yang jelas, apa yang mesti dianggap berita-berita di bidang militer, yang boleh atau tidak boleh disiarkan.”
“Saudara Hakim niscayalah dapat merasakan sendiri dan membayangkan apa akibatnya ini bagi para wartawan pencinta demokrasi, yang karenanya merasa tertekan jiwanya tidak ubahnya seperti keadaan yang berlaku di zaman pendudukan Jepang.”
Terdakwa memperingatkan akan perkataan IPI bahwa kemerdekaan pers boleh dikata telah dihapuskan di Indonesia. Dan juga kata-kata Serikat Penerbit Suratkabar setelah berkoferensi di Tawangmangu, 9-11 Mei. “Tindakan-tindakan yang banyak sedikitnya mengurangi kemerdekaan pers dan menyempitkan ruangan bergerak wartawan adalah tidak menguntungkan pemerintah dan merugikan nama baik negara di pandangan dunia internasional.’’
Kemudian Rosihan menambahkan: ‘’Saya kemukakan pula seterusnya perkembangan kronologis, bagaimana tanggal 25 Mei Pemimpin Redaksi Keng Po Injo Beng Goat dan pemimpin redaksi Marinjo Dick Joseph ditahan oleh KMKBDR, tanggal 25 Juni S. Brata dari “Brata News”, semuanya korban dari pengumuman no. 6 itu. Tetapi terhadap Antara yang pada tanggal 7 Mei menyiarkan “Pimpinan AD kirim delegasi untuk jumpai Soekarno-Hatta” cuma diambil tindakan mendengar keterangan wartawan yang bersangkutan.”
“Kesimpulan saya adalah: 1) betapa pengumuman no. 6 penguasa militer Djakarta Raya sangat "rekbaar" interpretasinya, tidak memberikan sesuatu pegangan kepada para wartawan; 2) betapa beleid praktis menghanteer pengumuman No. 6 itu telah membingungkan para wartawan; 3) betapa pengumuman No. 6 itu dirasakan sebagai membatasi kemerdekaan pers. Oleh karena itu, Saya tetap merasa diri tidak bersalah.’’
Rosihan Anwar kembali duduk. Kemudian hakim mempersilahkan pembela terdakwa, Mr. Lukman Wirjadinata, membacakan pledoinya.
“Terdakwa dituduh melanggar Peraturan Penguasa Militer Djakarta Raya No. 6 tertanggal 13 Maret 1957, yang berbunyi sebagai berikut: Dilarang mengadakan pemberitaan-pemberitaan mengenai keadaan di sekitar dan menyangkut-paut angkatan perang secara langsung atau tidak langsung yang sumbernya tidak berasal dari instansi-instansi yang berhak, dalam hal ini melalui perwira pers untuk daerah KMKBDR dan/atau Penad.”
“Considerans daripada Peraturan Penguasa Militer tersebut menjatakan, bahwa pada dewasa ini masih terdapat pemberitaan-pemberitaan, terutama pemberitaan-pemberitaan mengenai keadaan sekitar dan menyangkut angkatan perang, oleh sementara surat-surat kabar di daerah Djakarta Raya, yang isi dan sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga akan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.”
“Perlu kiranya dikemukakan, bahwa baik dari isi peraturan tersebut, maupun daripada consideransnya ternyata dengan jelas bahwa yang dilarang itu adalah pemberitaan mengenai “keadaan” sekitar dan menyangkut angkatan perang.”
“Selain daripada itu perlu diperhatikan pula, bahwa dari bunyi considerans peraturan itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemberitaan yang dilarang itu harus demikian rupa, sehingga akan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.”
“Saudara ketua, pemberitaan yang menjadi pokok perkara ini, yaitu yang berbunyi “Dua Utusan Dewan Banteng ditahan di Jakarta” memang menyangkut angkatan perang, akan tetapi menurut pendapat saya bukanlah mengenai “keadaan” angkatan perang.”
“Dari pemeriksaan di persidangan dapat dipastikan pula, bahwa berita yang menyangkut pokok perkara itu tidak berasal dari KMKBDR atau Penad, akan tetapi menurut hemat saya tidak terbukti sama sekali, bahwa berita itu dapat menimbulkan gangguan kemananan dan ketertiban umum.”
“Saudara ketua, untuk mendapatkan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai Penguasa Militer Jakarta Raya itu, maka bergubung dengan tidak adanya penjelasan, izinkanlah saya mengadakan perbandingan dengan “verordiningen van het Militair Gezag” di zaman Belanda.”
“Dalam hal ini saya ingin menunjuk kepada Verordening No. 14/Dv.0/7A-3 van het Militair Gezag (Javasche Courant 17-5-1940 No. 40 a) jo Verordening No. 66/Dv.0/VII A-3 (Javasche Courant 26-3-1941 No. 24 a).”
Pembela kemudian menjelaskan panjang lebar peraturan-peraturan tersebut dalam bahasa Belanda.
“Dari bunyi “verordening van het militair gezag” tersebut di atas ternyata dengan jelas, bahwa yang dilarang itu bukanlah tiap-tiap berita mengenai angkatan perang, melainkan berita-berita mengenai angkatan perang, yang:
a) Berbahaya untuk kemananan dan ketertiban umum.
b) Menyangkut keadaan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pertahanan negara, dan kepentingan-kepentingan militair lainnya, yang belum pernah diumumkan.”
“Saudara ketua, dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemberitaan, yang menjadi pokok perkara ini, tidak merupakan pelanggaran peraturan Penguasa Militer Djakarta raya No. 6, tertanggal 13 Maret 1957.”
“Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas saya mohon, supaya Pengadilan Negeri di Jakarta memutuskan untuk membebaskan terdakwa, setidak-tidaknya untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan.”
Setelah terdakwa dan pembelanya membacakan pledoinya, hakim memutuskan untuk mengundurkan perkara itu hingga tanggal 1 Oktober.
Perkara Tahsin juga diundur sampai 1 Oktober atas permintaan pembela Mr Tjian Djoe Kiam. Sedangkan Junus Lubis dibebaskan setelah disidangkan pagi itu.
Seperti diputuskan hakim A Razak Sutan Malelo pada sidang sebelumnya, sidang perkara Rosihan Anwar kembali digelar, 1 Oktober, pukul 09.00. Suasana sidang tidak berubah. Hanya ini kali terdakwa tinggal dua orang, Rosihan Anwar dan Tahsin.
Dalam sidang itu pengadilan memutuskan pembebasan Rosihan Anwar karena segala tuduhan tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah melanggar Peraturan No. 6 Penguasa Militer Djakarta Raya, dan negara akan memikul segala ongkos pemeriksaan perkara. Hakim Abdul Razak Sutan Malelo dalam pertimbangannya mengatakan: “Bahwa tidak nampak alasan yang sah yang menjadi landasan untuk larangan tersebut di dalam pasal I dan bukanlah dikandung maksud oleh pembentuk undang-undang tersebut untuk dijadikan larangan segala pemberitaan-pemberitaan, sekalipun yang mengenai unsur-unsurnya, karena tiap-tiap larangan itu (verbodsbepaling) ada rationya.
“Akan tetapi, ratio dari verbodsbepaling tersebut dapat dicari dalam considerans dari peraturan itu, yaitu “isi” dan “sumber”-nya itu dapat menimbulkan gangguan kemananan dan ketertiban umum.”
Pengadilan berpendapat bahwa larangan sebagaimana dalam pasal I tersebut baru dapat diancam dengan hukum (strafbaar/strafwaarding) sekira pemberitaan tersebut dapat mengakibatkan “gangguan keamananan dan ketertiban umum”.
Rosihan Anwar terbesa dari hukuman. Menanggapi pembebasan Rosihan Anwar, tajuk rencana Pedoman “Peraturan No 6 pers Jakarta”, 2 Oktober, melukiskannya sebagai suatu kemenangan moril yang besar bagi segenap korps wartawan Jakarta. Pedoman juga menyerukan agar korban di kalangan pers Jakarta, berupa pembredelan surat kabar, penahanan dan pemanggilan terhadap wartawan, untuk diperiksa.
Kemenangan yang tak berumur panjang. Pedoman kena bredel lagi dengan alasan “keamanan” karena memuat surat Jaksa Agung yang diberhentikan oleh pemerintah. Kemudian 22 Maret 1958, Pedoman dibredel atas perintah Penguasa Perang Djakarta Raya dengan alasan "demi hukum dan ketertiban” karena pemberitaan tentang kaum pemberontak yang membentuk Pemerintahan Republik Rakyat Indonesia di Padang. Pedoman baru diperbolehkan terbit kembali 2 April.
MARET 1959. Ketika Presiden Soekarno membubarkan parlemen, Panglima Militer Jakarta memperingatkan pers agar tidak melakukan penyajian redaksional yang keliru. Langkah preventif tersebut membuat pers dalam posisi tak menentu. Sebagai tindak lanjut pembubaran parlemen, Presiden Soekarno menyatakan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, muncul program manipolisasi pers yang diberi bentuk dengan dikeluarkannya izin terbit. Dengan Peraturan Peperti No. 10/1960, para peminta izin terbit harus menyetujui dan menandatangani pernyataan 19 pasal untuk mendukung Manipol-USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia). Pers yang tak mematuhi ketentuan harus berhenti terbit.
Beberapa penerbit menandatanganinya, beberapa tidak atau memilih berhenti terbit. Rosihan Anwar bersedia menandatangani “19 persyaratan” agar nafas hidup Pedoman tetap ada. Pilihan sikap, yang bagi wartawan Pedoman Amir Daud, berarti mempertaruhkan citra Rosihan. “Kita hendak menyelamatkan koran agar terbit terus. Saya pikir nggak ada kewajiban ini-itu. Nggak ada! Hanya mempertahankan koran. Kan dibilang, ‘daripada nggak terima kita tutup’. Nah bagaimana? Kita mau gagah-gagahan? Nggak bisa dong. Kita koran yang paling besar waktu itu. Orang banyak mesti melihat. Jadi kita coba ajukan. Kalau mau begitu permainannya, playing the game, kita ikuti. Kalau saya tanda tangani itu taktik; mau menyelamatkan Pedoman. Itu saja. Suatu yang biasa dilakukan koran,” ujar Rosihan.
Suardi Tasrif tak bersedia, dan memilih untuk menghentikan penerbitan Abadi tanggal Oktober 1960. Sedangkan Mochtar Lubis sudah tak lagi memimpin Indonesia Raya ketika pemerintah mengumumkan “19 persyaratan”. Harian yang ia pimpin tak diberi izin terbit pada akhir 1958. Ia sendiri masih mendekam dalam tahanan rumah.
Dari “penjara rumahnya”, Mochtar Lubis dengan keras mengecam ketentuan itu dan mengkritik Rosihan Anwar yang ikut menandatangani "19 persyaratan" sebagai "taktik" demi kelangsungan hidup korannya. Lubis, yang menjadi Ketua Komite dari Internasional Press Institute mengirimkan surat kepada International Press Institute menyalahkan pilihan sikap Rosihan. Ia juga mengusulkan agar Rosihan Anwar diberhentikan karena telah menandatangani “19 persyaratan” yang berarti melanggar prinsip International Press Institute mengenai kemerdekaan pers. Lubis dalam penjelasannya pada International Press Institute, dapat mengerti keadaan yang harus dihadapi Rosihan Anwar sebelum menandatangani “19 persyaratan”, tapi tindakan itu berarti “melenyapkan kebebasannya sendiri”.
Pengaduan tersebut diluar sepengetahuan Rosihan Anwar. Ia baru tahu ketika menerima surat dari International Press Institute, seminggu setelah pembredelan Pedoman, berisi keputusan untuk memecatnya sementara. Rosihan kaget, “Mochtar nih ngapain.” Rosihan kemudian mengirim surat balasan kepada International Press Institute memprotes keputusan tersebut.
“Tugas wartawan demokratis tidak mudah. Dia harus mencoba dengan berhati-hati mendorong mundur wilayah kesewenang-wenangan oleh pemerintah dan penyalahgunaan kekuasaan, dan membina suatu jenis hubungan dengan khalayak pembacanya yang akan memungkinkannya memperluas daerah pengaruh dan efektivitasnya. Betapa pun serba terbatasnya satu-satunya tempat bagi wartawan demokratis adalah membela hak-hak manusiawi dan demokratis rakyat...”
“Oleh karena keprihatinannya yang pertama bukanlah pemerintah yang tertib dan efektif, melainkan pembelaan di dalam batas-batas kemungkinan hak-hak azasi manusia. Wartawan demokratis harus melancarkan perjuangan dari daerah operasi mana pun yang disediakan baginya oleh rezim yang berkuasa. Soal yang pokok ialah dia harus berjuang. Menjadi tugas kewajiban pers yang berjiwa demokratis dan wartawan-wartawan yang mengabdi kepada cita-cita kemerdekaan pers untuk menyalakan terus api aspirasi-aspirasi demokrasi berhadapan dengan tekanan dari pihak pemerintah, dan mengobarnya dengan memperkuat kepercayaan rakyat akan hak-haknya serta kesediaannya berjuang untuk hak-hak itu...”
“Demikianlah pers akan harus bekerja dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh suatu pemerintah otoriter. Dan selamanya wartawan demokratis yakin bahwa sekalipun di dalam pembatasan itu dia dapat menyampaikan suaranya betapa pun bersifat berhati-hati, beta pun terselubungnya melewati pembatasan-pembatasan itu, maka adalah tugasnya untuk bekerja terus. Tetapi, segera dia melihat bahwa ini tidak mungkin lagi, maka adalah tugasnya menghentikan kegiatan-kegiatannya sebagai wartawan.”
Polemik tersebut menampilkan orang ketiga, Suardi Tasrif, mantan Pemimpin Redaksi Abadi. Dalam tulisannya kepada International Press Institute, ia mengingatkan bahwa keadaan darurat perang akibat pemberontakan di beberapa daerah menyebabkan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pers. Jika wartawan harus menaati ketentuan-ketentuan pembatasan dari pemerintah, tak berarti mereka berkompromi dengan prinsip-prinsip kebebasan pers dan keyakinan politiknya. Tapi ia menganggap pernyataan “19 persyaratan” sebagai dokumen bersifat politis yang apabila ditandatangi berarti berkompromi dengan prinsip-prinsip yang dianutnya dan dengan keyakinan politiknya. Menandatangi “dokumen 19 pasal”, menurut kesimpulan Tasrif, berarti wartawan bukan saja tidak dibolehkan mengritik, tetapi juga harus secara aktif mendukung pemerintah.
Polemik ini menjadi perhatian dan perdebatan di seluruh dunia melalui sidang-sidang International Press Institute dan IPI Report. Pemimpin Redaksi Nawa-I-Wagt, Pakistan misalnya, seperti dikutip dari Edward C Smith (1986:8-9), lebih berpihak ke Mochtar Lubis. Ia mengatakan pers yang bebas tidak bisa ada apabila para redaktur diharuskan menandatangani janji seperti pernyataan 19 pasal itu. Sementara Pemimpin Redaksi Democratie 61, Paris, mengakui dilema ini. “Dirasakan perlu menetapkan tapal batas antara kompromi dan kapitulasi,” katanya, “tetapi tampaknya bagi saya sangat sukar … mendapatkan rumusan yang dapat diterapkan di semua penjuru dunia …”
Pemimpin Redaksi Cape Argus dari Capetown, Afrika Selatan, menyatakan: “Apa yang cocok dalam suatu lingkungan masyarakat tidaklah cocok dalam lingkungan masyarakat lainnya … dan meskipun seluruh naluri dan simpati kita bersama Mochtar Lubis dalam “berikan aku kebebasan, atau berilah aku maut”, kita hendaknya tidak mudah menjadikannya sesuatu yang mutlak. Kebebasan itu sendiri tidak boleh dijadikan ideologi ….”
International Press Institute, yang menghimpun wartawan berbagai negara secara perorangan, akhirnya mencabut skorsing sementara keanggotaan Rosihan Anwar berdasarkan keputusan sidang umumnya di Tel Aviv. Keputusan yang memang tak bisa mengembalikan keberadaan Rosihan di International Press Institute, ia keluar dari keanggotaan.
Sebelumnya, Pedoman ditutup oleh pemerintah pada 7 Januari 1961, karena dianggap "sering memuat tulisan-tulisan yang nadanya bertentangan dengan atau melemahkan kepercayaan rakyat kepada landasan, tujuan, dan program kepemimpinan revolusi Indonesia". Pembredelan tersebut juga menyangkut seluruh "adik-adik penerbitan" yang diterbitkan Badan Penerbit Pedoman, yaitu Pedoman Minggu, Pedoman Wanita, Pedoman Anak, dan Pedoman Sport. Pembredelan yang berkaitan dengan usaha pemerintah untuk menghentikan penerbitan-penerbitan pers pendukung Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi yang dilarang dan dibubarkan bulan Agustus 1960.
"Meski saya kalah dalam pemilihan Konstituante, kemudian Partai Sosialis Indonesia dan juga Pedoman dibredel, saya tetap seorang sosialis, dan akan memperjuangkan sosialisme sampai kapanpun"*
Thursday, March 01, 2001
Bukan Rosihan Biasa
at
11:15 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


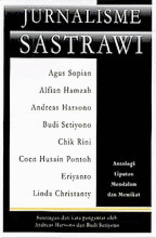


No comments:
Post a Comment