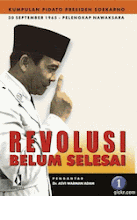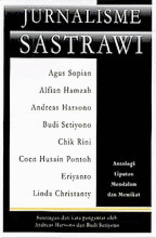SUARA gending mengalun. Kursi penonton masih kosong. Di depan panggung para pengrawit memainkan peralatan masing-masing. Cahaya lampu menyorot layar yang masih terkembang. Dekorasi panggung tertata apik dengan puncak logo bergambar mangkoro dan tulisan “Ngesti Pandowo” bertuliskan huruf Jawa di bawahnya.
Alunan gamelan berhenti sejenak, hening, lalu mengalun lagi dengan layar tergulung ke atas. Seorang penari berbaju merah bersimpuh beberapa saat, kemudian menari, tanda pertunjukan wayang dengan lakon “Srikandi Menjadi Ratu” dimulai.
Ruang Gedung Ki Narto Sabdo di kompleks Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Semarang yang berkapasitas 240 penonton, tak termasuk balkon, hanya terisi tujuh orang, yang menyimak pertunjukan dan dialog pemain yang lamat-lamat.
Cicuk Sastrosoedirdjo duduk menyendiri di antara kursi-kursi penonton yang kosong. Setiap pentas ia harus mengawasi pertunjukan sebagai pemimpin harian. Ia termasuk generasi ketiga di Ngesti Pandowo. Lelaki dari 5 bersaudara ini satu-satunya anak Sastrosoedirdjo yang terlibat di paguyuban wayang orang ini. “Saya tak dididik untuk main, sehingga tak pernah main,” ujarnya sembari menyimak pertunjukan.
Kesibukan terjadi di belakang panggung. Beberapa orang menarik-ulur kelir, mengatur sound system, dekorasi panggung, dan tata lampu. Beberapa pemain sibuk merias diri. Talok dengan sigap dan terampil memainkan tangannya; merias wajah sebagai Cembowati, istri Kresna. Soeratno memulaskan wajahnya menjadi seorang pendeta.
Soeratno dan Talok merupakan generasi pertama Ngesti Pandowo. Keduanya diambil anak oleh Sastro Sabdo, menjadi bujangan. Soeratno lahir tahun 1934, dan masuk Ngesti Pandowo delapan tahun kemudian. “Ayah saya dengan Sastro Sabdo sudah seperti kakak-beradik,” kata Soeratno.
Talok yang lahir pada 1940 sudah diambil sebagai anak Sastro Sabdo sejak berusia lima tahun. “Saya keponakan Bu Sastro Sabdo.”
Mereka menjadi bujangan bersama duapuluhan anak muda lain yang menjadi tanggungan Sastro Sabdo. Keseharian mereka seperti anak muda umumnya. Bermain, pergi ke sekolah, dan acap membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Malam hari mereka melihat pertunjukan wayang. “Bujang itu enak. Seperti keluarga, makan dan sebagainya dari Sastro Sabdho, tapi gaji utuh,” ujar Talok, yang punya nama asli Kasinem.
Mereka mengikuti ke mana pun Ngesti Pandowo pentas. Kalau berhenti di suatu tempat, rombongan diinapkan di rumah besar di kampung-kampung yang dikontrak, meski ada juga sebagian di hotel. Sebagai tempat pentas, dicarilah gedung yang mencukupi. Jika tak ada, dibuatlah tobong. Tiap malam Soeratno dan Talok menonton pertunjukan dari pinggir pilar, sekaligus mempelajari karakter tokoh-tokoh wayang, hingga mahir memainkannya.
Persiapan sudah selesai. Soeratno dan Talok bergegas menuju samping panggung, menunggu giliran tampil.
NGESTI Pandowo sendirian di Semarang. Perkumpulan Sri Wanito yang dipimpin dua bersaudara Yuk Hwa dan Kong Hwa berdiri tahun 1935, dan Wahyu Budoyo yang didirikan Sri Ani Sukarti pada 1970, sudah lama bubar. Ngesti Pandowo didirikan oleh Sastro Sabdho di Maespati, Madiun, 1 Juli 1937. Pertunjukan pertama “Endang Werdiningsih” beroleh sukses. Ngesti Pandowo kemudian menjadi kelompok wayang keliling. Dengan ukuran tonil (panggung) masih kecil dan kelir 7 ban per meter, serta busana dan gamelan sewaan, Ngesti Pandowo pentas dari satu pasar malam ke pasar malam; di Nganjuk, Kediri, Tukung Agung, Blitar, Kertosono, dan kembali ke Madiun. Sastro Sabdho kemudian diperkuat oleh Sastrosoedirdjo, Kusni, Darso Sabdho, Narto Sabdho, dan Marno Sabdho.
Keadaan susah dialami ketika zaman Jepang karena pemberlakuan jam malam dan sensor. Masalah datang ketika main di bioskop Gran dengan lakon “Kikis Tunggorono”. Sutradara Kusni diminta menghadap bagian sensor, dan diinterogasi. Lolos sensor, dan Ngesti Pandowo pun bisa pentas lagi. Keadaan susah ini bertahan hingga Jepang menyerah.
Meski masih kecil, Soeratno dan Talok sudah ikut rombongan ketika pendudukan Belanda, agresi kedua. Saat itu Ngesti Pandowo main di Delangu. Pukul 24.00 ada tentara Indonesia memberitahu bahwa gedung pertunjukan akan dibakar karena Delangu sudah diduduki Belanda, sehingga alat-alat harus segera dipindahkan. Wirjo, RM Begog, Markum, Kasidi, Truno Kartika, dan Tjipto mengangkat semua peralatan dan menitipkan ke rumah-rumah penduduk. Soeratno dan Talok hanya bisa melihat kesibukan senior-seniornya.
Oleh Sastrosoedirdjo, peralatan gamelan itu baru dibawa ke Solo ketika keadaan relatif tenang, meski di perjalanan sempat dicegat penjagaan Belanda. Keadaan genting ini membuat anak-anak wayang tak pentas selama satu tahun. Sebagian pemain pulang ke daerah masing-masing, dan sisanya menginap di rumah Sastrosoedirdjo. Talok berada di rumah Sastro Sabdho di Solo. Soeratno pulang ke rumah orang tuanya di Klaten selama setengah bulan, dan kemudian bergabung kembali ke Solo.
September 1949, akhir pendudukan Belanda, Ngesti Pandowo mendapatkan job untuk pentas di pasar malam di Stadion Semarang. Ki Narto Sabdho mengumpulkan anggotanya. Beberapa anggota di luar daerah dijemput. Karena tak semuanya kumpul, direkrut pemain-pemain baru. Mereka berangkat dengan truk yang dikawal konvoi Belanda. Di Semarang mereka mendapat asrama di kantor sosial di Jalan Kaligawe. Setelah sebulan, Ngesti Pandowo pentas di pasar malam Tegal, dan kemudian kembali ke Semarang untuk main di gedung kesenian di Dargo.
“Sastro Sabdho menginap di Peterongan. Kalau berangkat ke Dargo naik becak, iring-iringan seperti parade,” ujar Talok yang tak diizinkan main oleh polisi militer Belanda karena masih kecil.
Perlahan, sebagian anggota lainnya berkumpul kembali. Ngesti Pandowo mulai menetap, dan menata diri.
HARI itu, pukul 08.00, Walikota Semarang Hadisoebeno Sasrowerdoyo bersama kedua anaknya menemui Sastro Sabdho.
“Pak Sastro, sebetulnya Ngesti Pandowo tak layak main di sini. Sayang sekali.”
“Mau main dimana lagi?”
“Main di pusat kota.”
“Tapi bagaimana?”
“Tapi mau, Pak? Saya sanggup memberi gedung.”
“Mau!”
“Saat ini saya belum bisa beri gedung, karena biayanya besar. Saya beri brak (los) dulu.”
Ngesti Pandowo diberi tempat pementasan di belakang Gedung Rakyat Indonesia Semarang (GRIS). GRIS sebelumnya merupakan sebuah sosietet de Harmonie (gedung pertemuan Harmoni) milik seorang Belanda. Karena letaknya dirasa tak baik untuk sebuah sosietet, gedung itu dijual pada Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM). Untuk acara-acara sosietet De Harmonie dibuat gedung baru di Jalan Bojong. GRIS kemudian berpindah tangan ke Fonds Gris yang terbentuk Agustus 1945 dan beranggotakan wakil-wakil dari penduduk kota Semarang yang diketuai Hadisoebeno Sasrowerdoyo. Fonds Gris dibubarkan pada 1950, diganti Yayasan Gedung Rakyat, setelah tujuan pembelian gedung terlaksana. Pada 1953 dibangun gedung kesenian, yang kemudian dipinjamkan pada Ngesti Pandowo.
Di GRIS Ngesti Pandowo mengalami kejayaan. Mengunjungi Semarang tanpa menonton Ngesti Pandowo sungguh suatu kerugian, begitu kata orang-orang Semarang tempo doeloe. Begitu juga turis asing yang mengunjungi Indonesia. Ngesti Pandowo menjadi salah satu trade mark kota Semarang.
“Dulu meski hujan ada penonton. Gedung belum dibuka, orang-orang sudah antri beli karcis dan pesan tempat. Kalau tak pesan tempat, tak kebagian,” ujar Soeratno yang bisa memerankan tokoh apa saja; balatentara Kurawa, Petruk, Ontoseno, atau tokoh idolanya, Anoman.
Tak jarang ada penggemar yang kedanan (tergila-gila). Talok termasuk pemain yang punya banyak penggemar. “Misalnya ada orang punya hajat, kalau yang fanatik ya memanggil saya untuk main,” ujar Talok yang acap menjadi Abimanyu.
Soekarno salah satu penggemar wayang orang ini. Ada dua bambangan cakil kesayangan Soekarno yang dimainkan oleh Soetjipto dan Soewarni. Keduanya pemenang lomba tari bambangan cakil seluruh Jawa yang diadakan pemerintah. Mereka kerap diundang ke Istana Negara untuk menghibur tamu-tamu negara, serta tiap perayaan kemerdekaan Indonesia. Ketika Soewarni keluar dari Ngesti Pandowo, Talok menggantikannya.
Suatu ketika, Ngesti Pandowo pentas di Ikada. Soekarno datang, lalu meminta Ngesti Pandowo tampil di Istana keesokan harinya. Selepas tampil, Soekarno mengajak makan sembari mengobrol dan bercanda.
“Saya bangga dan gembira makan bareng Bung Karno. Bapak duduk di muka saya,” kata Soeratno yang masih ingat sajian penutup pisang ambon yang besar-besar, dan bisa dimakan untuk tiga orang.
“Saya merasa senang, merasa dihargai, ‘kok hanya Ngesti Pandowo yang dapat perhatian’. Anak-anak dan para menteri juga menonton,” kata Talok.
“Ngesti Pandowo main di Istana Bogor dan Merdeka sudah tiga kali. Di Istana Bogor tak diajak makan. Dulu masih Bu Fatmawati, tapi tak ikut. Mega, Rachma, Guruh, dan Sukma masih kecil-kecil,” ujar Soeratno.
Ada kejadian menarik mengenai Soekarno ketika memberi kuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penduduk Yogya tahu betul bahwa Soekarno akan menonton selepas mengajar. Di muka brak pentas dipadati penonton. Tiba-tiba gedeg (dinding dari anyaman bambu) jebol, Soekarno muncul dari belakang brak diikuti rombongan, lalu berkumpul dengan penonton lain. “Penonton tahunya Bung Karno bisa menghilang. Padahal Beliau tahu kalau lewat depan akan mengganggu penonton,” kata Soeratno, tergelak.
Untuk meningkatkan penghasilan pada 1959 Ngesti Pandowo masuk dapur rekaman. Sebagai langkah percobaan Ngesti Pandowo menjual naskah cerita “Kongso Adu Jago” dan “Kresno Kembang” dengan harga Rp 45.000 kepada Remaco yang merekamnya dalam bentuk piringan hitam. Karena relatif sukses, Remaco kemudian meminta lima naskah lagi untuk direkam.
Soeratno dan Talok menikmati masa jaya Ngesti Pandowo yang berdampak pada kesejahteraan anak-anak wayang. Ngesti Pandowo menanggung biaya sakit, melahirkan, maupun kebutuhan sekolah anak-anak anggota.
Zaman berubah, perlahan kejayaan itu meredup. Sesudah Kusni meninggal pada 1980, kemudian diikuti Sastrosoedirdjo pada 1984, dan Ki Narto Sabdho setahun kemudian, Ngesti Pandowo kehilangan tokoh-tokoh panutan. Bersamaan dengan itu, muncul kesulitan kronis soal manajemen dan kreativitas, hingga terlontar untuk menjual peralatan dan inventaris. Jumlah penonton makin surut hingga menyisakan 5 orang per malam. Kesejahteraan perlahan dikurangi dan kemudian dihentikan. Ketika masalah ini terselesaikan, muncul masalah lain yang bahkan lebih berat. Pada November 1996, Ngesti Pandowo digusur dari GRIS yang diambil-alih oleh pihak ketiga, Bank Pembangunan Daerah Jateng. Penggusuran ini mengejutkan masyarakat. Radio BBC menyiarkan sekaligus menyesalkannya. Anak-anak wayang kecewa, sedih, tak bisa membayangkan apakah masih bisa pentas dan mendapatkan uang.
Ngesti Pandowo kemudian diizinkan pentas di gedung TBRS, tanpa jadwal yang jelas dan tanpa background. Enam bulan berhenti pentas, Ngesti Pandowo menyewa gedung di Istana Majapahit dan bisa menggelar pentas secara penuh. Namun pengunjung telah berkurang drastis, hingga biaya sewa tak terbayar. Bantuan pemerintah daerah pun hanya bertahan 4 bulan. Terakhir, Gedung Ki Narto Sabdo di TBRS menjadi tempat pementasan, hingga kini.
“Ada surat resmi dari wali kota. Di sini dibebaskan dari sewa, tapi diberi kesempatan pentas tiga kali seminggu, Kamis sampai Sabtu,” kata Cicuk. “Susahnya kalau gedung ini dipakai untuk pementasan lain, alat-alat ini harus dipindahkan dulu, kecuali kalau untuk pementasan wayang. Padahal peralatan ini kan permanen dan sebagian sudah usang sehingga rawan.”
Namun ini pun tak mampu menaikkan kembali pamor Ngesti Pandowo. Setiap pementasan hanya dihadiri segelintir orang. praktis, kesejahteraan anak-anak wayang pun makin berkurang.
SORE itu, kesibukan terlihat di sebuah kompleks di Perumahan Kakancanmukti yang dikenal sebagai perumahan Ngesti Pandowo. Beberapa remaja bermain gitar, dan anak-anak berlari-lari. Tapi rumah bernomor 423 lengang. Tiga ekor burung tertidur di sangkar masing-masing. Di bawahnya empat sepeda tergeletak tak beraturan. Gambar Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri menghiasi dinding bercat putih yang sedikit mengelupas dengan sebuah lampu di bawahnya. Kursi tamunya juga sedikit rusak.
Seorang pria keluar dengan pakaian rapi. Kumisnya tipis, dan wajahnya menyisakan kegagahan sebagai pemain wayang. Cucunya yang berusia 5 tahun mengikuti dari belakang. Afrizal Ramadhani, nama anak itu, adalah cucu dari anak pertama Soeratno-Talok yang dititipkan di rumah pasangan ini. Enam dari delapan anak mereka sudah menikah, dan sisanya sudah mandiri.
“Saya tinggal di sini tak keluar sepeser pun, dan selang 3 bulan sertifikat keluar,” ujar Soeratno sembari menunjukkan buku catatan yang sedikit kumal. Di situ tercatat 24 April 1990 sebagai tanggal penempatan rumah itu. Sebuah foto hitam-putih bergambar Soeratno beraksi dengan penampilan Anoman dan brosur pementasan di India yang memakai gambar itu, terselip. Soeratno menunjukkan gambar itu dengan bangga.
Tak beberapa lama kemudian Talok muncul.
Soeratno dan Talok menikmati masa tuanya di rumah sederhana itu. Keseharian Talok disibukkan dengan membereskan rumah, dan sesekali mengikuti arisan atau kegiatan ibu-ibu di kampung. Soeratno biasa membaca koran atau majalah, mengisi teka-teki silang, dan sesekali memutar video compct disc. “Saya suka film detektif,” ujar Soeratno yang menikahi Talok pada 1956.
“Kami tak punya kesibukan apa-apa. Sudah lima tahun ini saya berhenti memberi kursus tari dan rias pengantin. Sudah banyak tempat kursus. Kesibukan utama kami sekarang ya mengurusi cucu,” kata Talok yang masih menyiratkan kecantikannya.
Meski usia menginjak senja, pasangan ini tetap bertahan di Ngesti Pandowo yang hanya bisa menggaji anggotanya di bawah upah minimum regional; Rp 2.000-5.000, tergantung jumlah penonton. Sejak pamor Ngesti Pandowo meredup, kehidupan pas-pasan semacam ini biasa mereka hadapi. “Meski kehidupan susah, saya serahkan pada Yang Di Atas. Dapat banyak ya dimakan, sedikit ya dimakan. Saya sendiri heran kok bisa hidup dengan penghasilan sekecil itu. Tapi kuncinya, hati tetap senang,” ujar Soeratno.
“Ini soal melestarikan budaya, panggilan seni,” kata Talok yang pernah meraih penghargaan bintang karena kesetiaannya dari Ngesti Pandowo saat peringatan 25 kelompok wayang ini.
Pukul 17.00. Sebentar lagi, sebuah mobil akan menjemput anak-anak wayang itu menuju tempat pementasan.*
Saturday, November 09, 2002
Anak Wayang Menggiring Angin
Permalink | 2 comments |
Monday, November 04, 2002
Superdirector: One Man Show
DIA berwajah bayi. Perawakannya kecil, tapi badannya gempal. Kulitnya rada gelap. Pakaiannya hitam-hitam. Dia duduk bersila di ruang tamu yang terasa adem, menikmati video musik dari MTV.
“Saya ini termasuk generasi MTV, generasi yang lahir ketika MTV lagi jaya-jayanya,” katanya, menyebut saluran khusus musik MTV yang muncul pada 1981.
Ketika itu, dia bukanlah siapa-siapa. Dia seperti remaja kebanyakan yang suka hal-hal baru. Kebetulan saja dia anak diplomat, yang harus hidup berpindah-pindah negara. Saat itulah dia menikmati MTV, dan takjub musik bisa berpadu dengan gambar. Musik ternyata tak hanya bisa didengar, tapi juga dilihat mata. Baginya, itu sesuatu yang baru. “MTV saya lihat sebagai satu revolusi kebudayaan pop. Fenomenal,” katanya.
Saat itu jauh dari pikirannya untuk menjadi sutradara video musik, meski dia sudah iseng bikin video musik sendiri. Dia membuatnya ketika kelas dua SMA di Srilanka, negara tempat ayahnya, Mohammad Saleh, bertugas pada 1983. Temannya, Edi Setiawan, punya kamera home video keluaran terbaru dari Sony. Karena mengidolakan Duran-Duran, muncul keinginan membuat video musik. Kebetulan salah satu video musik Duran-Duran berlokasi di Srilanka, jadi lokasinya sama. Ada dua lagu Duran-Duran yang mereka garap; Lonely in Your Nightmare dan Hungry Like The Wolf. Aksi mereka yang cuma berjalan-jalan direkam dalam pita kaset Betamax. Setelah selesai, mereka mengeditnya secara manual; dari VHS ke VHS.
“Kalau mau ngomong inspirasi bikin video musik, bukan (Steven) Spielberg, bukan orang film, malah Duran-Duran. Karena saat itu mereka bikin musik video yang benar-benar tergarap,” katanya.
“Saat MTV baru keluar, yang lain (video musiknya) cuma di studio. Ada dua yang fenomenal; Michael Jackson dan Duran-Duran. Saya suka Duran-Duran karena video klipnya lebih berpetualangan, di negara antah berantah segala macem, yang fantasi. Kalau Micheal Jackson ‘kan lebih dance.”
Srilanka jadi negara terakhir ayahnya bertugas di luar negeri setelah sempat ditempatkan di Iran dan Yugoslavia. Ayahnya pensiun, dan mulai menetap di Jakarta. Tapi, tiga tahun kemudian, ketika dia menginjak tingkat dua di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, Jakarta, ayahnya meninggal dunia. Keluarganya kehilangan satu-satunya sumber pencari nafkah. Untuk menambah biaya kuliah, dia mengerjakan poster-poster komikal di toko komik DEHA di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dia menggambar tokoh komik terkenal Superman, yang kemudian dipajang di dinding toko.
Suatu ketika, pada 1991, Edward Buntario, art director di Creative Concepts, sebuah perusahaan periklanan di Jakarta, tertarik dengan poster-poster itu dan ingin berkenalan dengannya.
“Nama saya Rizal Mantovani.”
“Kamu yang gambar ini, ya?”
“Iya.”
“Mau nggak kerja di kantor saya jadi grafis desainer?”
“Waduh Pak, susah banget. Saya sekarang lagi kuliah.”
“Ya udah part time aja lah.”
“Part time? Ya, boleh deh.”
Keesokan harinya, dia diperkenalkan dengan Richard Buntario, adik Edward yang punya perusahaan itu. Richard memintanya menggambar. Richard juga menanyai kesukaannya, yang dia jawab menonton MTV dan Sesame Street, serial televisi karya Jim Henson, yang juga memopulerkan The Muppet Show. Sejak pemunculannya pada 1970 Sesame Street sukses besar dan menjadi program yang sangat diminati anak-anak sepanjang sejarah pertelevisian.
“Jadi bahasa televisi kita nyambung, sama. Itu membuat saya tertarik untuk merekrut dia,” kata Richard.
Di Creative Concepts pekerjaannya membuat story board untuk keperluan iklan. Setahun kemudian, ketika Richard Buntario mendirikan perusahaan baru bernama Broadcast Design Indonesia (BDI), dia ikut bergabung. Selain membuat iklan, BDI juga memanfaatkan keberadaan televisi swasta dengan membuat acara televisi. Di sinilah dia kemudian dilibatkan sebagai asisten Richard Buntario. Dia terlibat dalam penggarapan Bursa Komedi untuk RCTI. Salah satu tokohnya, sebuah boneka bernama Bob yang jadi pasangan pelawak Krisna Purwana, dibikinnya dan juga dimainkan olehnya. Tokoh itu lahir karena kesukaannya pada serial pendidikan Sesame Street ketika kecil.
“Saya ingat Sesame Street ketika buat acara teve, yang humor tapi kepengin beda. ‘Apaan ya, boneka saja kali ya.’ Karena ‘kan bikin orang tertawa saja susah. Ada pepatah film di Inggris, dying is easy, comedy is hard. Mati itu lebih gampang daripada buat orang ketawa,” katanya.
“Saya memang senang Sesame Street. Jadi boneka-bonekanya Jim Henson itu saya senang banget, seperti Kermit dan Ernie. Dulu saya nonton Sesame Street tiap hari. Dulu Iran punya tiga channel, salah satunya pasang Sesame Street.”
Setelah bikin acara televisi, dia ingat kesukaannya nonton MTV. Dia lalu menonton beberapa video musik di TVRI. “Saya lihat video klip-video klip di teve pada 1991 itu, kecuali video klip Jay Subiakto, kalau syutingnya nggak di taman ya di Ancol. Isinya begitu melulu,” katanya.
Dia melihat video musik Jay Subiakto lebih berwarna etnik. Warna pop belum tergarap. Warna inilah yang kemudian dia tawarkan kepada Richard Buntario.
“Chard, kita bikin video musik, yuk.”
“Ayo, ayo. Cuma materinya mana. Ini ‘kan susah, dan kita bukan di dunia itu.”
Tawaran kali pertama datang dari teman Richard untuk membuat video musik dangdut Suka-Sukaku yang dinyanyikan Helvy Mariyand. Meski tak mendapat respon luar biasa, hasil dari pekerjaan pertama ini mereka tawarkan ke Musica Studio. Indrawati Widjaja, direktur produksi, menyambutnya dan menawarkan pembuatan video musik rapper Iwa K berjudul Kuingin Kembali. Ketika ditayangkan, video musik ini dianggap sebuah terobosan baru dalam industri musik Indonesia. Sejak itu BDI menerima banyak permintaan untuk pembuatan video musik yang dikerjakan Richard bersamanya sebagai asisten.
“Sebagai asisten dia rajin, setia, disiplin, dan sangat mendukung sekali sehingga bisa diandalkan. Kalau saya nggak masuk sehari-dua hari dia bisa melanjutkan pekerjaan saya. Benar-benar asisten yang diidealkan banget oleh setiap sutradara,” kata Richard.
Kerja sama itu berbuah manis. Keduanya meraih gelar sutradara terbaik dalam ajang Video Musik Indonesia 1995 pada acaranya yang perdana melalui video musik Cuma Khayalan-nya Oppie Andaresta. Sejak itu duet Richard Buntario-Rizal Mantovani mulai dikenal, yang lebih populer disebut Duo.
SEPAGI ini, di pertengahan Januari 1994, dia sudah berada di kantornya. Richard Buntario bertemu dengannya sebelum masuk ruangan.
“Kok, tumben datang pagi-pagi?”
“Oh, ya, nih gue lagi kepengin menyelesaikan beberapa tugas.”
Maka, keduanya pun berpisah, masuk ke ruangan masing-masing. Tak berapa lama, dia kembali masuk ke ruangan Richard. Dia menangis.
“Kenapa lu nangis, Zal?”
“Gila nih ....”
“Kenapa?”
“Gue tadi keluar rumah Ria, tahu-tahu ketemu temannya, Aldi. Aldi sudah teler-teler gitu. Gue pikir cuman ‘Wah sakit’ gitu. Nggak tahunya tuh lagi saat-saat sebelum dia mau mati. Gue juga baru tahu.”
“Poin lu apa?”
“Poinnya ada orang mati di rumah Ria sekarang, dan gue mesti balik ke rumah Ria.”
“Ya udah, pergi saja.”
Dia bergegas menuju rumah Ria Irawan, kekasihnya, yang terkenal sebagai pemeran Juminten dalam Lika-liku Laki-Laki di RCTI. Tiba di sana sudah ada ibu Ria, Ade Irawan, dokter, dan polisi. Siangnya, ditemani petugas, dia dan Ria datang ke rumah mertua Aldi untuk mengabarkan kematian Aldi.
Aldi, bernama lengkap Raden Mas Rifardi Soekarno Putro, yang dikenal sebagai seorang pengusaha muda ditemukan meninggal dunia karena overdosis di lantai bawah rumah Ria Irawan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kematian Aldi mendapat perhatian luas bukan saja karena melibatkan seorang artis, tapi juga karena mulai dikenal sejenis obat bius bernama ecstasy.
Beberapa jam sebelum Aldi meninggal dunia, Rizal Mantovani yang masih tercatat sebagai mahasiswa semester akhir di Universitas Trisakti berada di rumah Ria. Dia menjadi saksi kunci, dan akan terus dimintai keterangan oleh polisi. Dia akhirnya datang ke kepolisian sektor Metro Cilandak, dan bertemu dengan polisi R.E. Nasution.
“Pak, ada yang bisa saya bantu?”
“Kamu jangan ke mana-mana!”
“Saya nggak kemana-mana. Kalau perlu saya di sini.”
“Kamu mau di sini?”
“Nggak apa-apa.”
“Oke deh. Ya udah di mana?”
“’Kan bisa di kamar bapak.”
Dia menginap di ruang kerja Nasution selama beberapa hari. Keputusan ini dia ambil untuk membantu kerja polisi yang berarti mempercepat penuntasan kasus tersebut. Dia juga enggan pulang karena hadangan wartawan di luar rumahnya yang ingin mendapat informasi darinya.
Sebagai partner, Richard Buntario memahami betul apa yang dialami rekan kerjanya. Ia melihat kasus itu amat menganggu pikiran Rizal, juga pekerjaannya. “Dia merasa benar-benar capek, karena sorotan pers dan ditanyai pertanyaan serupa terus. Dia terus dihantui ini dan itu, padahal dia tak terlibat. Jadi dia tetap kerja, tapi kreativitasnya nggak maksimal. Dia sedang lesu,” kata Richard.
Untung, ini tak berlangsung lama. Sebulan kemudian dia bisa kembali bekerja. Dia juga bisa meneruskan hubungan asmaranya dengan Ria Irawan, hingga setahun kemudian berpisah. Masih bersama Richard, dia menggarap variety show bertajuk Intermezzo untuk ANteve dan juga beberapa video musik. Duo ini kembali berkibar ketika pada 1995 meraih MTV Asia Viewers Choice Award dalam ajang MTV Music Awards berkat video musik Sambutlah yang dibawakan Denada. Dia sendiri dinilai Vista, sebuah majalah musik dan televisi (kini sudah almarhum), sebagai salah satu dari 20 orang paling berpengaruh di industri televisi Indonesia pada tahun yang sama.
Dalam berkarya dia menggunakan konsep kebudayaan pop. Baginya, kebudayaan pop adalah sesuatu yang memiliki idiom-idiom, bahasa-bahasa, simbol-simbol, yang dapat dimengerti khalayak seluas-luasnya.
“Ini pengaruh dari waktu remaja. Saya selalu dikelilingi benda-benda yang sifatnya pop. Termasuk komik. Dan komik bukan Superman saja, tapi juga Gondala, Godam, Aquanus. Itu ‘kan kebudayaan pop. Teh botol ‘kan kebudayaan pop,” katanya.
Kebudayaan pop sangat dekat dengan dirinya. Dia suka menonton film –dia tak mau melewatkan midnight show. Dia suka makan junkfood dan minum Coca-Cola. Dia juga kolektor komik Superman.
“Gue pernah menemani dia di Los Angeles, mencari komik, sampai habis US$200. Nyari sampai sore. Bukan cuma di toko tapi juga di rumah-rumah orang kolektor. Komik yang dia cari macam-macam. Dia cari edisi lama, tahun lama, dan asli. Pokoknya kalau dia pulang, kopernya penuh buku, komik, mainan, dan majalah,” kata Eko Kristianto, sutradara video musik, rekan Rizal.
Kegemarannya pada komik berawal ketika dia masuk sekolah internasional di Iran yang menuntutnya mahir berbahasa Inggris. Ayahnya memberinya stimulasi dengan berbagai bacaan. Suatu ketika dia pergi ke toko buku yang hendak tutup. Kakaknya memintanya untuk memilih salah satu komik. Dia mengambil satu eksemplar, yang ternyata komik Superman. Ketika dia membacanya, dia merasa bisa memahami isinya meski dengan kemampuan bahasa Inggris yang seadanya. Karena cerita itu bersambung, dia harus mengikutinya pada bulan berikutnya, lagi, dan lagi. Lalu, dia mulai mencari komik kreasi Joe Shuster dan Jerome Siegel pada 1938 itu dari edisi lama, hingga jadi kolektor.
“Waktu kita ke Eropa, syuting, dia punya sekoper penuh buku. Orang-orang itu kalau ke sana, jalan, yang dicari baju, sepatu. Rizal nggak, ke toko buku, ngumplek aja. Dia bisa berjam-jam di toko buku. Akhirnya setiap pulang dari luar negeri dia pasti punya sekoper penuh buku,” kata Alfani Wiryawan, direktur program dan produksi di Avant Garde Productions.
Dia suka membeli dan membaca buku pop art, video musik, make up, dan buku-buku yang berhubungan dengan profesinya. Dia sadar dia belajar secara autodidak. “Bisa dibilang saya ‘kan salah jurusan. Mestinya masuk sekolah film, tapi ternyata nasib membawa saya menjadi begini. Seandainya saya disuruh mundur balik, mungkin saya akan sekolah film,” katanya.
Buku-buku itu bersama koleksinya yang lain ditatanya rapi. Di kantornya dia dikenal suka beberes. Sering terdengar suara palu dari ruangan kerjanya, yang menunjukkan dia lagi mengubah desain interior.
“Ada kesan dia one man show, apa-apa dia sendiri, bisa. Nggak salah kalau dia mengidolakan tokoh komik Superman. Dia itu Superman,” kata Oleg Sanchabakhtiar, sutradara video musik dari Planet Design Indonesia.
“Dulu, mau bikin video musik, kadang cuma dia sendiri yang tahu,” kata Eko Kristianto.
“Karena belum ada orang yang bisa, sesuai dengan dia, targetnya dia, mengimbangi dia. Jadi kalau dia nyuruh, daripada lama mending turun sendiri. Tapi one man show-nya lebih pada syuting,” kata Alfani. “Mungkin dia pikir biar cepat. Tapi anak-anak yang habis kerja sama Rizal biasanya bukan jadi tambah bego. Mereka juga tambah pinter.”
Oleg, Eko, dan Alfani—tiga rekannya semasa di BDI—mengatakan belajar banyak darinya, orang yang mau berbagi ilmu, tanpa terkesan menggurui.
Suatu ketika, di tahun 1996, dia keluar dari BDI. Alasan dia klise, “Tiap orang ingin berkembang.”
“Mungkin dia merasa sudah saatnya mencari, menjajaki hal baru, dan merasakan karya sendiri. Bagaimana pun di BDI dia merasa di bawah bayangan saya. Mungkin dia susah berkembang,” kata Richard Buntario.
Setelah itu, satu per satu karyawan juga memutuskan untuk keluar, termasuk Alfani, Oleg, dan Eko. Alasannya macam-macam, dari soal manajemen, perbedaan visi, sampai faktor kekeluargaan yang mengendur. Belasan karyawan itu kemudian berkumpul untuk mendirikan sebuah rumah produksi baru.
Dia tak ikut di dalamnya, karena ingin melanjutkan kuliah yang sempat terhenti. Tapi, teman-temannya berupaya mengajaknya serta ke dalam rumah produksi yang belum punya nama itu. Dia akhirnya bersedia ikut, dan bahkan mengusulkan nama Avant Garde Productions, nama yang kemudian dipakai hingga kini. Di Avant Garde dia bisa mewujudkan konsep-kosepnya lebih bebas. Selain tetap menggarap video musik, dia menciptakan sekaligus menyutradarai serial komedi situasi Satu Atap dan Gen-X, keduanya untuk ANTeve.
“Di Avant Garde cara kerjanya tak berubah. Lebih Superman. Lebihlah karena dia jadi one man show, dulu ‘kan duo,” kata Oleg Sanchabakhtiar.
1996. Dia didatangi Mira Lesmana. Mira baru saja keluar dari Katena, sebuah perusahaan periklanan di Jakarta. Mira juga pernah membantu Anak Seribu Pulau-nya Garin Nugroho, yang mempertemukannya kembali dengan Riri Riza dan Nan Triveni Achnas. Dari situ, Mira yakin bisa bikin film. Untuk itulah Mira mendatanginya yang tentu saja amat mengejutkan.
“Kenapa saya? Saya ‘kan sutradara music video?”
"Sebenarnya cita-cita kamu yang paling ultimate apa sih?"
"Bikin film."
"Ya sudah, mau nggak bikin film?"
"Gila apa, nggak ngerti 35 mm, nggak ngerti seluloid, nggak pernah tahu, saya nggak mau. Saya nggak!"
"Sudahlah, kita ‘kan sama-sama, berempat, kita punya teman-teman. Dan gue tahu elu bisa"
Mira juga mengajak Riri Riza dan Nan Triveni Achnas.
"Benar, yakin nih?"
Mira berusaha meyakinkannya. Dia pun berpikir tawaran tak datang dua kali. Dia menerimanya. Syaratnya, dia dibantu, karena awam.
Lalu, meluncurlah Kuldesak ke pasaran pada 1998. Kehadiran Kuldesak mengobati kerinduan publik terhadap film Indonesia, yang makin sepi karena aturan pembuatan yang ketat dan biaya produksi yang mahal. Beberapa kritikus film sempat menafsirkan film ini dipengaruhi Pulp Fiction karya Quentin Tarantino. Tapi, keempat sutradara ini berkali-kali bilang bahwa Kuldesak lahir karena pengaruh buku Robert Rodriquez berjudul Rebel Without A Crew.
Rodriquez adalah sutradara Meksiko yang sukses di Hollywood. Film pertamanya El Marachi, yang ia buat dengan peralatan sederhana, mendapat sambutan dan bahkan mengantarkannya ke Hollywood. Lalu, berturut-turut ia membikin film Desperado, From Dusk Till Dawn, The Faculty, dan Spy Kid. Melalui bukunya Rodriquez membagi pengalamannya membuat film dengan fasilitas terbatas. Ia juga menyuguhkan pelajaran-pelajaran praktis yang amat berguna bagi pembuat film amatir. Ada bagian khusus dalam buku itu yang diberinya judul “The Ten Minute Film School.”
Bagi Rizal Mantovani, pengalaman pertama membikin film ini amat menegangkan. Ada perasaan grogi pada awalnya. Tapi, dukungan teman-temannya membuat perasaan itu perlahan lenyap. Ini jadi momen yang amat menentukan dalam perjalanan kariernya. “Ya akhirnya saya merambah dari video musik ke dunia yang tadinya saya nggak kalah cintanya: film,” katanya.
Selepas itu, dia melanjutkan aktivitasnya sebagai sutradara video musik. Acap dia bertemu dan bertukar pikiran dengan teman-temannya yang berprofesi sama seperti Jose Poernomo, Jay Subiakto, Dimas Djajadiningrat, Oleg Sanchabakhtiar, Eko Kristianto, dan sebagainya. Lalu, muncullah ide dari Jose untuk membikin wadah bernama Music Video Makers (MVM). Bentuknya informal, hanya untuk bertukar pikiran saja. Tapi, MVM kemudian tak berjalan, meski sempat pula terlontar keinginan untuk membuat film.
Suatu hari dia diminta Erwin Arnada, pemimpin redaksi Neo, sebuah majalah gaya hidup, untuk menyumbang tulisan tentang film. Dia mengelak.
“Aduh, kayaknya saya nggak berkompeten menulis tentang film.”
“Ya udahlah Zal, lu bantuin kita bikin artikel apalah.”
“Apa aja?”
“Apa saja deh. Ntar gue lihat, kalau bagus, masuk.”
Dia menulis mengenai legenda-legenda urban di Jakarta, seperti Si Manis Jembatan Ancol, Suster Ngesot, dan Pastur Jeruk Purut. Dalam artikelnya yang berjudul “Legenda-legenda Urban di Jakarta” itu dia memasukkan sekitar 15 legenda.
Di luar dugaan, dua tahun kemudian, Rexinema menawarinya membuat film. Rexinema hendak membikin 12 telesinema untuk stasiun televisi baru TransTV, yang semuanya digarap sutradara video musik. Dia lalu mengembangkan artikelnya di Neo untuk filmnya yang kemudian diberi judul Jelangkung.
Dia minta Jose Poernomo untuk membantunya dalam penyutradaraan. Skenario ditulisnya bersama Jose dan scriptwriter Adi Nugroho. Sejumlah pemain yang tak dikenal publik direkrut agar penonton tak dibebani pencitraan karakter tertentu. Pembuatan film dilakukan dengan menggunakan Betacam, kamera yang biasa dipakai untuk membuat video musik. Syuting dimulai pada Desember 2000. Setingnya di pinggiran Jakarta. Waktu syuting cepat, hanya sepuluh hari. Dengan penyiasatan itu biaya produksi bisa ditekan minim, sekitar Rp 200 juta.
Setelah film selesai dibuat pada Mei 2001, muncul keinginan untuk menayangkannya di layar lebar. Pertimbangannya, film ini punya nilai sinematik yang beda dari sinetron, baik dari pendekatan visualnya maupun cara bertuturnya. “Dengan harapan kita bisa masukin proyektor, pasang cuma di satu bioskop doang di Pondok Indah Mall,” katanya.
Meski awalnya tak menanggapi, Studio 21 di Pondok Indah Mall akhirnya memutar film berdurasi 102 menit ini. Di luar dugaan, antrean penonton meluber, bahkan banyak yang tak kebagian karcis. Karena laku, film ini pun dialihkan ke dalam format pita seluloid 35 milimeter, dan dibuat 20 kopi agar bisa diputar serentak di banyak kota dengan cara konvensional.
Jelangkung menjadi film yang diburu penonton. Jelangkung juga menjadi film nasional pertama yang menembus pertunjukan midnight sampai 13 kali putar di Pondok Indah Mall. Pun jadi film nasional pertama yang diputar di empat layar sekaligus di beberapa bioskop karena bludakan penonton.
Keberhasilan Jelangkung amat mengejutkan, meski kisah misteri bukanlah tema baru dalam perfilman Indonesia. Pada 1970-an dan sesudahnya, penonton Indonesia disuguhi film-film bertema sejenis. Ada Beranak Dalam Kubur, Bayi Ajaib, Akibat Guna-Guna Istri Muda, Arwah Penasaran, Dendam Jumat Kliwon, dan sebagainya. Belakangan, RCTI juga menayangkan Si Manis Jembatan Ancol yang merupakan remake dari film layar lebar dengan judul sama produksi Sarinande Film pada 1973.
Meski tak tahu kenapa filmnya diminati, dia senang melihat antrian panjang penonton. Inilah momen yang amat berkesan baginya, setelah pemutaran kali pertama Kuldesak.
Buah dari keberhasilan Jelangkung terus berlanjut ketika dia bisa bertemu dengan Michael Bay, sutradara sekaligus produser film di Hollywood.
Semuanya berawal dari Variety, majalah bisnis hiburan yang jadi pegangan orang-orang perfilman. Pada edisi November 2001, Variety menurunkan artikel tentang sukses instan Jelangkung sebagai headline di rubrik yang mengulas industri hiburan Asia. Roy Lee, produser dari perusahaan Dimensions Film, divisi dari Miramax di Hollywood, membaca artikel itu dan tertarik. Miramax adalah distributor film berbasis di Amerika Serikat yang banyak memasok film asing (non-Amerika Serikat). Lee lalu mengirim surat elektronik ke Erwin Arnada, produser eksekutif dari Rexinema, yang meminta satu kopi Jelangkung. Permintaan itu dipenuhi dengan mengirimkan film dalam format DVD tanpa teks terjemahan.
Meski kesulitan mengikuti jalan cerita, Lee memuji penyutradaraan Jelangkung. Ia menyatakan ingin membeli film itu. Lee juga memperlihatkan Jelangkung kepada Julien Thuan dari United Talent Agency (UTA), yang selama ini mewakili bintang ternama seperti Harrison Ford dan Jim Carrey. Thuan mengatakan suka pada Jelangkung dan bersedia membantu mengurus kontrak untuk pembuatan ulang.
Ketika tawaran itu datang, Rizal Mantovani tentu saja terhenyak, kaget. Bukankah di Hollywood lebih banyak orang jago bikin film? Tapi, sekali lagi, kesempatan tak datang dua kali. Dan berangkatlah dia bersama Jose Poernomo ke Los Angeles untuk melihat kemungkinan kerja sama. Di Hollywood pula dia bertemu dengan Michael Bay, pemilik perusahaan film Platinum Dunes. Kesempatan itu juga dimanfaatkannya untuk menjual konsep film.
Dua kali kunjungan mereka ke sana membuahkan hasil. Michael Bay mengajak kerja sama pembuatan film horor The Well untuk penonton di Amerika. Bay melibatkan pula Radar Films untuk produksi ini. Selain itu, proposal penggarapan ulang Jelangkung yang menjadi The Uninvited masih dibahas di beberapa perusahaan film, antara lain Paramount dan FOX Seachlight.
"The Well masih dalam proses. Kita baru dapat penulisnya, tapi saya belum bisa ngomong karena itu masih confidential. Insya Allah Januari saya ke sana untuk … take,” katanya.
“Entar saya akan menyutradarai bareng Jose dengan supervisi dari mereka. Dan kita juga akan supervisi ceritanya.”
Selain The Well, dia juga sedang mempersiapkan penggarapan film layar lebar berjudul Dan yang bekerja sama dengan Multivision Plus di Jakarta. Awalnya film itu akan diberi judul Reaksi Kimia, tapi diurungkan. Nama Dan diambil dari judul lagu Sheila On 7. Ia sudah membicarakannya dengan Eros, personel Sheila On 7 yang menulis lagu Dan. Nantinya lagu itu akan dibawakan dengan alunan suara penyanyi cewek.
”Ceritanya tentang cinta, cinta untuk 22 tahun ke ataslah. Saya lihat kalau anak muda, ABG, ‘kan nanyanya Siapakah saya? Cari identitas. Saya rasa umur 23-24 ke atas bukan nanya itu lagi, tapi Di mana saya?” katanya.
Dan baru menyelesaikan pembuatan script dan pemilihan pemain. Dia berkolaborasi lagi dengan scriptwriter Adi Nugroho untuk film bertema urban-drama ini. Film dengan seting kota Jakarta ini akan menjadi film layar lebar pertama yang dia sutradarai sendiri.
“Sekarang lagi break dulu. Jadi script lagi kita selesaikan, casting baru selesai. Mudah-mudahan Desember kali ya,” katanya.
“Setelah Dan dan The Well baru saya akan mengerjakan film I-sinema saya. Insya Allah sama Rayya (Makarim) tahun depan. Konsep sudah ada tapi saya belum bisa ngomong sekarang.”
Dia ikut bergabung dengan I-sinema, suatu gerakan yang dilakukan 13 pembuat film yang sebagian besar sutradara muda untuk menyiasati problem perfilman Indonesia. Melalui I-sinema ini beberapa film lahir, seperti Bendera garapan Nan Triveni Achnas, Eliana eliana (Riri Riza), dan Lima Sehat Empat Sempurna (Richard Buntario).
Tapi, dia tak ingin muluk-muluk di sini. Seperti yang diterapkan dalam proses berkeseniannya, dia suka pada pendekatan pop culture, dan berorientasi pasar.
“Misi saya membuat sesuatu yang bisa diterima masyarakat luas. Kalau mendapat hati dari mereka saya sudah senang. Dan itu berat,” katanya.
DUA poster besar terpasang di ruangan ini; Reservoir Dogs dan Pulp Fiction, keduanya karya sutradara Quentin Tarantino. Satu stiker kecil menempel di kaca nako bertuliskan “Dreamscape Indonesia.” Dia masih duduk bersila. Sesekali saja dia mengubah posisi duduknya agar terasa lebih nyaman. Sesekali pula dia menengok televisi di sudut ruangan yang masih menayangkan lagu-lagu dari MTV, menikmati sejenak waktu luangnya yang sempit.
Dia baru saja menyelesaikan pembuatan video musik Chrismansyah Rahadi atau lebih populer dengan nama Chrisye berjudul Kangen yang dinyanyikan bareng Sophia Latjuba. Dia biasa mengerjakan semuanya sendirian; dari proses pengambilan gambar, editing hingga video musik siap ditayangkan di televisi. Selepas Chrisye beberapa pembuatan video musik menunggu.
“Dia itu jenius di bidang ini, audio visual. Dia bisa membuat beberapa macam karakter. Seperti dia bisa bikin dangdut, pop, jazz, mau apa bisa,” kata Oleg Sanchabakhtiar.
“Kalau syuting, gilanya, dia suka kolosal. Dia ngatur kameranya, dia ngatur lighting, artistiknya, ini-itu, bisa begitu. Dan dia produktif. Tiap tahun pasti ada karyanya yang kategori the best, di dunia musik Indonesia ya, bukan ajang video musik indonesia.”
“Rizal itu sangat komersil. Lagu apapun, musik apapun, dia bisa jadi komersil. Lagu jelek pun bisa jadi bagus,” kata Eko Kristianto. “Yang nggak gue suka dari dia, semuanya pakai emosi. Misalnya dia ada masalah, itu bisa berpengaruh pada ritme kerjanya. Tapi, sekarang ‘kan dia freelance, dia jadi tegar, bisa berdiri sendiri. Dia jadi lebih dewasa.”
Dia kini memang mandiri, menempati rumah yang agak sempit di daerah Pejompongan. Sudah beberapa bulan dia berkantor di sini, setelah Maret lalu resmi keluar dari Avant Garde Productions, rumah produksi yang ikut dibangunnya pada 1996. Dia lalu membuat tim kerja bernama Dreamscape Indonesia untuk pekerjaan video musik.
“Saya merasa di Avant Garde masih berpartner dengan teman. Jadi dalam segi profit saya masih berbagi dengan orang lain. Saya merasa, kenapa nggak buat saya sendiri sekalian, nggak usah ada partner, ‘kan pasti secara finansial bisa saya nikmati sendirian. Jadi saya bertekad untuk bikin Dreamscape,” katanya.
Tapi, dia tak hendak membuat Dreamscape menjadi besar. Dia hanya mempekerjakan enam orang. Lainnya, dia sewa per proyek, termasuk kru, peralatan syuting, dan editing.
“Konsepnya sama kayak di Broadcast Design Indonesia dan Avant Garde. Cuma konsep dasarnya adalah kecil. Saya nggak mau membuat ini jadi besar. Jadi memang dia selalu jadi perusahaan kecil,” katanya lagi.
Dreamscape adalah rumah produksi untuk video musik, sesekali saja menggarap iklan. Bahkan, untuk iklan dia kerap disewa rumah produksi lain. Dreamscape juga tak hendak menggarap acara televisi. Dreamscape hanya menjual jasa kemampuannya sebagai sutradara video musik. Bukan hal aneh bila orang lebih melihat nama sutradara ketimbang nama rumah produksinya. Dan di bidang video musik dia jagonya. Dari 1992 hingga kini setidaknya dia sudah menggarap hampir 200 video musik dan beberapa iklan televisi.
Di Dreamscape dia sendirian, tanpa partner, seperti juga dia sendirian menikmati masa lajangnya.
“Kalau dibilang yang bukan luck-nya dia, dia ‘kan luck ya, apa-apa punya, itu soal jodoh,” kata Oleg Sanchabakhtiar.
“Rizal cuma butuh orang yang sayang sama dia. Tapi, kebanyakan cewek yang dekat semuanya jahat sama dia. Rizal punya semua hal tapi cuma di situ doang yang kurang,” kata Eko Kristianto.
Dulu dia bisa stres ketika ditanya tentang pasangan hidup. Kini, dia bisa menerima keadaan sembari tetap menyibukkan diri dengan bejibun aktivitas. Dan toh, dia masih punya ibu, Widji Andari yang sudah lama menjanda, yang begitu peduli padanya, dan amat berarti baginya.
“Bagaimanapun ibulah yang memberikan saya suport selama ini. Kalau nggak ada beliau dan tidak bersama beliau, saya rasa nggak bisa bekerja,” katanya.
“Dia dekat sekali sama ibunya. Sampai sekarang apa-apa untuk ibunya. Dia ‘kan anak bungsu. Dia dulu manja banget sama ibu dan kakaknya. Tapi, dia paling sebal kalau ada saudaranya datang ke kantor,” kata Eko.
Lalu, dia bergegas. Kesibukan menjadi rutinitas kesehariannya. Ada acara syuting. Lalu, dia harus mengedit. Mungkin lusa dia pergi keluar negeri. Bukankah dia generasi MTV, generasi yang tak lagi merasa atau terkekang oleh “memiliki tanah air yang satu”—atau dalam istilah Joshua Meyrowitz, penulis buku Understanding The MTV Generation, generasi no sense of place. Di mana pun dia mendapatkan kesempatan untuk unjuk kebolehannya sebagai sutradara, itulah tanah airnya.*
Permalink | 2 comments |